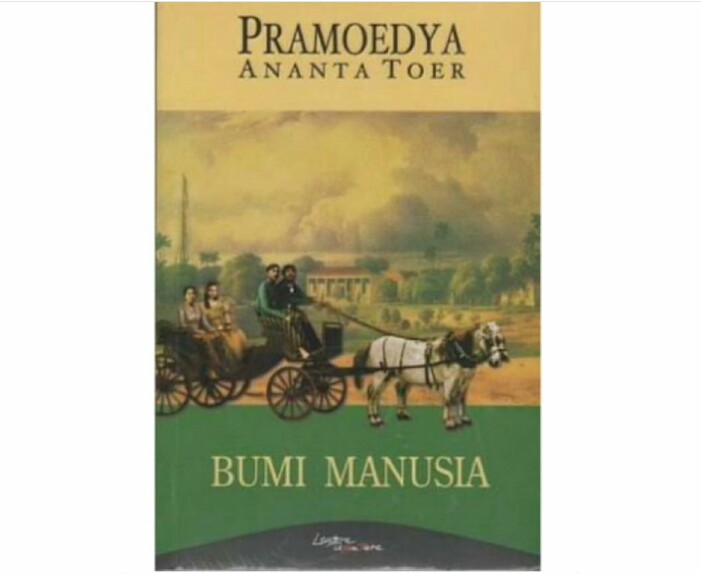Saya jujur tidak mengerti kaum tua mana yang disasar Bung Iqbal dalam tulisannya ‘Bumi Manusia’ dan Congkaknya Kaum Tua. Apakah ia menyasar cuitan Ariel Heryanto, atau kaum tua yang mana, tidak jelas juga. Pun saya tidak dalam posisi memberi pembelaan terhadap cuitan tersebut atau entah siapa pun yang Bung Iqbal tuju. Namun melihat polemik diangkatnya Bumi Manusia ke sinema menjadi hanya soal kecongkakan kaum tua rasanya terlalu mensimplifikasikan persoalan sesungguhnya.
Satu hal yang luput dari artikel Bung Iqbal adalah bagaimana ia terlalu gegabah dengan tidak melihat persoalan ini dalam konteks perfilman Indonesia. Apa yang dipikirkan Bung Iqbal sehingga ia bisa begitu optimistis bahwa difilmkannya Bumi Manusia akan dapat memperkenalkan gagasan Pram, saya tidak tahu. Saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang menjelaskan hubugan antara film AADC (2002) dengan tren kegemaran remaja terhadap puisi.
Apakah tren tersebut kemudian menciptakan satu generasi baru yang dibentuk oleh budaya membaca ataukah tren tersebut kemudian berlalu begitu saja seperti yang sudah-sudah, entahlah. Saya tidak memahami kenapa Bung Iqbal menganggap tren tersebut sebagai suatu keberhasilan yang perlu digarisbawahi.
Sebaliknya, saya justru membaca bagaimana membawa Pram ke layar bioskop bukanlah ide yang tepat untuk mengenalkan gagasan-gagasan beliau. Garin Nugroho dan Dyna Herlina dalam Krisis dan Paradoks Film Indonesia (2013) menjelaskan betapa problematisnya persoalan bioskop di Indonesia. Terlepas dari data-data yang terpaut waktu cukup jauh, kita masih mengalami persoalan yang sama perihal bioskop: ia masih menjadi kemewahan kota-kota besar.
Permasalahan lebih lanjut diuraikan oleh Adrian Jonathan Pasaribu dalam artikelnya Lebih dari Sekadar Angka (2018). Adrian menjelaskan bagaimana bioskop sangat tidak representatif terhadap masyarakat Indonesia sendiri. Monopoli oleh lembaga sensor serta kelompok yang berperan sebagai importir, distributor, sekaligus pemilik bioskop masih mengasingkan film Indonesia dari masyarakatnya sendiri.
Mengutip Adrian, “Sebagai perkara kultural, film Indonesia hanya relevan bagi sejumlah kelompok warga. Kebijakan sensor mensterilkan film dari berbagai representasi sosial dan ekspresi politik, seolah hendak mencitrakan masyarakat Indonesia sebagai suatu komunitas yang generik, apolitis, dan “sudah baik dari sananya”. Ungkapan tentang ras, agama, kelas sosial, selera politik, dan orientasi seksual hanya diizinkan apabila selaras dengan kebutuhan rezim yang berkuasa.”
Dengan serangkaian konteks yang meliputinya, alih-alih melihat polemik difilmkannya Bumi Manusia sebagai ekspresi kecongkakan kaum tua, saya lebih melihat ini sebagai penolakan atas arogansi Falcon Pictures dengan logika kapitalistiknya. Sejak awal saya memang tidak sreg dengan keputusan Hanung Bramantyo untuk memfilmkan Bumi Manusia. Tapi saya menolak kalau ini dianggap sebatas soal Minke yang akan diperankan oleh Iqbaal Ramadhan atau sebagai upaya meletakkan Bumi Manusia pada level kesakralan tertentu sehingga menutup ruang tafsir atasnya.
Jika mau berbicara salah-benar, tentu apa yang Hanung lakukan tidak salah. Setiap orang berhak memiliki pembacaan berbeda terhadap sebuah teks. Jika menurut pembacaan Hanung, Minke cocok diperankan oleh Iqbal, ya sah-sah saja. Misal yang menyutradarai adalah Jokowi, ya bebas-bebas saja kalau ia beranggapan Wiranto adalah sosok Minke yang ideal. Jawa, tegas, kulit sawo matang, ditambah pengalaman seni peran yang mumpuni, kurang apalagi?
Ia tidak salah dalam menjadikan interpretasinya atas karya Pram menjadi bentuk audio-visual. Sekali lagi, kalau ukurannya bebas, maka apa yang dilakukan Hanung tentu tidak bermasalah selama ia melunasi tetek bengek perihal hak cipta dan sejenisnya.
Pun dengan bagaimana Orde Baru menafsirkan apa yang terjadi pada malam 30 September di magnum opus Arifin C. Noer, Pengkhianatan G30S/PKI (1984). Soeharto bebas saja menulis sejarah bahwa malam 30 September adalah soal tari telanjang serta ritual pemotongan alat kelamin. Lagi pula saat itu siapa yang berani menawarkan narasi alternatif soal malam 30 September? Paling hanya sejarawan kacangan seperti Ben Anderson dan Ruth McVey dengan Cornell Paper-nya.
Ruang publik adalah arena pertarungan kebenaran. Dalam konteks Orde Baru, tentu saja kebenaran adalah milik rezim Soeharto dan kroni-kroninya. Mekanisme pasar dalam hal ini tidak kalah celakanya. Jelas setiap individu berhak memiliki interpretasi berbeda terkait Bumi Manusia. Namun siapa di antara individu-individu tersebut punya modal untuk mewujudkan pembacaannya menjadi sebuah film yang bisa jadi diamini menjadi kebenaran bersama oleh generasi yang barangkali secara sistemik dibutakan dari gagasan Pram?
Jika jawaban Bung Iqbal terhadap pertanyaan bagaimana mengenalkan Bumi Manusia kepada generasi-generasi yang lebih muda adalah menyerahkan tugas itu kepada kapitalis film macam Falcon Pictures, maka suram sekali masa depan bangsa kita ini. Bung Iqbal sepertinya lupa bahwa bangsanya menempati peringkat 60 dari 65 negara soal tingkat literasi. Persoalan fundamental yang tentunya tidak bisa diselesaikan dengan mengangkat teks sepenting Bumi Manusia ke sinema dan berakhir menjadi omong kosong perayaan sinematik.
Barangkali penolakan atas difilmkannya Bumi Manusia pada permukaan terlihat seperti arogansi segelintir manusia yang tidak rela karya monumental Pram diinterpretasikan oleh Hanung Bramantyo. Namun sekali lagi, merupakan kesalahan fatal apabila kita mengabaikan konteks perfilman Indonesia. Maka saya melihat penolakan ini sebagai prasangka yang lahir bukan tanpa sebab dan tidak bisa dihindari.
Ia lahir dari kelelahan atas bagaimana selama ini kita sebagai bangsa masih terjebak untuk memaknai sinema sekadar soal angka, sesuatu yang dilanggengkan oleh mesin-mesin kapitalisme seperti Falcon Pictures. Ia tidak berbeda layaknya prasangka yang wajib kita hadiahkan bagi siapa pun yang diberi kuasa oleh publik. Karena tanpa prasangka tersebut akan terulang kembali sejarah di mana kekuasaan selalu disalahgunakan.
Pada akhirnya, satu-satunya hal yang menarik justru pada segala perdebatan publik atas polemik difilmkannya Bumi Manusia. Bagi saya, menjadi tidak penting lagi untuk menonton film dari pihak yang memandang publik tidak sebagai manusia melainkan hanya konsumen. Sejak awal ini tidak pernah menjadi soal siapa memerankan siapa. Ini adalah persoalan apakah kita mau atau tidak untuk tunduk terhadap logika kapitalistik pihak-pihak seperti Falcon Pictures.