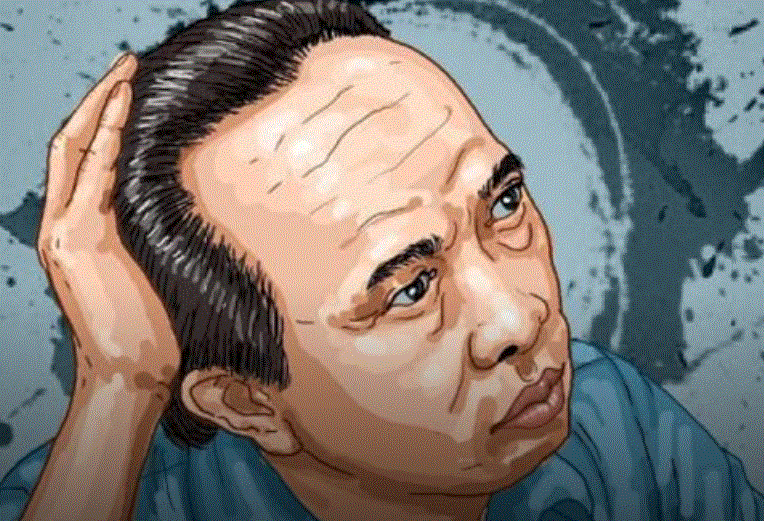Malam itu, 30 September 1995, dia masih sempat menonton film Pemberontakan PKI atau lebih populer dengan Gerakan tiga puluh September—G 30 S–PKI. Bagi Anda yang lahir tahun 1980-an pasti pernah menonton film wajib rezim orde baru itu.
Cuplikan yang paling dia ingat adalah di saat Subah Asa—pemeran Dipa Nusantara Aidit—Bos besar PKI mengatkan,”Jakarta adalah kunci.” Sambil menggerutu, dia berucap,” Ini Film banyak ngibulnya.” Kisah itu saya kutip dari buku Bung, Memoar tentang Mahbub Djunaidi, yang ditulis oleh Isfandiari—anaknya Mahbub– dan Iwan Rasta.
Film itu biasanya tayang setiap 30 September malam, besoknya diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober. Ditanggal itulah, menjelang subuh, seorang Kolumnis, Wartawan, Politisi, Kiyai NU meninggal dunia.
Dialah Mahbub Djunaidi. Dalam kesehariannya lebih senang dipanggil Bung. Dia bahkan meminta anak dan cucunya memanggil dirinya Bung. Saya tertarik menulis memoar ini bukan apa-apa, karena si Bung mempengaruhi saya dalam menulis.
Saya tidak mengenal si Bung secara fisik, karena di saat kematiannya, saya masih kelas 3 Sekolah Dasar. Apa tau anak seumuran itu, kecuali menghafal nama-nama Menteri Kabinet Pembangunan.
Saya membaca tulisan si Bung sepuluh tahun setelah kematiannya. Itupun, sebatas membaca satu dua artikel, sama seperti membaca karya beberapa penulis lain. Terakhir, saya membaca kolom si Bung hampir tuntas baru-baru ini, di bawah bayang-bayang Korona.
Atas usul Bung Alkaf, saya membaca tulisan-tulisan Mahbub Djunaidi. Menurutnya, karakter tulisan saya cocok mengikuti alur kolom Mahbub.
Sejak saat itu, saya mengoleksi beberapa karya si Bung, mulai dari kumpulan tulisannya seperti Kolom Demi Kolom, Humor Jurnalistik, Asal-usul, Novel karangannya nya, seperti Angin Musim, Dari Hari Ke Hari, Memoar yang ditulis Isfandiari MD dan Iwan Rista yang berjudul Bung, Memoar tentang Mahbub Djunaidi, sampai Novel yang dia terjemahkan, seperti Binatangisme.
Memang, saya menyukai gaya menulis Mahbub. Saya juga berupaya untuk “meniru” gaya bahasanya–kaya kosakata dan tidak garing kalau dibaca. Walaupun, upaya itu bukan perkara mudah. Paling tidak, sudah ada perbaikan dari sebelumnya.
Si Bung merupakan Generalis. Dia menulis apa saja yang menurutnya penting untuk ditulis. Mulai dari isu internasional, seperti tulisannya yang berkepala Musibah yang Menimpa Presiden Salvador Allende, Politik “Pragmatis” AS di Amerika Latin, Persatuan Arab, Upaya dan Jalan Teramat Panjang, Jepang Moder dari Sudut yang Lain, sejarah seperti tulisannya yang berkepala Kisah Sejarah yang Bengkok-Bengkok, agama seperti tulisannya yang berkepala Masuk Islam Jamaah, sampai persoalan masyarakat kecil seperti tulisannya yang berkepala Sebuah Pertanyaan “Remeh” untuk Dirjen Urusan Haji.
Dalam menulis, Mahbub juga tidak segan-segan mengkritik kawannya yang lagi menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dalam tulisan berkepala Isnaeni, yang Wartawan dan yang DPR, Mahbub mengkritik Isnaeni karena off the record. Isnaeni meminta wartawan tidak menayangkan beberapa pernyataannya. Beberapa hari berselang, Wakil Ketua DPR itu membalas tulisan Mahbub dengan judul Untuk Kawanku, Bung Mahbub Djunaidi.
Begitulah kritisnya Mahbub, dia mengkritik siapa saja. Padahal, waktu itu Orde Baru sedang berkuasa. Dengan gaya tulisan Mahbub, orang yang dikritik tidak merasa sedang dikritik. Itulah hebatnya si Bung dalam menulis.
Selain sebagai penulis, si Bung juga mencapai puncak dari dunianya yang lain itu. lihat saja, Mahbub sebagai seorang aktivis mahasiswa aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan setelah itu mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Mahbub adalah Ketua Umum pertama lembaga mahasiswa yang dekat dengan NU tersebut.
Sebagai politisi, Mahbub juga mencapai puncak karir sebagai anggota DPR–profesi yang dalam tulisan-tulisannya sering dikritik oleh Mahbub. Salah satu keberhasilan Mahbub sebagai anggota DPR adalah menginisiasi Undang-undang Ketentuan Pokok Pers, dia sendiri yang menjadi ketua Panitia Khusus. Setelah Partai NU—Partainya Mahbub—fusi menjadi PPP, Mahbub pun pernah menjadi salah satu pimpinan di DPP PPP.
Dalam dunia jurnalistik, si Bung pernah menjadi Pimpinan Redaksi Duta masyarakat, medianya NU. Puncak karir Mahbub dalam organisasi kewartawanan sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Di NU, Mahbub mengawali dari bawah. Mulai dari Ikatan Pelajar NU, terus Gerakan Pemuda Ansor, hingga menjadi pengurus PBNU.
Mahbub kritis dalam menulis, tidak pandang bulu. Siapapun yang memegang kuasa, tidak lewat dari amatan si Bung. Oleh karena itu pula, mengantarkan Mahbub ke penjara. Sejak saat itulah, kesehatan Mahbub terus menurun sampai ajal menjemput.
Satu perkara lagi yang ingin saya ingat dari seorang Mahbub. Dia toleran. Sebagai pimpinan media Partai NU, Mahbub membela Sutan Takdir Alisyahbana yang dituduh oleh Lekra—organisasi kebudayaan yang berafiliasi dengan PKI—plagiat. Menciplak karya orang.
Dilain kesempatan, mahbub berteman baik dengan beberapa petinggi PKI. Dua diantaranya adalah Lukman Nyoto dan Pramudya Ananta Toer. Menurut Mahbub, Nyoto adalah orang pintar, intelektual, bacaannya banyak. Sementara Pram, pada kemudian hari dijadikan Mahbub sebagai nama salah satu cucunya. Begitulah Mahbub ingin mengingat Pram.
Terkahir, tulisan Mahbub memang disukai kawan dihargai lawan. Sampai-sampai, Bung Karno penasaran dengan salah satu tulisan si Bung soal Pancasila. Menurut mahbub, Pancasila memiliki kedudukan sublimasi dibandingkan dengan Declaration of Independence yang disusun oleh Thomas Jefferson yang menjadi pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli 1776, maupun dengan Manifes Komunis yang disusun oleh Karl Marx dan Friedrich Engels 1847.
Begitulah Mahbub, sulit dicari ganti. Mahbub sudah tiada. Namun, tulisan-tulisannya masih dapat dibaca. Salah satu kosakata yang paling sering saya temukan dalam kolom Mahbub adalah Alang-Kepalang. Dan itu saya kutip untuk menjadi kepala tulisan ini, Mahbub Djunaidi, Kolumnis yang bukan alang-kepalang.