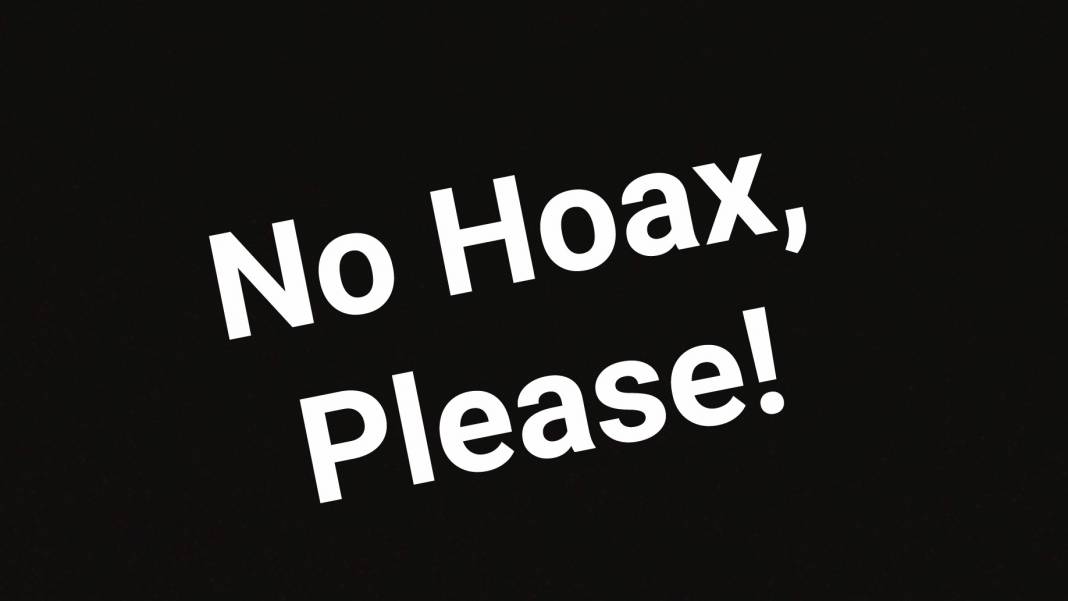Kamus Oxford menempatkan kata post-truth sebagai “Word of The Year” pada tahun 2016 karena kata tersebut begitu banyak digunakan oleh umat manusia, terlebih pada peristiwa terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dan keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit). Pada kedua momen itu, berita hoax (hoaks=bohong) dengan sangat mudah disebarkan kepada masyarakat luas dan mempengaruhi opini publik.
Indonesia sendiri mengalami dampak buruk dari era post-truth. Tanpa mengabaikan penyebaran hoaks pada masa sebelumnya, gempuran informasi hoaks bertaburan di media sosial selama 3-4 tahun terakhir, terutama ketika pilpres 2014 dan pilkada Jakarta 2015. Rakyat terpecah menjadi kubu-kubu yang saling serang hanya berdasarkan informasi bohong. Baru-baru ini kita pun disajikan drama hoax operasi plastik Ratna Sarumpaet yang mampu menipu Prabowo Subianto dan Tim Suksesnya.
Steve Tesich adalah orang pertama yang menggunakan istilah post-truth. Ia menggunakan istilah tersebut dalam artikelnya The Gorvernment of Lies di majalah The Nation yang terbit pada tanggal 6 Januari 1992. Ia mengambil latar belakang Skandal Watergate Amerika (1972-1974) maupun Perang Teluk Persia untuk menunjukkan situasi masyarakat pada saat itu yang tampaknya “nyaman” hidup dalam dunia yang penuh kebohongan. Ia melihat bahwa masyarakat tidak terlalu peduli dengan sekelumit kebenaran yang ditegakkan dan dengan bebas memilih untuk hidup pada ruang post-truth.
Singkatnya, era post-truth adalah era di mana manusia hidup di dalam kebohongan dan menganggap hal tersebut tidak lagi sebagai masalah besar. Bisa dikatakan bahwa era post-truth melahirkan suatu banalitas kebohongan yang membuat akal budi manusia kesulitan untuk melihatnya secara jelas.
Ruang publik masyarakat modern yang menjadi tempat manusia hidup tidak lagi kondusif untuk menyingkirkan kebohongan dan memeluk kebenaran. “Cakar” era post-truth semakin lama semakin kuat tertanam dalam diri setiap manusia tanpa batas negara ataupun kebudayaan, terlebih karena dibantu penyebarannya lewat media sosial dan internet.
Konstruksi Nalar Manusia pada Era Post-Truth dan Dampaknya
Persoalan utama yang menjadi fokus era post-truth adalah banalitas kebohongan yang merasuki pelbagai sendi kehidupan manusia, secara khusus pada bidang kebijakan publik dan politik elektoral. Penyebaran informasi hoax yang bertujuan untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap bidang-bidang tersebut dijadikan sebagai strategi agar tujuannya dapat tercapai.
Nalar manusia yang sudah dimanipulasi oleh informasi-informasi hoax tersebut selanjutnya akan menuntun setiap tindakan atau ucapan manusia itu sesuai dengan skema yang diharapkan oleh “otak” penyebaran hoax.
Konstruksi nalar manusia era post-truth ini sejatinya “unik” dalam hal mencari dan merumuskan kebenaran. Kebenaran sejati yang dimaksudkan dalam era post-truth tampaknya adalah kebenaran yang sesuai dengan emosi sosial.
Artinya, sejauh sesuatu dianggap dapat menggerakkan emosi publik, sesuatu itu dapat dianggap sebagai kebenaran; tidak peduli lagi dari mana segala informasi itu berasal atau bagaimana informasi itu dimodifikasi sehingga bersifat “abu-abu” atau malahan berlawanan dengan fakta.
Penyebaran hoax yang bertujuan untuk mempengaruhi emosi sosial menempatkan rakyat kebanyakan sebagai objeknya. Tujuannya sederhana: masyarakat era post-truth yang secara psikologis mudah melekatkan diri kepada kelompok sosial tertentu yang berlawanan dengan kaum elit akan teguh mengikuti keyakinan mayoritas di mana mereka berdiri. Persoalan uji kesahihan informasi yang beredar tidak lagi dianggap sebagai hal yang harus dilakukan. Kebenaran mayoritas (walaupun tidak sesuai fakta) dianggap sebagai kebenaran sejati.
Rekonstruksi Nalar Manusia pada Era Post-Truth
“Internetisasi” segala macam aspek kehidupan manusia pada saat ini memiliki dampak yang cukup serius pada cara manusia dalam menerima kebenaran. Sebelum dunia dikepung oleh kekuatan internet, informasi mengenai pengetahuan merupakan hal yang sangat mahal dan sulit untuk ditemukan.
Itulah sebabnya manusia pada masa sebelum internet berlomba-lomba mencari kebenaran pengetahuan tersebut dengan cara saling menguji dan mengkritisi. Manusia pada masa sebelum internet mengejar kebenaran pengetahuan sebagai sesuatu yang “mahal”.
Setelah internet hadir, bukan manusia yang mengejar informasi mengenai pengetahuan melainkan informasi tersebut yang “datang” kepada manusia. Penemuan informasi dan pengetahuan baru menjadi begitu instan dan mudah.
Akibatnya, manusia cenderung abai dalam memilah-milah informasi tersebut. Nalar kritis manusia “dimandulkan” oleh segala macam kemudahan yang ditawarkan oleh internet. Apakah suatu informasi itu hoax ataupun benar tidak lagi menjadi perhatian manusia. Hal yang dipedulikan manusia berkaitan dengan informasi tersebut adalah seberapa jauh informasi tersebut viral dan dibicarakan oleh banyak orang.
Nalar kritis manusia harus ditegakkan lagi pada masa ini, terlebih ketika hoax berhasil memporak-porandakan banyak sendi kehidupan manusia. Rekonstruksi nalar manusia pada era post-truth pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan lagi nalar kritis manusia untuk merumuskan kebenaran sejati. Nalar kritis ini dibangun dengan kemampuan manusia untuk bertanya dan memetakan informasi-informasi yang beredar di internet. Nalar manusia harus mau sedikit “bersusah payah” untuk mengecek kebenaran setiap informasi yang disajikan oleh media.
Rekonstruksi nalar kritis manusia ini juga berkaitan dengan cara manusia melihat internet, media sosial ataupun media massa online. Banyak orang merumuskan internet sebagai suatu realitas, atau di banyak kajian digunakan istilah hyper-reality. Akibatnya, banyak orang merasa bahwa media sosial online merupakan komunitas global di mana manusia berinteraksi dan juga saling membentuk persepsi.
Meledaknya “bom isu” di media sosial terhadap satu persoalan akan membentuk persepsi publik dalam kesehariannya di luar internet karena manusia yang berselancar di media tersebut meyakini bahwa itulah yang benar terjadi. Internet dan media sosial atau media online bukanlah realitas. Dalam perspektif Heideggerian (Heidegger, Being and Time 1927), semua hal tersebut hanyalah sarana yang membantu kehidupan manusia.
Rekonstruksi nalar manusia pada era post-truth bukanlah pekerjaan yang mudah karena hal ini berkaitan dengan kesadaran dan penyadaran bersama. “Racun” kemudahan yang ditawarkan oleh internet tampaknya sudah begitu kuat merasuki kehidupan manusia pada masa ini. Keduanya hampir sulit dipisahkan.
Rekonstruksi nalar ini menjadi tugas setiap orang yang peduli terhadap kebenaran sejati. Setiap orang diajak untuk mampu melihat internet dan media sosial lainnya sebagai teknologi yang sifatnya membantu kehidupan manusia. Pada akhirnya, informasi yang keluar dari teknologi semacam itu juga harus dikritisi dan “ditelanjangi” sehingga manusia bisa menikmati kebenaran yang sejati.
Bacaan:
Habermas, Jurgen. 1979. Communication and the Evolution of Society, trans. Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press.
Mudde, Cas. ‘The Populist Zeitgeist’, Government and Opposition, Vol. 39(4), 2004.
Tesich, Steve. “The Government of Lies”, The Nation, 6 Januari 1992.