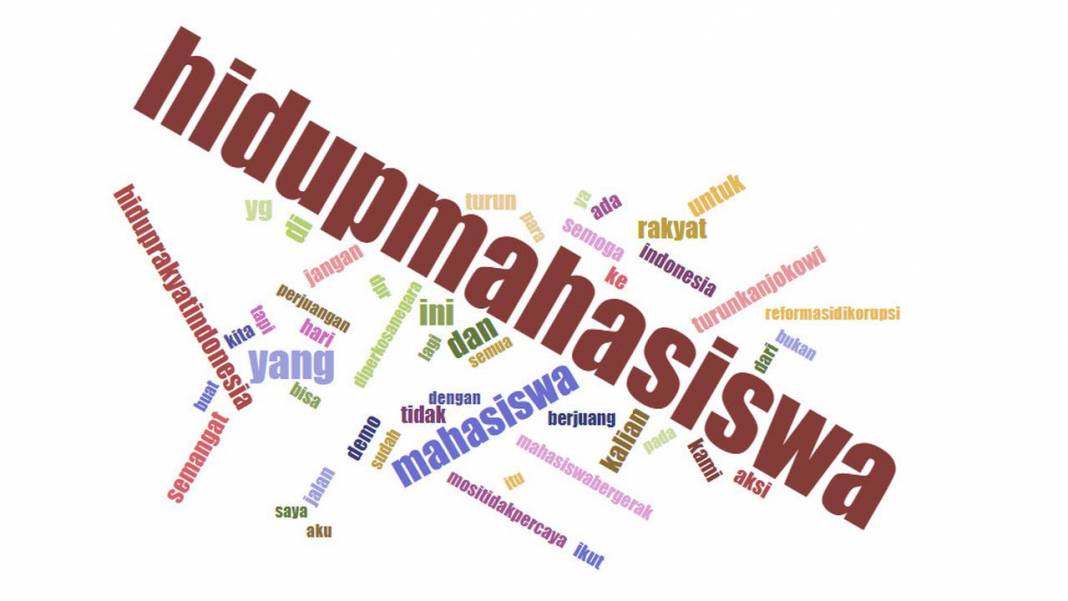Ada hal yang lebih berbahaya daripada kemiskinan finansial. Yakni, kemiskinan gagasan di lingkungan akademik. Ironisnya, sebagian perguruan tinggi lokal justru bangga dengan kemiskinan semacam ini. Mereka sibuk mendandani wajah institusi, tapi abai merawat organ vitalnya: budaya mutu akademik.
Di banyak kampus kecil, standar mutu itu sekadar banner seminar, backdrop acara, atau laporan kegiatan yang tebal tapi kosong makna. Semua rapi, semua formal. Tapi isinya? Ya, begitu-begitu saja. Mutu jadi semacam “kosmetik kelembagaan”, bukan komitmen kolektif.
Saya bicara begini bukan tanpa dasar. Bertahun-tahun saya berada di dalam sistem semacam ini. Menyaksikan langsung bagaimana kampus lebih takut pada perubahan daripada stagnasi. Di sini, ide segar bisa dianggap ancaman. Saking takutnya pada inovasi, orang-orang lebih nyaman merawat kemapanan semu.
Dosa kolektif ini diwariskan dari generasi ke generasi. Semua orang tahu ada yang keliru, tapi tak satu pun berani membenahi. Semua berpura-pura sibuk, asal posisi aman.
Dalam teori Organizational Inertia (Hannan & Freeman, 1984), organisasi seperti ini mengalami kekakuan struktural dan budaya. Setiap ide baru dicurigai. Setiap suara kritis dilabeli pembangkang. Wacana internasionalisasi? Ah, itu cuma bumbu proposal akreditasi.
Lebih parah lagi, akreditasi dijadikan proyek sesaat. Dokumen tebal-tebal disusun saat deadline. Setelah nilai keluar, semua kembali ke rutinitas lama. Jalan di tempat.
Inilah yang saya sebut kosmetik mutu akademik. Tampilan luar kinclong, dalamnya lapuk. Celakanya, semua pihak ikut ambil bagian dalam dosa ini. Dosen, tendik, mahasiswa, hingga pejabat kampus. Yang idealis dimusuhi. Yang oportunis dipromosikan.
Saya teringat pesan Dale Carnegie, “Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada melihat potensi besar dikubur hidup-hidup oleh ketakutan orang sekitar.” Atau pesan Buya Hamka, “Orang yang takut pada perubahan adalah orang yang rela hidup tanpa kemajuan.”
Di kampus-kampus seperti ini, ketakutan terhadap perubahan justru dilestarikan. Dianggap tradisi akademik. Internasionalisasi, digitalisasi, bahkan sekadar budaya akademik sehat tak akan pernah tumbuh di tanah gersang oleh ego sektoral. Kampus lebih sibuk menjaga loyalis ketimbang mencari inovator. Lebih nyaman dengan pembisik ketimbang pemikir.
Saya pribadi mengalami itu. Tak sedikit gagasan yang saya usulkan berujung ditolak. Bukan karena buruk, tapi dianggap “mengganggu ketenangan.” Di sinilah relevansi teori Gatekeeping Effect (Kurt Lewin) bekerja. Dalam setiap organisasi, selalu ada figur atau kelompok yang menjadi penjaga gerbang ide, peluang, dan informasi.
Loyalitas memang penting. Tapi saat loyalitas berubah menjadi patronase, di mana keputusan strategis ditentukan atas dasar kedekatan personal ketimbang pertimbangan profesional, di situ kehancuran budaya mutu mulai nyata.
Dalam perspektif Social Comparison Theory milik Leon Festinger, individu cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain untuk menilai keberhasilan. Sayangnya, dalam ekosistem seperti ini, keberhasilan orang lain bukan dirayakan, tapi dicurigai. Orang sukses diposisikan sebagai ancaman, bukan inspirasi. Lingkungan sosial yang rapuh seperti ini menjadikan kampus kecil makin terpuruk, karena potensi internalnya lebih sibuk bertahan daripada berkembang.
Padahal, di era AI, digitalisasi, dan society 5.0, kampus kecil punya peluang luar biasa. Masyarakat desa, guru PAUD, pemuda desa yang selama ini terpinggirkan sistem bisa menjadi target edukasi berbasis skill digital, edupreneur, dan manajemen kelembagaan. Dengan biaya kuliah fleksibel, sistem hybrid, dan program berbasis kebutuhan pasar, kampus kecil sebetulnya bisa bangkit — asal berani keluar dari kubangan ego sektoral.
Saya bukan siapa-siapa. Hanya anak desa dari Kebumen yang nekat bertahan di Purworejo. Kalau ada yang anggap keberhasilan akademik saya sebagai ancaman, itu urusan mereka. Saya percaya, sebagaimana pesan Nelson Mandela, “Tidak ada musuh yang lebih kuat daripada ketakutan yang diciptakan oleh diri sendiri.”
Tulisan ini bukan untuk mencibir. Hanya ajakan kecil untuk kampus-kampus kecil di manapun agar mulai berani berhenti berdandan dan mulai berbenah. Budaya mutu itu dibangun, bukan dipoles.
Karena sejatinya, dosa kolektif akademik ini bukan hanya akan menghancurkan institusi, tapi juga memutus rantai harapan anak-anak desa yang menitipkan cita-cita di ruang-ruang kelas sederhana. Mereka yang mestinya tumbuh sebagai generasi pembaharu, dipaksa tersesat di labirin sistem palsu yang pura-pura peduli.
Dan kalau kampus hanya jadi etalase palsu, jadi panggung ilusi tanpa isi — lalu untuk apa kita bertahan di sana? Menjadi bagian dari kemunafikan intelektual hanya akan menambah panjang daftar pengkhianat masa depan bangsa.
Sudah saatnya kampus-kampus kecil berhenti bercermin di kaca retak dan mulai berani bermimpi besar. Bukan mimpi kosong, bukan ilusi anak kecil. Karena sejarah mencatat, peradaban besar dibangun bukan oleh orang-orang yang pesimis dan paternalistik, tapi oleh mereka yang berani merancang utopia di tengah keraguan, lalu mewujudkannya pelan-pelan dengan gagasan dan keberanian.
Karena dalam dunia pendidikan, mutu yang palsu tidak hanya tak menyelamatkan siapa pun — tapi akan menjadi warisan kutukan bagi generasi berikutnya. Dan di situ, kita semua akan tercatat sebagai bagian dari dosa kolektif itu.