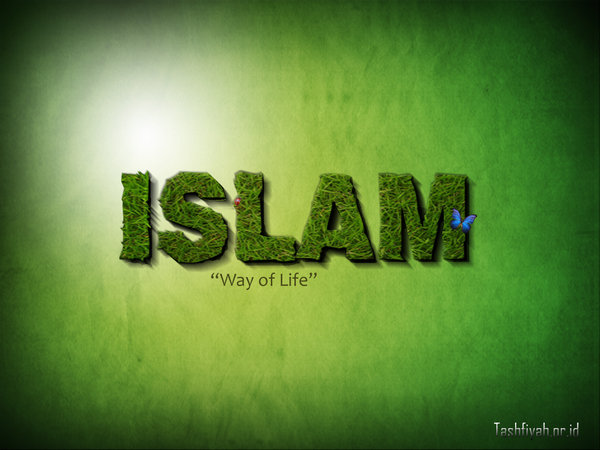Islam dan adat di Sumatera Barat adalah dua sistem nilai dan norma yang berperan penting membangun landasan moral kehidupan bermasyarakat, terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya alam. Menelisik kembali landasan moral dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi penting di tengah semakin besarnya kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, yang hadir akibat eksploitasi tanpa batas manusia.
Kerusakan lingkungan dan sumber daya alam tersebut tidak bisa dilepaskan dari penyingkiran sisi moral pengelolaan sumber daya alam dan “pemberhalaan” terhadap sisi teknikal pengelolaan sumber daya alam di era modern. Era modern memang telah menyediakan pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan secara teknis manusia menguasasi alam, sekaligus mengurangi resiko dari dampak kerusakan yang ditimbulkannya.
Dalam hal ini, manusia seolah-olah telah mengambil alih alam untuk dirinya sendiri dan sedemikian rupa mengeksploitasinya tanpa batas. Model pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif tersebut kemudian dikritik sebagai penyebab utama persoalan-persoalan lingkungan hidup hari ini, mulai dari persoalan pemanasan global sampai dengan bencana ekologis.
Paradigma baru-pun muncul sebagai alternatif pengelolaan sumber daya alam, yang menempatkan prinsip keberlanjutan (sustainable), keadilan sosial, dan landasan moral hadir kembali dalam aras pengelolaan sumber daya alam.
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana landasan moral yang terkandung dalam Adat dan Islam hadir dan berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Tulisan ini mengambil studi kasus di Nagari Guguk Malalo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
Relasi Adat dan Islam
Karakter tradisi islam pada masyarakat melayu, khususnya minangkabau menghormati nilai-nilai tradisional (adat) dan konsisten menjalankan adat dan islam secara bersamaan. Hal tersebut termanifes dalam pepatah; “adat basandi syara;, syara’ basandi kitabullah.”
Pepatah tersebut menjelaskan bahwa adat dan islam telah terjalin sedemikian rupa, dan dilaksanakan dengan prinsip “islam adalah dasar dan adat adalah operasional.” Nilai-nilai islam menjadi tonggak yang dijalankan dalam pemakluman adat. Prinsip tersebut adalah cara masyarakat minangkabau melegitimasi menjalankan adat dan islam secara bersamaan (koeksistensi).
Koeksistensi adat dan islam tersebut terutama terkait dengan konsistensi masyarakat minangkabau pada umumnya, dan masyarakat nagari guguk malalo pada khususnya untuk menjaga sistem pewarisan matrilineal penguasaan tanah dan sumber daya alam berdasarkan adat (hak ulayat). Sistem penguasaan sumber daya alam tersebut kemudian membentuk model pengelolaan sumber daya alam.
Ekonomi Kaum dan Model Kelola
Model pengelolaan sumber daya alam berbasis adat utamanya adalah untuk menjamin keadilan (distribusi) sumber daya bagi keberlanjutan mata pencarian seluruh anggota komunitas masyarakat nagari guguk malalo. Sistem pewarisan dan penguasaan sumber daya alam ini melahirkan pembatasan atas penguasaan tanah dan sumber daya alam oleh individu secara mutlak.
Seorang laki-laki dewasa, yakni laki-laki menikah dibebankan memenuhi kebutuhan keluarga batih (istri dan anak-anak), yang dia bisa hasilkan dari pemanfaatan tanah-tanah sawah dan parak (agroforest). Pemanfaatan tanah-tanah tersebut bisa pada tanah yang dimiliki oleh keluarga istri, maupun pada tanah-tanah dari keluarga ibunya melalui hak pakai ‘ganggam bauntuk.’
Dalam hal ini, laki-laki dewasa tersebut hanya bisa memanfaatkan hasil dari lahan-lahan produktif untuk memenuhi kebutuhan keluarga batih, tetapi tidak untuk dimiliki secara mutlak. Begitu juga halnya dengan istri pewaris tanah, juga hanya bisa menyediakan lahan untuk dikelola keluarga batihnya, namun dibatasi untuk memiliki secara mutlak.
Model pengelolaan tanah tersebut (model tanah pusako tinggi) tidak bisa dilepas dari model ekonominya, yaitu model ekonomi keluarga berbasis suku/kaum. Graves (2007) menjelaskan bagaimana model tanah pusako tinggi memastikan model ekonomi tersebut berlangsung. Tanah pusako tinggi sebagai harta pusaka adalah semacam “dana jaminan bersama” (trust fund), yang dimiliki bersama-sama oleh anggota kaum/suku.
Kepemilikan individual mutlak tidak dimungkinkan dalam sistem ini, sehingga juga menyulitkan untuk diperjualbelikan oleh masing-masing anggota kaum/suku. Sistem ini melindungi semua anggota kaum/suku dari kemiskinan fatal, yang secara bersamaan juga menyulitkan pemilikan tanah-tanah secara pribadi yang memungkinkan seseorang menjadi kaya mendadak.
Adat dan Pengelolaan Keberlanjutan
Pada tingkat lebih tinggi di tingkat nagari/desa terdapat tanah ulayat nagari. Tanah ulayat nagari adalah ‘trust fund’ bagi seluruh suku-suku dan kaum-kaum yang ada di nagari. Hal ini terlihat dari konsep tanah dan hutan cadangan pada areal ulayat nagari yang dikenal di nagari guguk malalo.
Sumber daya alam yang ada di ulayat nagari tersebut oleh adat diperuntukkan untuk kepentingan perluasan lahan pertanian dan pemukiman bagi pengembangan kepentingan ekonomi kaum/suku. Sedangkan hasil hutan kayu dan non kayu adalah hasil sampingan dalam model ini, sehingga pemanfaatannya tidak untuk kepentingan individual, namun diprioritaskan bagi kepentingan publik nagari, seperti membangun fasilitas umum, surau atau masjid.
Dalam konteks ini, pemanfaatan oleh individu atas hasil hutan kayu adalah ‘penyimpangan,’ sehingga bagi mereka dianggap sebagai orang luar yang memanfaatkan harta bersama. Konsekuensinya, mereka diberlakukan sama dengan orang luar komunitas yang harus mendapatkan izin dari panghulu-panghulu nagari dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan juga Pemerintah Nagari.
Selain itu, adat juga membatasi pemanfaatan hasil hutan kayu oleh individu tersebut sebatas untuk kebutuhan sendiri, seperti memperbaiki rumah, kandang ternak, dan dilarang keras bagi kepentingan komersil.
Model pengelolaan hutan dan sumber daya alam diatas terkait dengan keberlanjutan pola produksi masyarakat di sektor pertanian sawah dan pengelolaan agroforestry. Produksi pertanian pokok masyarakat berasal dari panen padi sawah dan hasil parak (agroforest) tersebut.
Hasil panen padi diprioritaskan untuk kebutuhan pangan keluarga, dan sisanya menjadi komoditi perdagangan pada pasar-pasar tradisional. Sedangkan hasil produksi parak (agroforest), berupa kayu manis, kopi, dan buah-buahan musiman menjadi komoditas yang dijual pada pengumpul dan sebagian kecil lagi dijual pada pasar-pasar nagari.
Hasil panen parak berkontribusi pada mata pencarian keluarga batih untuk kebutuhan non pangan, seperti pendidikan anak, kesehatan dan kebutuhan skunder lainnya.
Model produksi ini mengakibatkan pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu adalah produksi minor masyarakat. Dalam konteks ini, hutan sebenarnya adalah sumber daya ‘cadangan’ bagi kepentingan pemanfaatan lahannya, bukan pada hasil hutannya.
Adat dan Islam sebagai Landasan Moral
Topografi nagari guguk malalo berlereng bukit berakibat pada perluasan persawahan tidak dimungkinkan lagi, namun hanya pada perluasan parak (agroforest). Adat sendiri membatasi perluasan lahan parak tersebut dengan menetapkan areal tertentu sebagai ‘hutan larangan.’ Fungsi hutan larangan ini adalah untuk kepentingan memelihara sumber mata air penopang irigasi lahan persawahan masyarakat.
Pola produksi dan model pengelolaan sumber daya alam ini melahirkan kesatuan landscape ekosistem nagari yang terintegrasi antara ekosistem pertanian sawah irigasi, agroforestry dengan hutan. Hutan adalah penopang ekosistem pertanian sawah irigasi dan agroforestry dengan menyediakan sumber mata air bagi pertanian sawah irigasi dan penyediaan lahan agroforestry.
Selaras dengan itu, Islam menjadi faktor penting pola produksi dan model pengelolaan sumber daya alam tersebut tetap berlangsung, dengan memperkuat tanggung jawab sosial-ekonomi dan ekologis, baik secara individual maupun komunal, melalui; (1) Mempertegas tanggung jawab sosial-ekonomi komunitas dengan penetapan hisab atas zakat maal (zakat harta) dari pemanfaatan tanah pusako tinggi oleh masing-masing keluarga batih dan paruik yang disampaikan setiap tahun dalam ritual mambuka kapalo banda.
Penetapan hisab zakat maal pada ritual tersebut adalah bentuk legitimasi relijius atas sistem ekonomi kaum/suku yang berbasis pada hak adat, yang mengutamakan ‘kesejahtreraan umum’ dibandingkan dengan ‘kesejahteraan individual.’ Prinsip kesejahteraan umum dalam sistem adat ini kemudian bertemu dengan nilai islam yang menolak keserakahan individual dengan zakat sebagai intsrumennya.
(2) Tanggung jawab ekologis, yaitu dengan melegitimasi penetapan wilayah “konservasi adat” yang disebut juga dengan ‘hutan larangan.’ Penetapan hutan larangan dilaksanakan melalui adat dan diperkuat oleh nilai-nilai islam yang direproduksi secara konsisten terus menerus dalam penyelenggaraan ritual ‘mambuka kapalo banda.’
Ritual ini menjadi sarana komunikasi komunitas atas norma dan pengetahuan lokal tentang pentingnya menjaga sumber mata air melalui penetapan hutan larangan yang berfungsi profan sekaligus sakral tersebut. Fungsi profan terkait dengan fungsi konservasi adat untuk kepentingan menjaga keseimbangan ekosistem, sedangkan fungsi yang sakral adalah tanggung jawab individu dan komunitas terhadap keseimbangan alam sebagai sunnatullah.
Akhir kata, koeksistensi menjalankan adat dan islam dalam pengelolaan sumberdaya alam di nagari guguk malalo adalah bentuk aktualisasi konkrit dari konsep pembangunan berkelanjutan dalam frame al-qur’an, yang oleh Abomoghli dalam Mangunjaya (2014) menyebutkan bahwa pembangunan keberlanjutan dalam islam adalah keseimbangan dan realisasi berkesinambungan antara kesejahteraan dan pemanfaatan, efisien secara ekonomi, memperoleh keadilan sosial, dan keseimbangan ekologi.