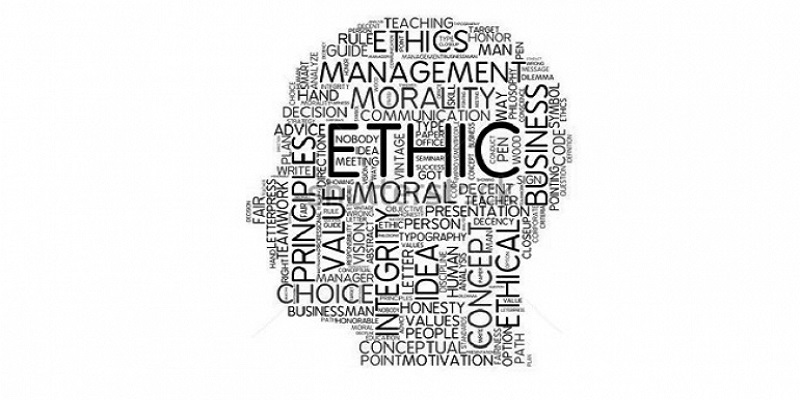“Bukan kegilaan, tetapi matematika keabadian yang mendorong mereka.” – Mary Doria Russell, The Sparrow.
Bayangkan Anda dihadapkan pada sebuah keputusan yang sangat dilematis: Anda memiliki peluang satu dalam satu miliar untuk menyelamatkan umat manusia dari kepunahan akibat bencana kosmik. Namun, untuk mengambil peluang itu, Anda harus mengorbankan sesuatu yang nyata, misalnya, dana besar yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan ribuan nyawa yang sekarat akibat kelaparan atau penyakit menular. Haruskah Anda mengambil keputusan tersebut?
Inilah inti dari Fanaticism, sebuah konsep etis yang menyatakan bahwa sekecil apa pun peluang untuk mencapai sesuatu yang luar biasa baik atau menghindari sesuatu yang luar biasa buruk, pengorbanan demi peluang itu tetap layak dilakukan. Dalam dunia modern, gagasan ini sering muncul dalam diskusi tentang kebijakan perubahan iklim, mitigasi risiko eksistensial, serta strategi filantropi jangka panjang.
Namun, di balik daya tarik logisnya, Fanaticism mengandung jebakan filosofis yang berbahaya. Jika diterapkan secara ekstrem, ia dapat menyesatkan pengambilan keputusan moral, membenarkan pengorbanan besar demi kemungkinan yang hampir nihil, dan pada akhirnya, menjebak manusia dalam ilusi kebaikan yang tidak pernah benar-benar tercapai.
Logika di Balik Fanaticism: Kekuatan dan Kelemahannya
Fanaticism didasarkan pada dua prinsip utama yang tampaknya masuk akal dalam teori keputusan:
- Prinsip ekspektasi utilitarian: Semakin besar manfaat yang mungkin diperoleh, semakin besar nilai moral tindakan tersebut, meskipun peluang keberhasilannya sangat kecil.
- Prinsip risiko eksistensial: Jika ada skenario yang dapat menyebabkan kepunahan umat manusia atau kerusakan besar bagi peradaban, maka mencegahnya, tidak peduli seberapa kecil peluang keberhasilannya harus menjadi prioritas utama.
Prinsip ini banyak digunakan dalam teori-teori seperti yang dikemukakan oleh Nick Bostrom (2003), yang berargumen bahwa mengurangi risiko eksistensial, bahkan dengan probabilitas yang hampir nol, lebih berharga daripada menyelamatkan ribuan nyawa saat ini. Dengan kata lain, jika ada peluang satu dalam satu triliun untuk mencegah bencana besar yang dapat memusnahkan peradaban, maka tindakan tersebut tetap memiliki nilai yang sangat besar dalam kalkulasi utilitarian.
Namun, di sinilah muncul permasalahan mendasar. Prinsip ini mengasumsikan bahwa nilai moral suatu tindakan dapat diukur hanya dengan perkalian antara manfaat yang mungkin terjadi dengan probabilitasnya, tanpa mempertimbangkan dimensi moral lain seperti keadilan, keseimbangan prioritas, dan konsekuensi yang lebih nyata dalam jangka pendek.
Jika diterapkan secara ekstrem, Fanaticism bisa membenarkan keputusan yang absurd, seperti mengalokasikan semua sumber daya manusia untuk mencegah kemungkinan kecil bencana kosmik sambil mengabaikan jutaan orang yang saat ini menderita kelaparan. Secara logis, konsep ini tampaknya kokoh, tetapi secara moral, ia mulai retak.
Ketidakseimbangan dalam Pengorbanan
Salah satu kelemahan utama Fanaticism adalah kecenderungannya untuk menciptakan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan moral. Jika kita selalu menimbang manfaat besar dalam jangka panjang dengan mengabaikan kemungkinan keberhasilannya yang hampir nihil, kita berisiko mengorbankan solusi nyata bagi permasalahan yang lebih konkret.
Sebagai contoh, bayangkan seorang filantropis memiliki dana sebesar satu miliar dolar. Ia dapat memilih antara dua opsi berikut:
- Menggunakan dana tersebut untuk membangun sistem kesehatan di negara berkembang yang akan menyelamatkan jutaan nyawa dalam beberapa dekade ke depan.
- Menggunakan dana tersebut untuk mendanai riset teknologi spekulatif yang mungkin dapat mencegah skenario bencana eksistensial di masa depan, meskipun peluang keberhasilannya hanya 0,0000001%.
Dalam logika Fanaticism, opsi kedua tampaknya lebih rasional karena nilai potensialnya sangat besar. Namun, secara moral, pilihan ini bermasalah karena mengabaikan kebutuhan mendesak yang lebih pasti dan lebih konkret.
Kita dapat melihat fenomena serupa dalam kebijakan publik dan keuangan global. Banyak negara menghabiskan miliaran dolar untuk proyek-proyek dengan hasil spekulatif, sementara masalah sosial yang lebih nyata, seperti pendidikan dan kesejahteraan, sering kali diabaikan. Fanaticism dalam bentuk ini bukan hanya irasional, tetapi juga berbahaya karena dapat mengarah pada keputusan yang tidak berimbang dan tidak manusiawi.
Mengapa Fanaticism Masih Dipertahankan?
Pendukung Fanaticism sering kali membela pandangan ini dengan merujuk pada sejarah. Mereka berargumen bahwa banyak kemajuan besar dalam sains dan teknologi berasal dari investasi pada peluang yang tampaknya sangat kecil. Misalnya, penelitian tentang vaksin awalnya dipandang sebagai proyek dengan probabilitas keberhasilan yang rendah, tetapi hasilnya kini menyelamatkan jutaan nyawa.
Namun, ada perbedaan fundamental antara Fanaticism dan pengambilan risiko yang rasional. Dalam kasus vaksin, keputusan untuk berinvestasi didasarkan pada pemahaman ilmiah yang berkembang dan hasil yang terukur, bukan sekadar harapan bahwa kemungkinan sekecil apa pun layak diperjuangkan. Fanaticism, di sisi lain, sering kali mengabaikan pertimbangan pragmatis ini dan hanya bergantung pada logika matematis yang tidak mempertimbangkan keterbatasan dunia nyata.
Menyeimbangkan Visi Jangka Panjang dan Kebutuhan Nyata
Fanaticism menghadirkan dilema menarik dalam filsafat moral. Di satu sisi, ia mendorong kita untuk berpikir jangka panjang dan mempertimbangkan dampak besar dari keputusan kita. Namun, di sisi lain, ia juga mengarah pada pengabaian terhadap kebutuhan mendesak yang lebih nyata dan konkret.
Jika kita hanya mengikuti logika Fanaticism, maka tidak ada batasan rasional dalam pengambilan keputusan. Kita bisa terus mengalokasikan sumber daya demi kemungkinan yang semakin kecil, hingga akhirnya kita kehilangan kemampuan untuk bertindak secara efektif dalam dunia nyata.
Sebaliknya, pendekatan yang lebih masuk akal adalah dengan tetap mempertimbangkan probabilitas dan nilai ekspektasi dalam keputusan etis, tetapi tanpa mengorbankan akal sehat dan keseimbangan moral. Kita perlu membedakan antara mengambil risiko yang rasional dan jatuh ke dalam perangkap justifikasi pengorbanan besar demi hasil yang hampir mustahil.
Antara Harapan Besar dan Ilusi yang Menyesatkan
Fanaticism adalah konsep yang menggoda dalam filsafat moral karena ia menawarkan narasi yang menarik, bahwa kita harus selalu mengejar kemungkinan besar, tidak peduli seberapa kecil probabilitasnya. Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini mengarah pada dilema etis yang serius dan berpotensi menyesatkan pengambilan keputusan moral.
Sebagai gantinya, kita harus mengembangkan pendekatan yang lebih seimbang, yang mempertimbangkan manfaat jangka panjang tanpa mengabaikan kebutuhan mendesak di masa kini. Sebelum kita terjebak dalam logika Fanaticism, kita harus bertanya: Apakah kita benar-benar membuat keputusan yang rasional, atau hanya tertipu oleh ilusi harapan yang terlalu jauh untuk digapai?