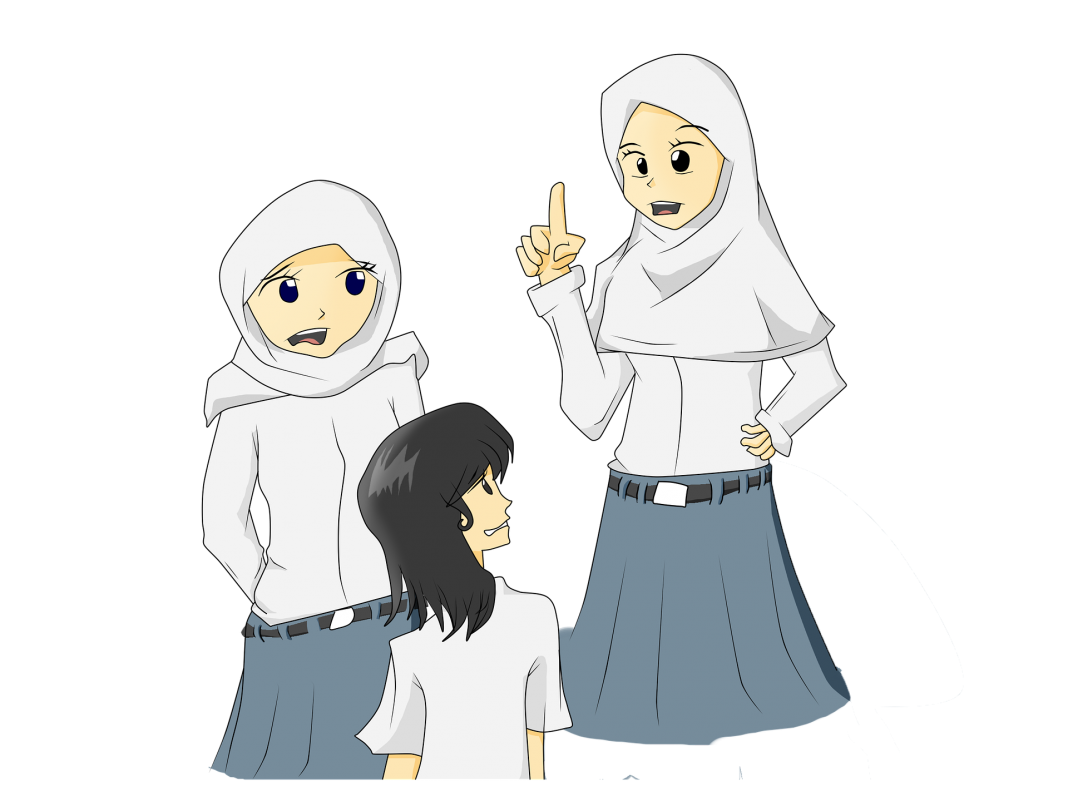Mau berjilbab atau enggak, itu urusan pribadi. Namun keharusan berjilbab di sekolah umum, baik tertulis maupun tidak, itu sudah jadi urusan publik.
Bayangkan sebuah media daring terkemuka menyebarkan berita bahwa ada beberapa sekolah negeri yang mewajibkan siswinya yang Islam berjilbab. Aturan ini tertulis, ditandatangani kepala sekolah.
Persepsi apa yang akan muncul di masyarakat? Ada yang setuju, ada yang tidak, tentu saja. Itu hal yang biasa. Tapi menjadi menarik jika kita membedah bagaimana orang-orang bisa sampai pada kesimpulannya.
Pertama, tentang kelompok yang setuju. Secara umum, argumen kelompok ini didasarkan pada tafsir hukum Islam yang sudah kokoh di benak masyarakat. Bahwa perempuan muslim ya memang seharusnya berjilbab, wajib, apalagi sudah memasuki usia dewasa. Bagian tubuh yang termasuk aurat, seperti rambut, harus ditutup. Kalau tidak, si punya tubuh akan mendapatkan siksaan di akhirat.
Percaya tafsir seperti ini sah-sah saja, bebas, selama masih dalam lingkup pribadi dan keluarga. Namun, jika sudah memasuki lahan publik, dalam hal ini sekolah umum, tafsir kita akan berinteraksi dengan tafsir orang lain. Kan ada juga orang yang menganggap bahwa tidak masalah kok perempuan muslim nggak pakai jilbab, yang penting kan tetap rajin ibadah.
Juga ada kan yang suka pakai jilbab tapi nggak panjang-panjang amat. Cukup sampai leher saja. Dan tentunya ini beda sama kelompok orang yang percaya bahwa perempuan muslim seharusnya memakai jilbab hingga menutup dada dan mengenakan cadar.
Beragam cara pandang dalam beragama ini perlu diakomodasi oleh sekolah umum. Kenapa? Alasannya sederhana sekali, yaitu karena sekolah umum adalah fasilitas publik. Sebagian besar biaya operasionalnya disokong oleh pemerintah.
Jadi, karena ia fasilitas publik, aturan di dalamnya tidak boleh memanjakan pandangan kelompok tertentu dan meminggirkan kepercayaan kelompok lain. Fasilitas publik memang seharusnya diawasi agar tetap berfungsi sebagai ruang berinteraksi antar-kelompok yang berbeda cara pandang baik dalam agama, adat-istiadat, sampai urusan etika.
Kecuali kalau sekolahnya swasta. Misalnya kelompok yang setuju ini ingin mendirikan sekolah sendiri dengan biaya urunan dari anggota lalu mewajibkan seluruh siswinya memakai berjilbab hingga menutupi dada, ya silakan saja.
Kelompok kedua, yang tidak setuju sama aturan wajib berjilbab, bisa juga terseret ke dalam cara berpikir yang bermasalah. Misalnya, ada yang berpendapat bahwa sekolah umum, yang dibiayai masyarakat, seharusnya hanya mengatur nilai-nilai umum saja dalam urusan seragam.
Contohnya, sekolah menengah atas mengatur seragam siswa harus menutupi alat kelamin, bajunya kemeja berkerah, memakai sabuk, dan warnanya putih abu-abu. Selebihnya, yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan, diserahkan pada pribadi siswa masing-masing. Mau pakai rok pendek kek, rok panjang kek, jilbab lebar kek, atau cadar kek, ya terserah siswinya dong.
Sekolah jangan ngatur-ngatur muridnya harus pakai jilbablah, harus pakai rok pendeklah. Murid harus diberi kebebasan memilih. Dan apabila para siswi sudah tidak merasa ada paksaan dalam memilih mode pakaian sekolah, berarti sudah tidak ada masalah di sekolah tersebut.
Masalahnya, argumen di atas melupakan fakta bahwa murid tidak bebas memilih. Keputusannya untuk memakai rok pendek atau jilbaban atau memakai cadar ke sekolah, sangat kuat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.
Di lingkungan sekolah, ia akan berinteraksi dengan guru, teman-teman seangkatan, kakak kelas, adik kelas, dan juga tukang kebun. Ketika ada seorang perempuan muslim tidak berjilbab dan merasa oke-oke saja dengan penampilannya lalu ia masuk di sebuah sekolah yang kepala sekolahnya, guru-gurunya, murid-muridnya, bakul nasinya.’
Hingga tukang kebunnya percaya bahwa perempuan muslim wajib berjilbab kalau tidak akan disiksa di akhirat dan mereka merasa punya kewajiban untuk mengingatkan perempuan yang belum memenuhi standar kepercayaannya, apa yang akan terjadi? Masa depan memang sangat sulit diprediksi.
Tapi, saya yakin kuping si perempuan tadi sehari-harinya akan dihinggapi suara semacam “kapan hijrah?”, “perempuan muslim itu wajib lho memakai jilbab”, “kamu kayaknya cantik deh kalo pakai hijab”.
Dan bisa saja gurunya mengatakan hal ini di kelas saat mengajar matematika: adalah dosa besar bagi perempuan muslim yang memperlihatkan rambutnya kepada yang bukan muhrimnya, dan mereka akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Kalimat-kalimat di atas tidak bersifat memaksa. Juga tidak tertulis.
Bagaimana kelompok orang yang percaya bahwa “asalkan si murid perempuan tidak merasa terpaksa mengenakan hijab saat memasuki sekolah, ya sah-sah saja” menyikapi contoh kejadian di atas?
Saya punya pengalaman menarik terkait hal ini. Ketika saya kuliah di Bogor, seorang dosen perempuan paruh baya tak pernah lupa menyinggung soal jilbab tiap kuliah. Seakan itu adalah template mengajarnya. Kalimatnya tak jauh beda dengan ucapan guru matematika yang saya ceritakan tadi.
Selain di ruang kelas, para mahasiswi ini juga mendapatkan suasana yang serupa di asrama, dan juga di beberapa organisasi mahasiswa. Entah ini berhubungan atau tidak, tapi di akhir-akhir pertemuan kuliah, tiga perempat mahasiswi yang sebelumnya tak berjilbab menjadi berjilbab. Kira-kira, kalau ditanya, apakah mahasiswi tersebut merasa terpaksa? Saya sih yakin mereka akan merasa melakukan hal tersebut atas keputusannya sendiri. Tidak ada paksaan. Ia merasa bebas memilih.
Artinya, menilai sebuah sekolah dari segi ketersediaan ruang berinteraksi kelompok-kelompok yang berbeda pandangannya dalam urusan jilbab tidak hanya dengan cara bertanya pada para siswi apakah ia mendapatkan paksaan untuk berjilbab atau tidak.
Tapi dibedah lagi: apakah sekolah tersebut menyediakan ruang yang lapang bagi kelompok-kelompok yang beragam untuk saling berinteraksi? Atau sekolah malah menutup ruang itu dengan sedemikian cara sehingga murid-muridnya tidak punya pilihan lain selain mengikuti “budaya” (aturan tidak tertulis) yang sudah berlangsung?
Sebagian pembaca mungkin heran, lho kok sekolah jadinya ikut campur? Ya iya dong. Sekolah memang harus ikut campur. Sekolah umum kan dibiayai negara. Dan negara punya kepentingan untuk menjaga ruang keberagaman tetap jembar, demi kerukunan. Sekolah harus ramah bagi beragam pilihan, baik yang suka pakai rok pendek, berjilbab, bercadar, dll dll.
Jadi diusahakan sejak dini. Bukan pas ada kejadian intoleransi kita baru teriak sana-sini mengajak orang-orang untuk saling menghargai, toleransi, dan hidup rukun.