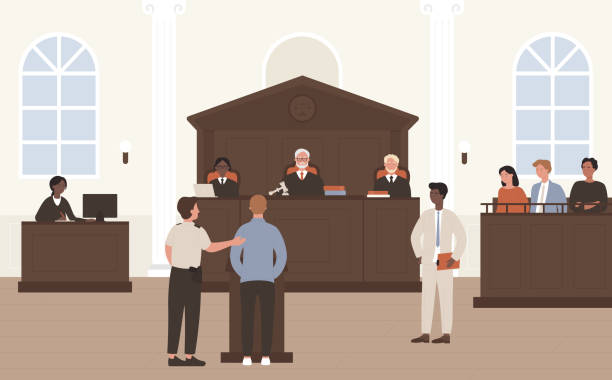Oknum merupakan lagu lama yang sering dipakai oleh pihak kepolisian dalam berdalih saat terjadi kasus yang menyeret nama baik institusi kepolisian. Kasus yang menyeret institusi kepolisian merupakan mimpi buruk bagi nama baik institusi penegak hukum ini.
Kepercayaan rakyat menjadi faktor penentu dimana kepolisian akan tetap dipercaya menjadi penegak hukum atau tidak. Memang secara de jure institusi kepolisian dilindungi oleh undang-undang, namun apakah secara de facto institusi kepolisian dipercaya oleh masyarakat?
Kita berkaca pada kasus FS, dimana penanganan kasus berjalan rumit yang demikian merupakan sesuatu yang kontradiktif secara konstitusional. Hal semacam inilah yang membuat rakyat berprasangka bahwa pihak kepolisian terlihat sangat berhati-hati dalam menyusun skenario penindakan anggotanya.
Terlebih beberapa saksi yang dihadirkan justru menampilkan kesaksian yang cenderung mengada-ada. Hal ini tentu saja dapat menjadi bumerang terhadap FS sekaligus institusi dimana dirinya bertugas.
Ramai di khalayak media sosial yang melayangkan tagar #percumalaporpolisi sebagai reaksi terhadap tindakan para ‘oknum’ yang selalu disebut pada setiap kasus dimana terdapat nama kepolisian di dalamnya. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena hal tersebut juga merupakan implementasi dari bersuara dan berpendapat.
Akan tetapi, tindakan represif dari aparat merupakan rintangan yang berat dimana suara dibungkam. Tanggapan yang seharusnya dilakukan dengan prinsip pervasion (dilakukan tanpa kekerasan) malah dilakukan dengan cara yang koersif. Hal ini sangat disayangkan karena kemanusiaan cenderung diabaikan demi sebuah kepentingan. Such a shame to hear that!
Aparat yang seharusnya melindungi dan mengayomi nyatanya malah mencederai nilai-nilai sakral demokrasi. Hal ini tentu saja sangat kontradiktif dengan nilai-nilai yang tertera pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah untuk “melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Sekali lagi, ekspektasi tidak sebanding dengan realita yang ada di lapangan.
Framing yang dilakukan oleh aparat kepolisian juga terkesan percuma karena kredibilitas institusi telah tercoreng akibat runtutan kasus yang dimulai dari kasus FS, pelecehan terhadap TNI, hingga yang paling membekas adalah Tragedi Kanjuruhan. Kepolisian dituntut dengan tingkat profesionalitas yang tinggi, bukan hanya arogansi yang ditampilkan dalam implementasi demokrasi.
Profesionalisme berarti mutu, kualitas, dan segala tindak tanduk yang menjadi ciri khas suatu instansi. Dengan banyaknya kasus yang terjadi di negara ini, apakah demos atau rakyat bisa menilai profesionalitas dari institusi kepolisian? Bagaimana bisa rakyat percaya dan terbuai dengan aksi-aksi heroik yang dinarasikan oleh kepolisian untuk menghilangkan citra buruk insitusi tersebut.
Apabila semua tindakan koersif serta represif dilakukan secara terus menerus, maka yang akan terjadi hanyalah fantasi utopis mengenai implementasi demokrasi. Law in the book harus menjadi law in action supaya bibit-bibit otoritarianisme tidak tumbuh subur. Indikasi otoritarianisme ini dapat dilihat dengan berlangsungnya politik identitas sebagai akar kekuatan rezim.
Rezim menggunakan aparat penegak hukum sebagai kontrol sosial terhadap ancaman yang berpotensi untuk mengganggu keberlangsungan hegemoni rezim yang berkuasa. Pada akhirnya, aparat penegak hukum hanya akan membungkam suara lantang yang sedang memperjuangkan hak-haknya.
Masyarakat berpikir bahwa mereka akan dilindungi oleh Hak Asasi Manusia (HAM) yang turut mempengaruhi undang-undang yang berlaku. Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa sistem yang berlaku adalah produk dari otoritarianisme yang berjalan. Mana mungkin `sang penguasa` akan mengambil kebijakan tanpa pengaruh mastermind di balik jalannya rezim? Seperti yang kita ketahui bahwa penerapan pidana seringkali tidak tepat sasaran dan cenderung tumpul ke atas.
Hal tersebut juga merupakan pengantar negeri ini untuk terjun ke jurang kematian demokrasi. Hukum yang berlaku juga merupakan salah satu produk dari perancang sistematika negara ini. Seperti kritik yang dilontarkan oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. mengenai sistem hukum di Indonesia yang menjelaskan bahwa tindakan kriminal, terutama korupsi, semakin dipermudah oleh undang-undang karena koruptor merupakan salah satu dari perancang undang-undang tersebut. Undang-undang yang seharusnya tidak subjektif dalam menindak para pelaku kriminal.
Abuse of power juga dapat kita dapati dimana sesama wakil rakyat membungkam suara satu sama lain. Jika individu yang memiliki kedudukan yang setara saja dapat dibungkam dengan mudah melalui mikrofon, lalu bagaimana nasib suara rakyat yang berasal dari kaum marjinal? Bukankah mereka harusnya menjadi wadah aspirasi rakyat dan harus menghindari praktik politik identitas?
Memang secara normatif para wakil rakyat seharusnya mendengar keluhan dan aspirasi rakyat. Akan tetapi, mereka seakan lupa akan tupoksi yang telah dibebankan kepada mereka. Sumpah serta janji mereka terlihat hanya seperti formalitas tekstual saja. Mereka ingin menjadi tuhan-tuhan baru yang berkuasa di negeri yang akan terjun di lembah anarki.
Hal ini bisa menjadi sarana introspeksi bagi para elit politik serta seluruh jajaran institusi terkait. Perwujudan demokrasi harus diimplementasikan secara nyata, bukan sebatas teori-teori politis belaka. Dapat kita amati bahwa segala framing yang dilakukan baik melalui media sosial atau bahkan pengalihan isu terbilang percuma karena skenario yang ada dapat terbaca. Segala intrik dan konflik di permainan politik hanya terasa menggelitik karena rakyat negeri ini sudah kian cerdik.