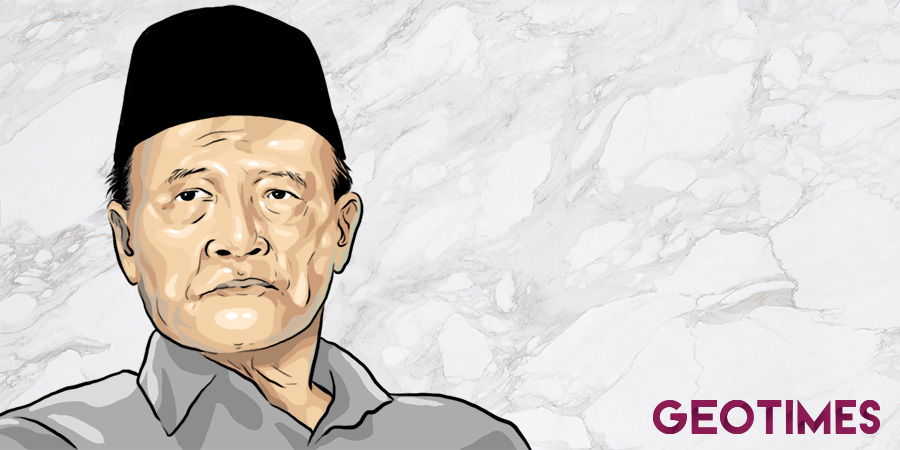Setidaknya, terdapat tiga orang yang dijuluki sebagai guru bangsa. Pertama, almarhum Nurcholis Madjid, pendekar pembaharu Islam dari Chicago. Cak Nur, begitu sapaan akrabnya, lulus dengan disertasi Ibnu Taimiyah Tentang Falsafah dan Kalam.
Ibnu Taymiyyah, yang selama ini dianggap sebagai pemikir Islam yang menentang habis-habisan ilmu filsafat dan kalam tidak terbukti. Itu dibuktikan dengan kedalaman analisis Cak Nur mengenai pemikiran Ibnu Taymiyyah. Mungkin, itulah salah salah satu alasan dari sekian banyak alasan mengapa beliau pantas didapuk sebagai guru bangsa. Pemikiran keislamannya selalu segar, relevan, dan tentunya mengajak orang-orang “berkelahi”.
Kedua, almarhum Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Sebagai tokoh yang dihormati di kalangan Nahdliyin, pemikiran-pemikirannya selalu mengacu pada kondisi kebangsaan mutakhir Indonesia dengan balutan gagasan keislaman yang khas berkat pengetahuannya yang begitu luas mengenai turats atau tradisi Islam klasik dan modernitas.
Gagasannya yang kontroversial, pribumisasi Islam, mendapat kecaman dari berbagai pihak. Namun, gagasan tersebut lantas menjadi bahan diskusi menarik hingga sekarang. Humor-humornya mengenai kondisi sosial keindonesiaan juga selalu nampak relevan. Kebesaran hatinya untuk turun dari tahta kepresidenan membuat banyak orang takjub.
Bukan karena kesukarelaannya mengundurkan diri, tetapi pernyataannya yang membuat orang-orang pengejar jabatan merinding, “Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian. Presiden itu cuma apa sih”, ujarnya dengan tegas. Ialah guru bangsa yang mengajari anak-anak bangsanya untuk menghadapi masalah dengan besar hati.
Ketiga, almarhum Ahmad Syafii Maarif. Beliau satu almamater dengan Cak Nur di Universitas Chicago. Buya Syafii, sapaan akrabnya, juga berhak menyandang gelar guru bangsa. Bahkan, ia seringkali disebut sebagai muadzin moralitas bangsa. Seakan tidak pernah lelah, ia selalu mengingatkan anak-anak bangsa untuk selalu mengedepankan moralitas dalam menyelesaikan problematika kebangsaan yang dihadapi.
Kejernihannya dalam memandang problematika kebangsaan membuat orang-orang mengacungi jempol. Tetapi tidak jarang pula ia dihujat. Wajar saja jika seorang yang tidak mempunyai kepentingan politik seperti Buya Syafii berbicara apa yang diyakininya, walaupun banyak bertentangan dengan mayoritas masyarakat.
Buya Syafii sendiri merupakan seorang yang memiliki dinamika tersendiri dalam perjalanan intelektualnya. Dahulu, ia merupakan pendukung garis keras negara Islam. Beliau mempertegas fakta tersebut dalam autobiografinya, Tititk-titik Kisar di Perjalananku. Setelah bertemu cendekiawan Muslim berpengaruh asal Pakistan, Fazlur Rahman, beliau sedikit demi sedikit mengubah pandangan keagamaannya yang tadinya ingin mendirikan negara Islam menjadi pendukung demokrasi.
Kasus Ahok seringkali disinggung untuk menjatuhkan martabat beliau. Namun itu tidak berpengaruh kepadanya, sebab ia mengatakan apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Kebenaran sama sekali tidak mengikuti kemauan orang kebanyakan, begitu yang diyakini nya.
Esai singkat ini ingin sedikit memaparkan pikiran-pikiran Buya Syafii mengenai demokrasi. Sebagai salah satu guru bangsa, pemikiran beliau patut direnungkan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mencintai demokrasi.
Otoritasnya dalam membahas demokrasi tidak perlu diragukan. Bahkan beliau telah mempraktekkannya secara langsung. Terdapat banyak sekali kisah-kisah yang dapat dituliskan mengenai perjuangan Buya Syafii untuk menegakkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Namun, kiranya perlu kita memahami bagaimana pemikiran demokrasi Buya Syafii itu sendiri sehingga dapat tercermin dalam perilaku sehari-harinya?
Demokrasi dalam Pandangan Buya Syafii
Alois Agus Nugroho, Professor of Ethics and Philosophy, Universitas Atma Jaya, Jakarta, memetakan ada empat pokok pikiran Buya Syafii mengenai demokrasi.
Pertama, tentang etika politik demokrasi. Mengacu pada pemikiran Buya Syafii mengenai kehidupan bernegara.
Kedua, etika politisi dan birokrat. Buya Syafii senantiasa mengingatkan para politisi dan birokrat untuk bekerja di bawah kode etik yang mengedepankan kemanusiaan.
Ketiga, etika sosial yang menghormati kemajemukan dan kesetaraan. Ini selaras dengan komitmen Buya Syafii yang selalu menyerukan pluralisme.
Keempat, etika global. Pemikiran Buya Syafii mengenai demokrasi bukan hanya berbicara pada konteks keindonesiaan, melainkan juga dunia seluruhnya. Buya Syafii hingga akhir hayatnya mengikuti pemberitaan mutakhir dunia Arab, khususnya, sebagai representasi masyarakat Islam. Ia selalu melontarkan kritik tajam terhadap perkembangan demokrasi di dunia Arab yang masih seperti anak bayi yang merangkak.
Demokrasi dapat dipadankan dengan kata musyawarah dalam Al-Qur’an. Islam sejatinya menuntun umat manusia ke jalan rahmat. Kasih sayang sesama manusia menjadi acuan utama dalam menjalani kehidupan di muka bumi. Politik, yang notabene mengatur hubungan antara sesama manusia harus menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan tersebut.
Tidak ada perintah dalam ajaran Islam untuk mendirikan suatu negara tertentu. Buya Syafii sepakat bahwa Rasulullah tidak pernah mendirikan negara. Ini sesuai dengan perintah Al-Qur’an, bahwasanya Rasulullah hanyalah seorang Rasul, bukan sosok penguasa politis.
Bagi Buya Syafii, Al-Qur’an adalah pedoman etik bagi kaum muslimin. Apapun bentuk negara yang didirikan, jangan lupa dengan prinsip etik kemanusiaan yang sudah sewajarnya menjadi landasan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Justru dalam pandangan Al-Qur’an, demokrasi yang dibahasakan melalui musyawarah harus menjadi landasan bernegara bagi kaum muslimin tanpa membeda-bedakan warga negara. Semuanya setara di hadapan Tuhan. Ketakwaanlah yang menentukan ukuran kualitas seseorang.
Sebagai pengagum Moh. Hatta, demokrasi bukan hanya mengenai kebebasan praktik politik di suatu negara. Demokrasi bukan hanya pada tataran politik. Demokrasi ekonomi perlu juga dijalankan. Inilah yang sering menjadi sasaran kritik Buya dalam pernyataannya, “Jangan biarkan sila ke-lima itu mengawang-ngawang di langit. Tarik dia turun ke bumi”, tegasnya. Artinya, selama ini sila ke-lima pancasila belum diterapkan dalam negeri ini, khususnya dalam bentuk kebijakan. Buktinya, kemiskinan masih menjadi makanan sehari-hari bagi mayoritas rakyat Indonesia.
Buya Syafii meyakini bahwa negara Indonesia terbentuk atas dasar kontrak sosial. Kontrak sosial tersebut terbentuk melalui sejarah panjang bangsa Indonesia. Pandangan Buya Syafii mengenai pasang surut pembentukan identitas keagamaan dan kebangsaan masyarakat Indonesia tercermin dalam bukunya, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan.
Melalui refleksi sejarah, Buya Syafii mengingatkan bangsa Indonesia agar menghargai jasa pahlawan. Atas jasa mereka, bangsa Indonesia bisa merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Pembentukan identitas keagamaan dan kebangsaan tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Dua identitas tersebut menyatu dalam darah seorang manusia Indonesia sehingga tidak perlu dipertentangkan.