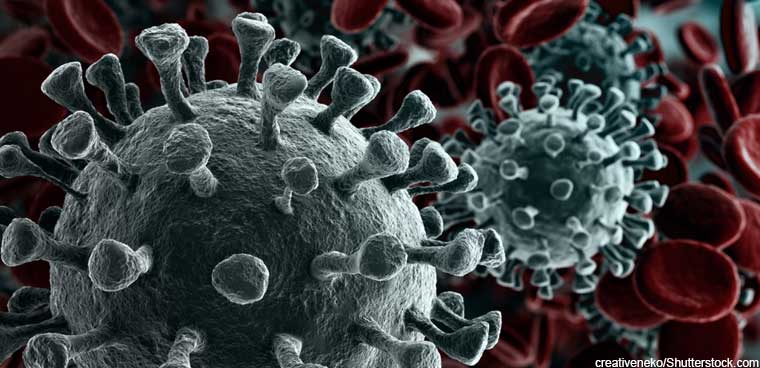Memang, Indonesia baru mengkonfirmasi secara resmi kasus pertama Corona pada 2 Maret 2020. 28 Hari yang lalu. Namun selama itu, jumlah kasus positif Covid-19 tumbuh secara eksponensial. Tercatat per 29 Maret 2020, jumlah kasus positif mencapai 1.414 orang. Dan jumlah itu sepertinya belum akan berhenti bergerak secara eksponensial di dalam waktu dekat.
Berbagai prediksi kemudian dibuat. Salah satunya yang dirilis 27 maret kemaren oleh Tim FKM UI. Dilansir detikcom (27/3) Mereka menyatakan bahwa, di dalam kondisi tanpa intervensi maka lebih kurang 2.500.000 orang berpotensi terjangkiti Coronovirus pada hari ke 77 sejak awal penularan dengan jumlah yang meninggal lebih kurang 240 ribu.
Tentu kita tidak menghendaki skenario tersebut terjadi. Bahkan pada kondisi di bawah intervensi tinggi pun, jumlah 500 ribu kasus positif tetaplah jumlah yang sangat besar. Belum lagi jumlah kasus kematian pada kondisi High intensity juga sangat tinggi, yaitu 11 ribuan. Kondisi tersebut lebih tinggi dari kondisi yang dihadapi oleh Amerika Serikat, Italia, dan China saat ini, yang merupakan tiga negara terdampak paling parah dari wabah Covid-19. Mengerikan? Ya.
Namun, seandainya kondisi itu menjadi kenyataan apa yang akan terjadi? Dan bagaimana mengatasinya? Dua pertanyaan itu yang akan saya coba jawab di dalam tulisan ini.
Runtuhnya sistem kesehatan
Perang melawan virus ataupun bakteri bukanlah hal yang baru bagi manusia. Di zaman pra-modern, makhluk mikroskopis tersebut sering membawa malapetaka dalam peradaban manusia. Pada abad ke 14 misalnya, kematian hitam atau the black death menewaskan 75 juta sampai 200 juta orang di seluruh dunia.
Bahkan, Inggris harus kehilangan sekurangnya 40% dari jumlah penduduknya saat itu. Setali tiga uang, pada waktu yang lebih dekat dari sekarang, tahun 1918 setidaknya 50 – 100 juta orang tewas diakibatkan oleh flu spanyol, dan menginfeksi sekitar setengah miliar penduduk dunia atau seperempat dari spesies manusia yang ada saat itu.
Kita tentu tidak berharap Covid-19 ini akan berdampak semasif pendahulunya Yersinia Pestis atau H1N1 itu. Dan dengan kecanggihan ilmu kedokteran dan biologi (biologi molekuler atapun virologi) kita boleh sangat optimis bahwa itu tidak akan terjadi.
Namun, keadaan yang ada sekarang, dengan 660 ribu orang yang terinfeksi dengan lebih dari 30 ribu yang meninggal membuat kita sedikit gusar. Bahwa public health service yang kita (baca:peradaban modern) bangun tidak cukup mampu mengantisipasi dan menanggulangi wabah. Sekurangnya kasus seperti itu sudah kita lihat di Italia dan mungkin sebentar lagi juga terjadi di Indonesia.
Kita layak khawatir, dibandingkan dengan Italia, layanan kesehatan Indonesia mungkin tidak lebih baik. Dengan skala wabah yang baru 1% dari apa yang terjadi di Italia, layanan kesehatan kita sudah kewalahan. Berita tentang kurangnya APD, respirator, ataupun ruang perawatan hanyalah sedikit bukti bahwa layanan kesehatan Indonesia tidak siap menghadapi wabah.
Jika kemudian kita hubungkan dengan prediksi dari Tim FKM UI tentu akan membuat kita bergidik. Apa jadinya jika itu benar terjadi? Dalam kondisi ekstrem maka jawabannya adalah runtuhnya Layanan kesehatan Publik. Dan tentu itu skenario yang menakutkan, bukan saja dampaknya secara kesehatan tetapi juga sosial dan politik.
Akan terjadi kepanikan dan ketakutan massal yang bisa berujung pada kondisi chaos. Kita tidak berharap itu terjadi. Tapi jika melihat kondisi yang ada sekarang, bukankah harapan kita adalah itu benar-benar tidak terjadi?
Terbatasnya opsi kebijakan
Tadi itu terdengar sangat pesimis dan suram. Bukankah Public Policy harus selalu menyediakan alternatif bahkan ditengah krisis? Begitulah kebijakan. Kebijakan harus membawa perbaikan terhadap masalah yang ada. Itulah landasan etis dari sebuah kebijakan publik.
Sayangnya sekarang kita memiliki opsi kebijakan yang terbatas. Social distancing atau sekarang physical distancing hanyalah cara untuk mengulur waktu agar tidak terjadi lonjakan kasus secara eksponensial yang nantinya memberatkan public health service. Ditambah dengan kondisi masyarakat kita yang tidak disiplin membuat kedua distancing tadi sekurangnya sampai saat ini terlihat tidak efektif.
Kemudian debat publik membawa kita pada opsi lock down atau karantina. Kita punya succes story kebijakan ini, yaitu China. Kurang dari 2 bulan semenjak kebijakan diambil, Wuhan yang menjadi pendemik awal covid-19 menunjukkan penurunan kasus positif bahkan hampir zero case.
Italia, spanyol, Inggris, Prancis, Jerman, Malaysia, India, Filiphina dan beberapa negara lainnya kemudian mengambil kebijakan yang sama, yaitu me-lock down wilayahnya untuk mengurangi perluasan penyebaran virus. Meskipun di negara-negara tersebut belum memperlihatkan hasil seperti di Wuhan tapi itu cukup membuat publik mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan yang sama.
Namun, pemerintah sepertinya enggan. Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat menjadi alasan pemerintah keberatan mengambil opsi ini. Sehingga sampai saat ini, debat tentang lock down atau tidak kemudian menjadi debat yang tidak berujung. Meskipun beberapa daerah sudah mulai menerapkan kebijakan lock down secara sendiri-sendiri namun itu sepertinya tidak akan efektif.
Lockdown hanya cara bertahan, kita butuh menyerang!
Kenapa tidak efektif? Ada tiga alasan yang membuat saya sedikit skeptik dengan kebijakan model lock down atau karantina ini. Pertama, lock down atau karantina haruslah berupa kebijakan yang dilakukan secara global. Sebab pengendalian epidemi (wabah) bukan hanya kepentingan nasional apalagi daerah.
Sayangnya, mengharapkan terjadinya konsensus internasional seperti itu suatu hal yang nyaris mustahil untuk saat ini. Kedua, jika kebijakan itu dilakukan secara parsial, pertanyaannya berapa lama suatu negara mampu mengunci wilayahnya? di mana di saat yang bersamaan negara-negara lain masih terinfeksi virus. Ketiga, kebijakan mengunci negara merupakan kebijakan yang mahal sehingga dapat menyebabkan keruntuhan ekonomi. Apalagi bagi negara-negara berkembang yang kemampuan ekonominya terbatas seperti Indonesia.
Mungkin hal terpenting yang harus disadari orang tentang epidemi semacam ini adalah bahwa penyebaran epidemi di negara mana pun membahayakan seluruh spesies manusia. Oleh sebab itu, mengutip Yuval Noah Harari dalam artikelnya yang berjudul “In the Battle Against Coronavirus, Humanity Lacks Leadership” menyatakan bahwa …the best defense humans have against pathogens is not isolation – it is information.
Oleh sebab itu, lock down hanyalah “kebijakan bertahan” yang bisa kita lakukan dengan berbagai pertimbangan. Yang seharusnya dilakukan sekarang adalah berbagi informasi dan kerjasama ditingkat global dari berbagai pihak bukan saja government actors tapi juga non-government untuk berhimpun daya menemukan dan memproduksi vaksin. Seperti yang dikatakan oleh Bill Gates, vaksin merupakan satu-satunya cara untuk mengalahkan corona.