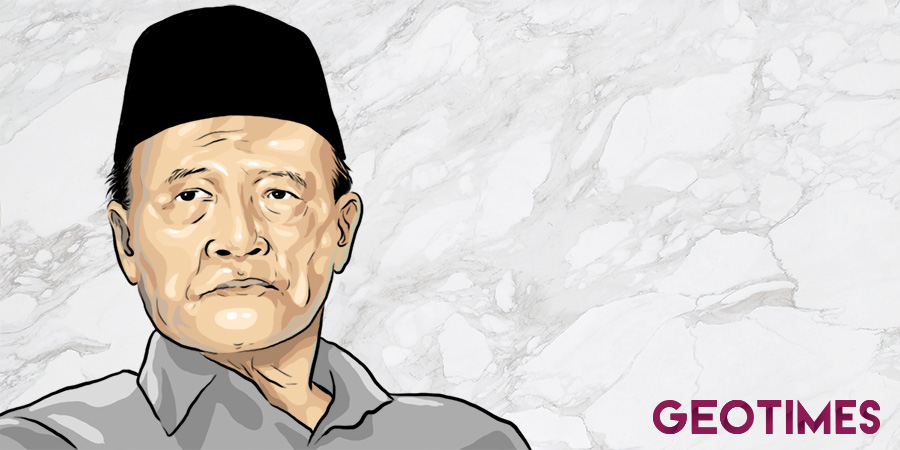Buya Syafii, satu di antara pendekar dari Chicago—meminjam istilah Gus Dur—Jumat lalu, 27 Mei 2022 sudah pergi meninggalkan kita. Kita semua tentu merasa sangat kehilangan.
Cerita kehidupan Buya, adalah cerita keteladanan, cerita seorang cendekiawan dengan kepribadian yang humanis, yang memandang bahwa setiap manusia—apapun agamanya, keyakinannya, suku, etnis, budaya—harus dihormati sebagai seorang manusia seutuhnya.
Tak heran, jika berita tentang wafatnya Buya, menyisakan duka yang mendalam, bukan hanya keluarga yang ditinggalkan, atau di lingkungan Muhammadiyah sebagai rumah ideologisnya, tetapi juga bangsa Indonesia kehilangan sosok yang tak pernah absen di ruang kelas keindonesiaan, keislaman, dan kemanusiaan.
Berita wafatnya Buya, menyapu sudut-sudut halaman nusantara ini ; di warung kopi, bengkel sepeda, tukang kayu, pasar-pasar tradisional, di pesisir laut, alun-alun kota, dan tentu saja di kalangan pendidik, politisi, pengusaha, birokrat, dan kawiwara. Di mana-mana tak pernah sunyi dari obrolan tentang Buya Syafii.
Buya, bukan hanya menjadi guru inspiratif bagi keluarganya, murid-muridnya, para jamaahnya, tetapi juga guru inspiratif bagi bangsanya.
Nama Buya Syafii akan terus hidup di hati masyarakat. Sosok yang tak pernah berhenti memikirkan bangsanya, seorang humanis yang selalu mengajak bangsa besar ini untuk bangun dari ketertinggalan. Sosok guru bangsa, yang spirit keindonesiaan dan humanismenya tak diragukan lagi. Ajaran-ajaran bijak yang dilayarkannya melintasi agama, budaya, usia, dan kelompok, membuat siapa pun yang berdialog dengannya merasa teduh.
Buya Syafii, sepeninggal sahabatnya Cak Nur dan Gus Dur, nyaris bergerak dan berjalan sendirian. Banyak sekali orang bersetuju dengan gagasan gagasannya yang brilian nan cerdas, kritiknya yang keras, namun sedikit sekali–-atau tidak ada sama sekali—yang berani menyuarakan kebenaran di tengah rimba perebutan kepentingan dan kekuasaan.
Buya Syafii, bukanlah manusia yang datang tiba-tiba dari ruang kosong. Ia adalah sosok manusia yang tumbuh dari dentuman demi dentuman zaman. Menempuh jalan bergelombang, naik turun di sana sini. Dan, Buya—seperti yang kita saksikan sampai maut menaklukannya—tetap berdiri kokoh laksana karang di lautan.
Buya Syafii melangkah dengan pasti di tengah bising dan riuhnya paduan suara caci maki, karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka. Bahkan, Buya tidak terlalu hirau dengan persetujuan atau perlawanan. Yang beliau pedulikan adalah orang harus selalu jujur dengan hati nuraninya, bersikap adil kepada siapapun—termasuk mereka yang tidak kita sukai.
Perlu dijelaskan di sini, bahwa Buya meskipun bahasanya keras dan tajam menukik, tetapi sesungguhnya hatinya begitu sangat lembut, dan tak jarang menyungging senyum pada siapapun yang diajaknya bicara. Hatinya yang lembut, senafas dengan rasa kecintaannya terhadap seni.
Buya banyak sekali dipengaruhi oleh Mohammad Iqbal, penyair kelahiran Pakistan. Buya adalah pembaca Iqbal yang baik. Bagi Buya, Iqbal adalah seorang penyair Muslim terbesar yang dalam kurun 500 tahun terakhir diakui kepiawaiannya sebagai seorang filsuf Timur.
Nada tulisan Buya dengan spirit Iqbal ini, sering kita jumpai dan baca dalam tulisan tulisannya yang tajam. Melalui puisi Iqbal pulalah, Buya menemukan kontekstualisasi hijrah intelektualnya dari sekadar “Adat basandi syara’. Syara basandi Kitabullah” ke arah panduan kosmos “Alam terkembang menjadi guru”. Sebuah falsafah yang sangat progresif dari Minang yang cocok dengan ijtihad Iqbal.
Gagasan gagasan Buya tentang universalitas Islam dan kemanusiaan ini bisa digambarkan sebagai karya seni. Ketika karya seni itu berkualitas, maka semua orang—apapun agama dan keyakinannya—akan mengapresiasi dan menghargai.
Dan, Buya Syafii adalah karya seni, yang dihasilkan oleh lingkungan pendidikannya, oleh Muhammadiyah dan oleh bangsanya yang bisa dirasakan oleh semua orang. Buya Syafii adalah karya seni, Mahatma Gandhi adalah karya seni, Bunda Theresa adalah karya seni, Muhammad Iqbal adalah juga karya seni.
Di akhir-akhir kehidupannya, Buya adalah sosok manusia yang selalu kesepian. Mengapa saya katakan kesepian? Karena ide ide Buya yang kelewat berani. Orang tidak berani melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Buya. Buya tak pernah bisa ditundukkan oleh rasa takut. Buya tetap tegak bagaikan karang dan secara konsisten mengumandangkan kewarasan publik, dan keadaban publik.
Dan, kesepian menurut Iqbal, adalah keadaan jiwa pelakunya, tetapi kesepian itu bukanlah tujuan hidup itu sendiri. Kesepian dan kegelisahan sebagai cara berada; tetapi kesepian seperti ini bukanlah merupakan cara yang final asalkan manusia itu mau menyelami, mengakui kedudukannya sebagai Khalifah di muka bumi. Dan saya kira apa yang dialami oleh Iqbal, demikian pulalah yang dialami oleh Buya Syafii.
Di tengah krisis keteladanan, Buya Syafii adalah teladan yang sesungguhnya.
Alfatihah untuk Buya Syafii