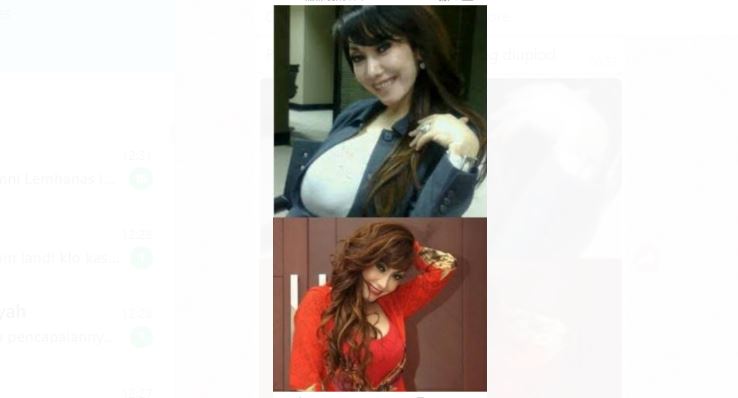Di Indramayu ada dongeng rakyat yang sangat menarik. Konon, seorang gadis miskin, Saida Saini sejak kecil bercita-cita ingin jadi orang kaya dan terkenal. Untuk meraih cita-citanya, Saida mau melakukan apa saja – bahkan mau menjadi buaya di penghujung hidupnya, asalkan kaya. Dengan sumpah setia di hadapan ratu buaya, Saida pun akhirnya menjadi sinden terkenal. Saweran dari pria yang tergila-gila padanya banyak sekali sehingga dia pun menjadi wanita yang kaya raya.
Jika di Indramayu ada Saida Saini, di Tebet, Betawi, ada Inong-Malinda Dee. Sejak kecil, Inong yang lugu bercita-cita ingin jadi orang kaya dan terkenal. Untuk mencapai kekayaannya, Inong mau melakukan apa saja.
Hidungnya yang pesek dioperasi agar bangir. Dadanya yang kerempeng, juga dioperasi agar montok. Kulitnya diperhalus dan diputihkan. Jadilah Inong seorang wanita yang sangat cantik dan menarik. Berkat kecantikannya, karir Inong di CityBank makin moncer.
Sayangnya, untuk meraih cita-citanya menjadi orang kaya raya, Inong tega membobol bank tempat kerjanya. Hasilnya: Inong benar-benar menjadi bidadari sehingga mempesona kaum sosialita metropolis. Inong berhasil merengkuh kedua cita-citanya sekaligus: menjadi cantik dan kaya raya. Secara spiritual-hedonism Inong telah berhasil “mentransendensikan” fisiknya yang riil menjadi sesuatu yang mistis dan tak terjangkau manusia awam.
Jika Saida di ujung hidupnya harus mencebur ke dalam sungai karena menjadi buaya, Inong di “penghujung” hidupnya harus mendekam dalam penjara yang pengap. Jika Saida fisiknya menjadi buaya, tapi jiwanya tetap manusia, maka Inong sebaliknya. Fisiknya tetap Inong tapi jiwanya menjadi “buaya”.
Apa yang dilakukan Saida dan Inong sebenarnya hampir sama, kecuali prosesnya. Saida menjadi kaya dan terkenal karena jebakan mistisisme lokal abad 16 sehingga kepribadiannya menjadi buaya. Yang kedua, melalui jebakan mistisisme global abad 21, Inong menjadi Dee, sebuah transformasi nama yang megikat dirinya dengan komunitas Ferari yang mewah dan mahal di kota metropolitan Jakarta.
Dee bukan sekadar deretan huruf pada nomor plat polisi Ferari milik Inong, tapi juga sebuah identitas ‘spiritual hedonism’ dalam komunitas the haves metropolis. Sayangnya, di “ujung” kehidupannya Dee terpaksa harus tinggal dalam penjara yang memisahkan dirinya secara ekstrim dari kemewahan yang selalu mengiringnya.
Lalu, salahkah jika Inong bermimpi jadi orang kaya dan terkenal di tengah kehidupan metropolis abad 21? Tidak! Begitu pula Saida yang ingin kaya dan terkenal di tengah kehidupan dusun abad 16. Yang salah, kehidupan bak mimpi itu diraihnya dengan proses yang ilegal dan irasional. Akibatnya, mereka pun mendapatkan tempat yang tidak semestinya yang tidak sesuai dengan harkat kemanusiaannya.
Saida, dalam legenda rakyat, hidup di sungai sebagai buaya, sedangkan Inong yang hidup bagai legenda, harus tinggal di penjara sebagai terpidana.
Saida dan Inong, pinjam istilah filsuf eksistensial JP Sartre — adalah potret manusia yang telah dibunuh kesadarannya sehingga perilaku hidupnya dikendalikan ketidaksadarannya. Dalam dunia filsafat, Saida dan Inong telah dibunuh kesadarannya sehingga mereka lupa akan jati dirinya sebagai manusia yang bermartabat dan terhormat.
Lalu, siapa yang membunuh Inong? Pembunuh pertama adalah Sigmund Freud. Freud adalah pembunuh kesadaran manusia yang paling brutal. Bagi Freud kesadaran manusia telah mati. Karena itu, perilaku manusia dikendalikan ketidaksadarannya. Gerakan manusia di mata Freud tak lebih dari gerakan voodoo, mayat hidup yang berjalan di kuburan-kuburan tua Haiti.
Pembunuh kedua adalah Camillo Golgi, nobelis penemu sistem saraf. Menurut Golgi, setiap sel saraf (neuron) terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam serabut saraf: dendrite dan akson. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain.
Kedua entitas dalam sel saraf inilah yang mengendalikan perilaku manusia. Apa yang disebut kesadaran manusia sebetulnya adalah reaksi neuron terhadap sebuah obyek. Dengan demikian, manusia sebetulnya tidak punya kesadaran. Ryu Hasan, dokter ahli bedah saraf menyatakan, karakter manusia merupakan hasil reaksi neuron terhadap obyek yang ada di sekitarnya.
Jika seseorang berubah sistem sel sarafnya, maka orang tersebut secara praktis sebetulnya telah berubah menjadi orang lain. Jika manusia bisa berubah menjadi orang lain hanya karena perubahan sel sarafnya, lantas apa arti jati diri dan identitas manusia? No thing.
Pembunuh ketiga adalah Michel Foucault, seorang filsuf strukturalisme. Menurut Foucault, manusia sebetulnya tidak bebas karena ia selalu terkungkung dengan berbagai faktor yang ada dalam lingkungan hidupnya. Foucault menyatakan, umat manusia tengah berada di ujung kematiannya. Ini terjadi karena manusia telah kehilangan tempatnya yang sentral dalam struktur sosial dan budayanya.
Di lihat dari filsafat strukturalisme, manusia hakikatnya telah mati karena manusia tidak punya kesadaran untuk membangun karakter dan perilaku hidupnya secara mandiri. Dari gambaran itulah mungkin kita bisa memahami perilaku Inong yang telah “mentransendensikan” dirinya dari seorang gadis lugu yang hidup di kompleks perumahan sederhana menjadi seorang sosialita yang hidup di blok apartemen mewah lengkap dengan simbol-simbol hedonisme metropolisnya.
Sebagaimana halnya Saida yang telah menjadi korban mimpi-mimpinya, Inong pun telah menjadi korban mimpi-mimpinya – meski keduanya hidup dalam rentang waktu yang amat berbeda. Inong mati karena dibunuh Freud, Golgi, dan Foucault. Ironisnya, secara tidak sadar kita senang mengikuti gaya hidup sang legenda itu.
Lalu, salahkah jika orang menyukai kisah legenda Inong? Entahlah. Yang jelas, kita memang sering lupa bahwa “kesenangan” tersebut suatu ketika bisa merasuki diri kita, dan kita terjebak dalam lakon yang sama seperti Inong. Juga Saida Saini.
Akhirnya, saat ini, ketika dunia saiber tak menyisakan perbedaan berarti antara jagad metropolis dan jagad kampung, bukan tidak mungkin jebakan pembunuhan kesadaran itu kini tengah berada di tengah kita. Untuk itulah, manusia perlu waspada dan tidak hanyut dalam hedonisme superfisial.
Sastrawan Jawa Raden Ngabehi Ronggowarsito, tiga abad lalu, pernah berpesan: sebaik-baik manusia di zaman yang edan adalah manusia yang tidak edan. Dan manusia yang tidak edan adalah manusia yang selalu eling, waspada, dan menghidupkan kesadarannya.