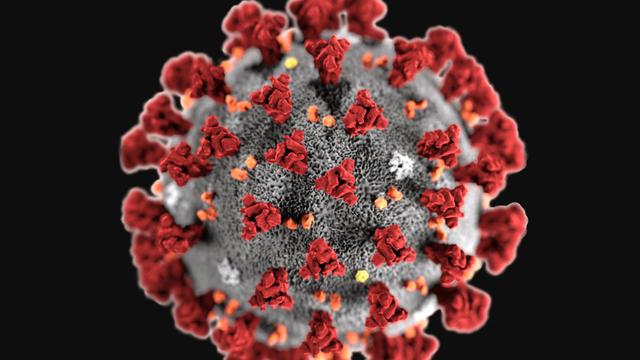Di hadapan wabah pandemi Covid-19, pengalaman penderitaan, dan kematian manusia, pertanyaan yang cukup pasti mendesak orang beriman untuk mendakwa Allah adalah apakah Allah itu ada? Apakah Allah itu Maha Penyanyang dan Maha Pengasih? Jika Dia ada mengapa manusia berjuang sendiri melawan wabah ini? Mengapa Dia diam saja? Apakah Allah tidak mampu meniadakan penderitaan? Atau barangkali Dia bisa meniadakan wabah ini tapi Dia tidak mau? Di manakah kemahakuasaan dan keadilan-Nya? Atau Dia tidak mau sekaligus juga tidak bisa meniadakan wabah ini? Maka, apakah hakikat Allah sebagai Allah masih disebut Allah?
Sejumlah gugatan itu menuntun kita ke arah rasionalisasi: adalah masuk akal untuk mengatakan, Allah telah kehilangan hakikatnya sebagai Allah. Nyatanya Dia tidak melakukan intervensi sama sekali, menolong. Allah sungguh tidak bermoral, Allah tidak ada!
Dalam lintasan sejarah, sejumlah gugatan terhadap eksistensi kemahakuasaan Allah di hadapan fakta penderitaan manusia itu, telah lebih dahulu diajukan oleh Epikuros (341 SM-270 SM), seorang filosof Yunani, pada periode awal filsafat di Yunani Kuno. Ia mengajukan pertanyaan (teodisea, berasal dari dua kata, theos: Allah dan dike: keadilan, teodisea artinya, perkara pembenaran keadilan Allah) serius tentang asal-muasal kejahatan dan penderitaan yang selalu meneror manusia di muka bumi ini.
Fakta itu lalu dibenturkan dengan eksistensi kemahakuasaan Allah dan sampailah ia pada sejumlah pertanyaan dakwaan di atas. Kini, di hadapan fakta penderitaan, kematian, dan wabah Covid-19, pertanyaan-pertanyaan itu kembali dimunculkan di dalam upaya menalar Tuhan.
Manusia Tersandera Covid-19
Dunia macam apakah yang sedang kita masuki? Siapakah kita di dalamnya? Relasi antar manusia macam apakah yang sedang kita bangun lewat fenomena Covid-19 hari ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menggelisahkan dan patut disodorkan di awal ini untuk mengusik kesadaran dan nalar kita tentang “dunia baru” yang sedang kita hadapi. Fenomena Covid-19 tidak hanya mengubah kesosialan kita sebagai manusia, tetapi secara ontologi mengubah cara kita memandang tubuh kita sendiri.
Manusia sebagai makhluk sosial, kini berhadapan dengan fakta: bahwa kerekatan dan keakraban kita sebagai makluk sosial mesti diubah, yakni menarik diri ke ruang privat demi langgengnya hakikat kita sebagai makhluk sosial. Covid-19 menyadarkan kita untuk merumuskan ulang hakikat kesosialan kita dengan tidak membangun lingkungan sosial secara corporeal melainkan pertama kita dipaksa untuk masuk ke dalam logika teknologi untuk membangun relasi virtual dan kedua kita diminta dengan segala hormat untuk mengurung diri ke ruang privat demi keselamatan ruang publik-sosial. Inilah dunia yang sedang kita hadapi, yakni “hakikat kesosialan kita diukur berdasarkan seberapa cermat kita merawat tubuh kita”.
Tapi, pertanyaanya adalah apakah keadaan ini membuat kita makin manusiawi dan kurang sangar terhadap sesama manusia? Thomas Hobbes (1588-1679), seorang filosof politik berkebangsaan Inggris, pada subuh modernitas menerbitkan Leviathan (1651) buku yang coba memberikan solusi bagaimana mengatasi kekacauan sosial.
Hobbes mempostulatkan suatu kondisi yang tak tertanggungkan, yakni kondisi kekacauan (chaos): dunia tanpa hukum dan aturan, orang saling membunuh, merampok dan menjarah, tidak ada keadilan, hidup manusia menjadi sunyi, miskin, buas dan orang tidak bisa bikin puisi, pergi kondangan, tidak bisa berpacaran, atau pun bersantai ria di senja hari. Kondisi ini dikenal dengan istilah state of nature. Dalam kondisi alami, kebebasan setiap orang merupakan ancaman kebebasan setiap orang lainnya, sehingga praktis meniadakan kebebasan itu.
Hobbes lalu menawarkan solusi untuk mengakhiri keadaan kekacauan itu dengan merumuskan teori kontrak sosial: setiap orang menyerahkan hak saling membunuh dan menghakimi kepada pihak yang diberi kekuasaan mutlak untuk menjamin dan melindungi. Pihak penjamin kontrak itu adalah Negara (the state)—Leviathan. Negara memainkan peran sentral di dalam upaya memaksa warga untuk mengendalikan diri dan memberi respek satu sama lain. Artinya, negara memberadabkan orang.
Kini, negara hukum tetap berdiri tegak dan kelihatannya kokoh tetapi fenomena hari ini menyingkapkan fakta lain bahwa sesungguhnya tak satu pun negara yang siap menghadapi serangan mematikan makhluk renik ini. Negara kehilangan taringnya sebagai leviathan, bagaimana seharusnya memberadabkan orang di tengah gempuran Covid-19. Hidup manusia menjadi sunyi dan dingin.
Kota-kota terasa sepi dan lengang dan ketakutan akan kematian seperti hantu yang senantiasa meneror manusia. Tak ada bau mesiu dan tak ada pertumpahan darah. Yang terjadi adalah suatu pandemi global yang memaksa manusia mengurung diri, merefleksikan hakikat dirinya sebagai manusia. Serangan pandemi global ini memicu kekacauan baru, yakni Covid-19 state of nature.
Pokok tersebut punya implikasi luas, yakni guna menyelamatkan dirinya, harapan tidak lagi diletakkan secara mutlak kepada Negara, tetapi manusia dipaksa untuk menjadi leviathan bagi dirinya sendiri: disiplin diri yang ketat. Hal ini penting karena bisa Anda bayangkan, Covid-19 membuat tangan kanan/kiri Anda menjadi predator bagi diri Anda sendiri.
Anda tidak lagi bebas menggunakan tubuh Anda. Malahan—kini—Anda gelisah dan cemas ketika memakai tangan Anda untuk menyentuh bagian lain tubuh Anda. Covid-19 membuat manusia terperangkap dan terteror dalam tubuhnya sendiri. Horor ini menyadarkan manusia bahwa kini “Aku sedang tersandera di dalam dirinya sendiri”. Aku, The I, makin sadar akan ontologi ke-diri-anya bahwa tubuhnya bukan dirinya, dan “ke-bertubuh-anku” adalah neraka bagi Aku, The I.
Kini, di hadapan situasi hari ini manusia bertanya, Allah adakah? Dia adilkah? Atau Dia masih Mahakuasakah? Kalau Dia ada dan Mahakuasa, apa artinya penderitaan ini? Nyatanya manusia makin diburuh dan kematian terjadi setiap saat. Situasi ini barangkali membuktikan bahwa Dia tidak ada atau setidaknya Allah pernah menjadi tidak mahakuasa, tidak adil dll. Pertanyaan-pertanyaan itu membuka peluang kepada diskursus tentang ateisme.
Apakah Ateisme Itu?
Istilah “ateisme” berasal dari dua kata Yunani: awalan “a” (ά) yang berarti “tidak, tanpa, tidak ada” dan kata “theos” (ϑεος) artinya “Allah atau dewa”. Dalam arti ketat, secara harafiah ateisme bisa lugas dikenal sebagai paham yang menyangkal eksistensi adanya Allah dan atau menganggap bahwa Allah tidak berperan dalam kehidupan manusia. Dari pokok ini, secara umum dibedakan lagi dua macam ateisme: ateisme praktis dan ateisme teoritis.
Seorang ateis praktis, percaya kepada Allah dan tidak mempersoalkan eksistensi Allah tetapi dalam praktik hidupnya ia melakukan segala sesuatu seolah-olah tidak ada Allah. Konsep keallahan mendapat tempat terhormat dalam teori dan ajarannya, namun hidup orang ini praktis dijalaninya tanpa mempedulikan Allah dan perintah-perintah-Nya. Sedangkan ateisme teoritis adalah gagasan yang menyangkal secara terang-terangan adanya Allah dan berusaha mempertanggungjawabkan keyakinannya dengan mengajukan argumentasi-argumentasi. Gagasan ateistis semacam ini akan berkutat dengan filsafat terutama metafisika, “Ada tertinggi,” yang dalam bahasa agama disebut Tuhan.