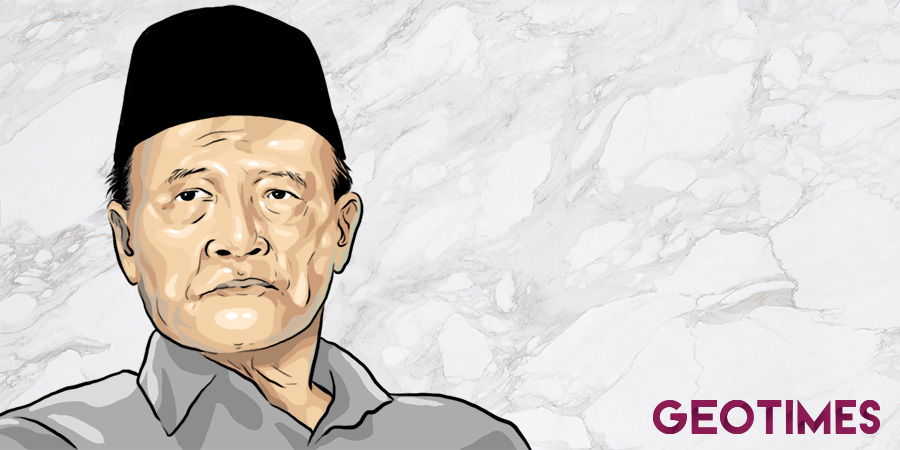“Permainan kau permainkan..” (Amir Hamzah)
Seperti yang kita duga, MK akhirnya menolak seluruh permohonan tim hukum BPN Prabowo-Sandi yang menuding Pemilu 2019 dipenuhi kecurangan hingga meminta MK mendiskualifikasi capres-cawapres pemenang Pemilu 2019 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Gedung MK sempat dikepung massa.
Syukurnya, aksi itu tidak berlanjut rusuh sebagaimana terjadi pada 21-22 Mei lalu. Penerimaan pada hasil putusan MK oleh kubu 02 (kendati tidak disertai dengan ucapan selamat pada Jokowi–Ma’ruf Amin) cukup menenangkan hati masyarakat, karena ada harapan ketegangan akibat Pilpres 2019 bisa mereda. Sisanya adalah masalah etika politik yang menjadi tanggungjawab setiap politisi. Tanggungjawab masyarakat untuk menunaikan Pemilu sebagai salah satu unsur terpenting demokrasi telah selesai.
Kemudian seperti yang kita duga juga, wacana rekonsiliasi di laman-laman media massa, mulai mengerucut menjadi wacana “transaksi” atau isu bagi-bagi jatah kursi di kabinet 2019-2024. Termasuk isu jatah kursi mentri untuk kubu 02.
Karena masih isu, tentu tak tak dapat dibuktikan kebenarannya, mengingat Presiden Jokowi juga belum mengumumkan susunan menteri-menteri baru yang akan membantu kinerjanya dalam satu periode ke depan.
Tetapi, pernyataan Presiden Jokowi di media massa yang akan membuka pintu kerjasama bagi pihak mana pun (termasuk Prabowo-Sandi), telah mengundang spekulasi bakal ada transaksi bagi-bagi kursi di kabinet tersebut. Bahkan, tokoh nasional Buya Syafii Maarif sempat merespon dan mengingatkan agar Jokowi tak harus menampung kubu 02.
Sebagai tokoh bangsa, ulama, dan cendekia, pandangan Buya Syafi’i Maarif patut kita renungkan bersama. Itu adalah wujud dari kejujuran intelektual untuk memberikan arah yang betul bagi perjalanan demokrasi dan kekuasaan di republik ini.
Di saat yang lain heboh dan terkamuflase dengan topik rekonsiliasi, Buya justru menggugah kita dengan sisi tak tampak dari wacana rekonsiliasi itu. Yakni kuatnya permainan elite oligarki di dalamnya, yang terwujud dalam bentuk kompromi yang berarti pula transaksi politik.
Kompromi dengan cara jatah-jatahan di kabinet, mungkin saja efektif untuk menghindarkan keriuhan politik. Tapi kompromi bukanlah kata yang arif untuk membangun demokrasi berlandas hukum, apalagi bagi kemurnian dunia intelektual. Itu lebih cocok sebagai mekanisme damai ala sindikat kriminal ketimbang ketimbang bagi sebuah masyarakat dan negara hukum.
Namun faktanya memang, kompromi telah menjadi karakter dalam dunia politik kita. Pada situasi ini, sistem demokrasi diperalat menjadi permainan elit politik dengan mengorbankan rasa keadilan masyarakat yang sebenarnya lebih menginginkan penegakan hukum ketimbang kompromi politik.
Seluruh nilai (tatanan, hukum, ideologi, kearifan, pengetahuan) yang dijunjung masyarakat kehilangan dimensi kebenarannya dan menguap menjadi sekedar representasi yang diproduksi sebagai bagian dari permainan kepentingan elit.
Pada kondisi semacam itu, tidaklah patut kalangan intelektual bersikap netral. Karena yang diperlukan masyarakat adalah keberanian untuk mengungkap kebenaran dengan cara menyentuh kesadaran masyarakat. Sesuai dengan tanggungjawab mendasar intelektual untuk membangunkan masyarakat dari kealpaan.
Dalam konteks realitas yang terpermainkan, berarti membangunkan masyarakat dari jebakan permainan yang meliputi kehidupan orang banyak. Hal itu dikarenakan daya intelektual adalah anugerah Allah Swt yang dicapai seseorang untuk dijadikan sarana mengungkap kebenaran, menyatakan apa yang hoaks, yang permainan, dan kemudian membimbing masyarakat keluar dari simulasi itu dengan hikmat intelektualitas.
Kita tentu tidak menginginkan demokrasi yang diperjuangkan susah payah ini terperangkap dalam permainan. Untuk itu, kalangan intelektual jangan sampai terseret menjadi bagian dari proses permainan itu.
Keberpihakan dan keterlibatannya yang terutama haruslah berpijak pada kesadaran yang kuat dan murni, demi menguji kembali seluruh jargon sosial budaya, simbol-simbol, serta mitos yang terlanjur menjadi realitas. Dialog yang intens, kritik wacana, serta kritik kebijakan merupakan di antara langkah penting mewujudkan kerja semacam itu.
Topeng rekonsiliasi
Di antara ciri dari kerja permainan politik yang menonjol adalah take over simbol dan isu. Yakni bergesernya makna dan wacana dari porsi dan definisi yang sah menjadi definisi baru sesuai kepentingan politik tertentu. Contohnya isu “kecurangan” yang maknanya diciptakan sepihak dan diproduksi untuk menjadi senjata memukul lawan politik.
Walaupun kecurangan seharusnya ditetapkan berdasarkan prosedur hukum, namun dalam realitas permainan hal itu tidak diperlukan, karena kecurangan dapat menjadi realitas hanya dengan memproduksi kata kecurangan itu secara intens, massif dan terstruktur.
Nasib wacana rekonsliasi dalam pola permainan ini pun tak jauh berbeda. Rekonsiliasi berubah menjadi wacana ambigu dan cenderung menjadi topeng untuk mengkamuflase kenyataan yang sesungguhnya berlaku di baliknya.
Sebab, jika dilihat dengan hati telanjang, konteks Pilpres 2019 tidak memenuhi syarat yang diperlukan untuk dilakukan suatu rekonsiliasi. Kenyataannya, pemungutan suara berjalan lancar, dan pemilu secara keseluruhan berjalan baik menandakan masyarakat dan pemerintah Indonesia konsisten menjalankan demokrasi.
Dengan kata lain, pemilu ini tidak menjadikan suatu kelompok sebagai korban, melainkan sebagai rakyat yang bertanggungjawab. Apabila isu itu dipaksakan, pemerintah mungkin akan dirugikan karena akan menjadi alat legitimasi bagi kekuatan politik yang menuding pemilu telah dicurangi kekuasaan.
Selain tidak memiliki konteks historis dan aktualnya, pemunculan ide rekonsiliasi pada proses Pemilu 2019 ini dapat melukai elemen-elemen masyarakat yang selama ini mencoba mendapat keadilan melalui proses rekonsiliasi. Seperti elemen korban ‘65’ yang berusaha memulihkan trauma dan citra kewarganegaraan mereka akibat kekejaman politik di masa Orde Baru, rekonsiliasi korban kekerasan DOM di Aceh, rekonsiliasi pasca konflik di sejumlah daerah konflik yang semuanya belum direspon dengan tuntas oleh pemerintah dan lembaga berwenang.
Lalu, kosa kata itu sekarang di take over dengan semena-mena demi mengesankan ada kekacauan yang memerlukan rekonsiliasi? Dikhawatirkan efeknya bukan rekonsiliasi sesuai maknanya, melainkan provokasi dan transaksi. Kekhawatiran semacam ini mungkin saja sudah terjadi melihat gelagat para politisi di hari-hari terakhir.
Respon yang wajar terhadap situasi ini adalah memulihkan tujuan rekonsiliasi itu, yakni untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak. Hal itu, tentu berbeda maknanya dengan bagi-bagi kursi di kabinet. Untuk itu, dunia intelektual tak punya pilihan lain, kecuali pro aktif mengingatkan kekuasaan dan masyarakat akan makna sebenarnya dari rekonsiliasi agar rekonsiliasi tidak menjadi topeng belaka.
Jakarta Juli 2019