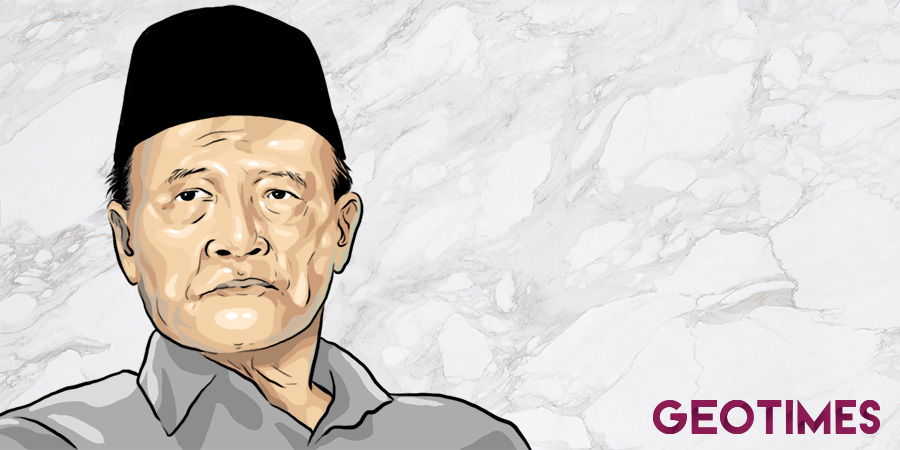Assalamu’alaikum.
Selamat pagi, Buya.
Semoga Buya tetap dikaruniai kesehatan, kebijaksanaan, keberanian, keberdikarian, dan pendirian yang teguh. Sebagaimana adanya.
Buya, saya ingin bercerita. Lebih tepatnya, meluapkan kesah dan kasih.
Beberapa malam terakhir saya terusik oleh kenyataan bahwa semakin hari, Buya semakin bertambah usia. Memikirkan itu, tidur saya tak nyenyak. Sekali dua saya terbangun dari tidur dan langsung terbayang wajah Buya. Saya tahu ini terdengar aneh: seolah saya hendak bilang kalau “sebentar lagi Buya akan tutup usia.” Tapi sungguh, bukan itu kegelisahan saya.
Saya menulis ini di tengah dera tipes. Saya tidak boleh banyak bergerak sebab perut saya akan terasa nyeri. Tapi kegelisahan tak tertahankan. Dengan sedikit menyimpan malu pada Buya, yang hingga kini masih gigih bertarung berebut keadilan, yang masih tekun ‘bersuara’ di koran-koran, saya putuskan untuk melawan nyeri. Saya ambil laptop dan menulis.
Buya,
Sebagai seorang anak muda yang menyaksikan Buya dari jauh, saya bertanya-tanya, harus sekeras apakah batu pendirian saya agar bisa seistikamah Buya. Apa yang sebetulnya Buya percaya? Apa yang Buya cari? Tidakkah Buya lelah?
Mungkin jawabannya kelihatan simpel: Buya percaya Allah sangat menjunjung keadilan dan menentang eksploitasi. Buya percaya Islam menjunjung penghormatan dan kasih sayang. Atas dasar itu Buya menentang agenda-agenda politik yang mengeksploitasi sentimen keagamaan umat; atas dasar itu juga Buya istikamah membela kaum minoritas.
Tapi, Buya, saya mengenal banyak orang yang memiliki kepercayaan yang sama seperti Buya. Hanya Buya yang saya ketahui segigih itu. Buya seperti tidak pandang bulu. Buya tidak urus apakah setelah kritik dan pembelaan Buya akan dibenci dan dikucilkan. Tidak banyak manusia yang berani menghadapi kesepian. Tapi Buya seberani itu. Apa sebetulnya resep Buya? Apa yang menjadi sumber tak hingga dari segala kegigihan dan ketahanan itu?
Saya membaca beberapa karya Buya. Bahkan otobiografi Buya saya baca. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan saya bisa dijawab oleh karya-karya itu. Tapi saya belum puas. Teks berbicara seperti sedang menahan-nahan diri, sedangkan saya ingin tahu lebih dalam. Diary Soe Hok Gie membuat kita tahu titik-titik dalam sejarah hidupnya di mana dendam pada kekuasaan mulai membatu. Punyakah Buya pengalaman semacam itu?
Mungkin saya gelisah, Buya. Saya gelisah karena berkaca pada diri saya sendiri. Saya muda dan malas membaca buku; saya muda dan jarang menulis; saya muda dan, seiring memasuki dunia kerja, menjadi tipikal yes man yang terbiasa dengan kepalsuan; saya muda dan mulai suka dengan ide “dilayani” alih-alih melayani; saya muda dan pengecut angkat suara membela golongan tertindas; saya muda dan membawa sederet kebodohan yang khas.
Sedangkan Buya bukan saja seperti jauh dari hal-hal semacam itu, tapi anti. Buya sengit mempertunjukkan cara hidup yang sebaliknya. Saya terkenang Buya yang bersepeda, Buya yang menolak dibawakan tasnya, yang mengkritik dengan menunjuk hidung, yang memberi dukungan moril bagi jemaat gereja yang gerejanya dirusak sekelompok babon bodoh, yang mudah ditemui oleh siapa pun yang ingin berdiskusi, yang tidak putus menulis, dan lain-lain.
Saya tidak suka versi diri saya ini, setelah berkaca pada Buya. Bukan sekali dua saya berusaha, Buya, agar menjadi sosok merdeka nan tekun seperti Buya. Bukan sekali dua saya berlatih agar menjadi lebih berani dan tegar. Kadang saya melihat diri saya berhasil, tetapi lebih sering saya temukan semangat yang luntur. Ternyata, motivasi saya tidak kuat. Usaha saya tidak lahir dari keyakinan yang membatu. Saya kembali malas dan emohan.
Kadang saya menyalahkan “zaman”, yakni bahwa di masa serba praktis dan sudah serba enak ini, “zaman” seperti sudah tidak sanggup lagi melahirkan sosok-sosok besar seperti Buya, seperti alm. Pak Malik Fadjar, alm. KH. Abdurrahman Wahid, alm. Kang Moeslim Abdurrahman, alm. Pak Kuntowijoyo, alm. Soedjatmoko, dll. Saya merasa nyaman bila menemukan pihak yang bisa saya salahkan. Tapi itu sikap pengecut, saya sangat tahu.
Dan Allah menghadirkan kegelisahan lewat bayang-bayang wajah Buya di malam-malam saya. Saya begitu rindu dan ingin meluapkan pertanyaan-pertanyaan di atas. Saya begitu ingin memahami hulu ledak Buya. Meski sekiranya hulu ledak itu tidak bisa saya tiru, tapi paling tidak saya tahu. Saya bisa mengusahakan hulu ledak saya sendiri. Kawula muda lain pun, yang juga gelisah seperti saya, bisa menjemput jatah rizki hulu ledaknya masing-masing.
Dan bila nanti Buya tidak lagi bersama kami di sini (ya Allah, saya berharap hal itu masih sangat lama akan terjadi), setidaknya ada semacam cetak biru yang bisa dijadikan panduan untuk menjadi Buya-Buya baru, dengan tulang punggung yang sama kerasnya, dengan pena yang sama tajamnya.
Semoga Buya tetap dikaruniai kesehatan, kebijaksanaan, keberanian, keberdikarian, dan pendirian yang teguh. Sebagaimana adanya.
Wassalamu’alaikum.