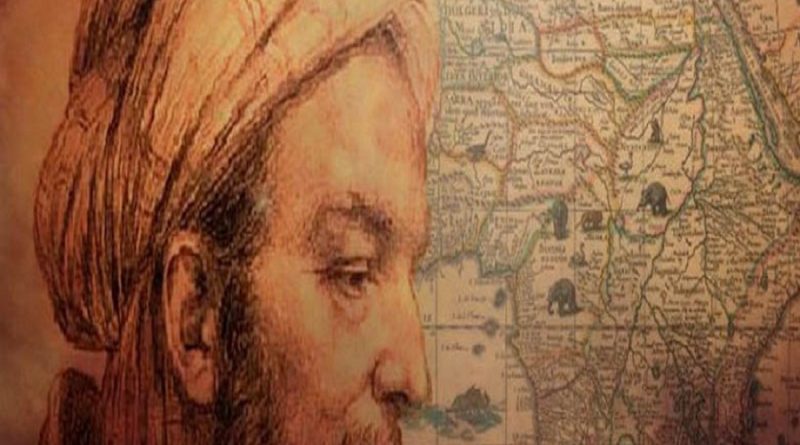Tertangkapnya Saracen, sindikat penyedia berita-berita hoax (palsu, bohong, tak benar) berbayar, baru-baru ini semakin menyadarkan kita bahwa teknologi informasi rentan digunakan untuk memproduksi berita menyesatkan. Meskipun, pada saat yang sama, tertangkapnya Saracen memberi angin segar dan optimisme bagi pemberantasan hoax di Indonesia, setelah sebelumnya pegiat anti-hoax menciptakan aplikasi dan situs pengecek berita-berita hoax.
Kini, hoax sedang menjadi ancaman serius yang tengah melanda masyarakat dunia. Dari hoax yang bersifat global, yakni menyasar banyak orang di berbagai negara, seperti halnya kasus perang Suriah—yang dipropagandakan sedemikian rupa oleh elite-elite tertentu untuk meneguhkan bahwa pemerintahan Suriah bersikap zalim terhadap rakyatnya—hingga hoax yang bersifat lokal, hanya menyasar satu negara saja, misalnya kasus gerakan rush money 2016 lalu—yang disebar oleh oknum tertentu untuk mengajak masyarakat Indonesia menarik semua uangnya di bank negara dan bank swasta.
Tetapi, yang paling mengkhawatirkan adalah penyajian hoax—baik dalam bentuk meme, tulisan, maupun video—di media sosial dan berita online yang tak hanya memuat informasi palsu yang datar, tetapi lebih jauh lagi sudah dibumbui dengan pernyataan-pernyataan provokatif yang tak jarang berpotensi menggiring pembacanya bertindak anarkis.
Tujuannya tentu untuk mempengaruhi opini pembaca, dan kalau bisa mengajak mereka agar beraksi. Dalam hal ini pembaca dianggap sebagai kertas kosong, yang pena informasinya dikuasai oleh sang penyebar hoax. Pembaca diposisikan sebagai objek pasif, pikirannya coba ‘diracun’. Motif pelaku hoax sendiri beragam; ada yang demi uang, demi dakwah agama, maupun demi uang tapi dibungkus seolah-olah demi dakwah agama.
Hoax sejatinya bukan “barang baru”. Sedari dulu kasus semacam ini sudah ada. Ingat, di masa-masa awal Islam, sejarah mencatat bahwa ketika Perang Uhud sedang berkecamuk, tersebar hoax bahwa Nabi wafat. Seketika semangat juang pasukan Muslim turun drastis dan hampir memutuskan untuk mundur. Kendati kenyataannya Nabi masih hidup, bahkan dengan gagah mengomandoi pasukannya untuk kembali merebut kemenangan.
Pada masa itu pula sudah ada hadis-hadis palsu, hadis yang ditulis seakan-akan berasal dari Nabi, padahal bukan; sehingga Nabi buru-buru mengingatkan dalam sabdanya, “Sesiapa yang berdusta atas namaku, maka tempatnya adalah di neraka.”
Begitu pula kitab-kitab yang memuat informasi palsu guna mendukung dan mengukuhkan suatu rezim tertentu yang ditulis oleh penulis-penulis bayaran, sehingga suatu ungkapan menyebutkan, “Sejarah ditulis oleh siapa yang berkuasa.” Pada akhirnya, bagaimanapun, sejarah dan reportase ditulis, peradaban tentu akan terpengaruh.
Lantaran terkait dengan kondisi-kondisi yang mempengaruhi tabiat dari peradaban, tak heran jika kisah-kisah dan berita-berita palsu pernah menjadi perhatian Ibnu Khaldun, filsuf abad ke-14, dalam kajian sosio-historisnya. Baginya, sejarah-sejarah yang telah ditulis tak aman dari berita-berita palsu atau pun berita-berita keliru, baik berita yang diproduksi oleh penguasa ataupun sang sejarawan, si penulis sejarah, itu sendiri.
Dalam magnum opus-nya, al-‘Ibar, sering kali Ibnu Khaldun mengkritik penulisan-penulisan sejarah oleh tokoh-tokoh yang mendahuluinya. Hanya segelintir orang saja yang memiliki kecakapan yang diakui dan dapat menulis sejarah secara komprehensif, di antaranya adalah Ibnu Ishaq, al-Thabari, Ibnu al-Kalbi, Muhammad ibnu Umar al-Waqidi, Saif ibnu Umar al-Asadi, dan lainnya yang sudah terkenal dan memiliki keistimewaan sendiri.
Kendati demikian, menurutnya, karya-karya mereka masih terdapat ‘kecacatan’. Terlebih karya-karya dari sejarawan yang datang setelah mereka. Dalam salah satu kritikan di kitabnya, Muqaddimah (t.th), Ibnu Khaldun mendaftar kecacatan-kecacatan yang dimaksudnya, di antaranya: menempuh cara-cara taklid, miskin karakter dan akal, berpikiran jumud.
Sejarawan ini menurut Ibnu Khaldun “…hanya mengikuti pola-pola penulisan sejarah yang sudah ada dan lalai terhadap perubahan-perubahan masa dan tradisi-tradisinya dari generasi ke generasi, dari bangsa ke bangsa lain… Mereka hanya memuat informasi yang tak berguna karena tak jelas ujung pangkalnya. Yang mereka catat hanyalah peristiwa-peristiwa yang tidak jelas usulnya, atau pun bagian-bagian yang tak dapat ditarik kesimpulan umumnya, serta tak dapat diklasifikasikan secara sistematis.” (t.th: 11)
Setidaknya, secara garis besar terdapat empat penulisan sejarah dan penulisan narasi atau reportase yang Ibnu Khaldun kritisi, sebagaimana diteliti oleh Syed Farid al-Attas dalam karyanya, Ibn Khaldun (2013). Pertama, gosip dan laporan-laporan ciptaan yang dicampurkan dengan laporan-laporan yang benar.
Kedua, pelaporan terhadap peristiwa-peristiwa historis yang sering ditemukan error dan dugaan liar. Ketiga, [narasi ditulis oleh] orang-orang yang tidak memiliki kompetensi tetapi masuk ke dalam disiplin-disiplin akademis.
Keempat, taklid buta terhadap sejarah-sejarah yang telah lalu dari satu generasi ke generasi lainnya dan diterima tanpa pertanyaan (2013: 26).
Kritikan-kritikan terhadap model penulisan sejarah banyak didapati di Muqaddimah. Kritikan-kritikannya dalam beberapa hal sangat mendetail, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami kelemahan-kelemahan dari sejarah yang dia kritisi. Pertanyaannya, mengapa penulisan sejarah semacam ini dapat terjadi?
Menurut Ibnu Khaldun, setidaknya terdapat tujuh sumber prinsip error dalam sejarah. Pertama, sikap berat sebelah terhadap pendapat dan mazhab (aliran). Kedua, menggantungkan kepercayaan pada pembawa berita. Ketiga, kurangnya kesadaran terhadap tujuan dari suatu peristiwa.
Keempat, asumsi-asumsi tak berdasar yang dianggap sebagai kebenaran dari suatu peristiwa. Kelima, ketidaktahuan terhadap kesesuaian antara kondisi-kondisi dan peristiwa-peristiwa aktual. Keenam, “penjilat”. Ketujuh, ketidaktahuan terhadap sifat dari kondisi-kondisi masyarakat. (2013: 42-43)
Pada dasarnya, sejarah tidak hanya berkaitan dengan masa yang jauh dengan masa kita, bahkan kemarin dan apa yang baru kita lalui pun sejatinya adalah sejarah. Oleh sebab itu, kritik Ibnu Khaldun mengenai penulisan sejarah dapat berlaku pada penulisan reportase yang baru-baru saja terjadi.
Pertama, karena sama-sama berbicara mengenai apa yang sudah lalu. Kedua, karena sama-sama berkutat pada penulisan dan reportase atas apa yang telah terjadi. Dengan kata lain, tujuh sumber prinsip error dalam sejarah pada dasarnya adalah tujuh sumber prinsip error dalam reportase atas peristiwa yang telah terjadi.
Tujuh sumber prinsip error ini pada gilirannya mengambil bentuk menjadi berita yang tak akurat, tak berimbang, palsu (hoax), gosip, bahkan fitnah. Sayangnya, berita-berita semacam ini justru ‘menemukan habitatnya’ di lingkungan sekitar kita.
Boleh jadi, beberapa orang terjebak dalam dua, tiga, atau empat sumber prinsip error, tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa orang terjebak dalam tujuh sumber prinsip error di atas. Imbasnya, mereka rentan diadu-domba, mudah konflik hanya karena perbedaan pendapat semata.
Patut diperhatikan bahwa untuk mendapat pengetahuan dan gambaran yang komplet mengenai suatu peristiwa, sejarawan dan pembaca fenomena sosial-politik membutuhkan banyak rujukan, sejumlah kecakapan, dan penalaran sekaligus ketelitian. Di antaranya mereka mesti mengetahui ilmu politik, karakter-karakter alam, perbedaaan bangsa-bangsa, kawasan dan zaman dalam hal perjalanan hidup, akhlak, tradisi mazhab, dan hal-hal lain. Fungsinya tidak lain adalah mendapatkan kebenaran dan menyelamatkan dari kesalahan dan penyimpangan.
Bahkan, tak cukup sampai di situ, mereka mesti kreatif. Sebagaimana terbersit dalam Muqaddimah, “ia harus menguasai masa sekarang untuk membandingkan masa lalu, mencari sisi-sisi persamaan dan sisi-sisi perbedaan antara keduanya, menggali latar belakang persamaan dan latar belakang perbedaan tersebut.” (t.th: 47)
Apabila kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip semacam ini sudah dimiliki, maka dengan mudah seseorang dapat menilai data-data informasi yang ia peroleh. Jika berita tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut dan berjalan sesuai dengan hukum-hukumnya, maka berita tersebut adalah benar. Jika tidak demikian, maka ia mendustakannya dan meninggalkannya.
Ibnu Khaldun percaya bahwa suatu peristiwa memiliki karakter tersendiri, dan yang perlu dilakukan oleh pengamat adalah menemukan karakter ini dengan tentunya menyelidiki sebab dan asalnya, serta menyelidiki secara mendalam tentang bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi, hingga kemudian dapat disimpulkan suatu aturan umum yang dapat berlaku pada semua peristiwa yang serupa di masa lalu maupun sekarang.
Sebab dan asal serta mengapa dan bagaimana suatu peristiwa sifatnya tak tampak atau batin. Bagi Ibnu Khaldun, dengan mengetahui batiniah (sebab dan asal, bagaimana dan mengapa) suatu peristiwa, kita akan terhindar dari kesalahan. Dalam konteks ini, dia berpendapat bahwa suatu fenomena memiliki esensi (dzāt) dan aksiden (‘aradh).
Untuk mengetahui sesuatu, katanya, adalah untuk mengetahui esensinya dan dapat membedakan antara esensi dan properti-properti aksidentalnya. Jika diterapkan pada peristiwa yang telah lalu, hal ini bermakna bahwa pengamat mesti mengetahui sifat (tabiat) dari peristiwa-peristiwa, kondisi-kondisinya, serta syarat-syaratnya agar dapat dibedakan kebenaran dari kesalahan.
Ringkasnya, terdapat perbedaan mendasar antara reporter dengan perspektif kritis. Yang pertama hanya merekam dan menyebarkan apa yang telah ia kumpulkan, sementara yang kedua mensyaratkan untuk menguak makna batin dari peristiwa-peristiwa.
Begitulah perspektif kritis atau perspektif filsuf (yang direpresentasi oleh Ibnu Khaldun) dalam memperoleh dan menilai suatu berita atau informasi, memang agak berliku tapi potensi menghasilkan kesimpulan yang aman sangatlah tinggi. Sebab, tahapan penilaiannya terbilang ketat dan premis-premis yang digunakan sebisa mungkin valid dan aksiomatis. Artinya, metodenya tidak gampangan, sehingga rentan menghasilkan kesimpulan yang keliru dan sesat.
Pada akhirnya, dengan cara dan paradigma semacam ini, kita tak akan mudah percaya pada suatu berita, tak mudah dihasut atau diadu-domba, dan cenderung akan lebih berhati-hati dan tidak keburu-buru dalam menilai dan membuat kesimpulan.
Atau setidaknya, selama kita belum memiliki perangkat epistemologis yang dibutuhkan, sebaiknya kita menahan diri untuk menilai dan berkomentar dan rujuklah yang ahli di bidangnya. Seperti saran Sayyidina Ali bin Abi Thalib, “Andai yang tak berilmu diam sejenak, niscaya gugur perselisihan yang banyak.”