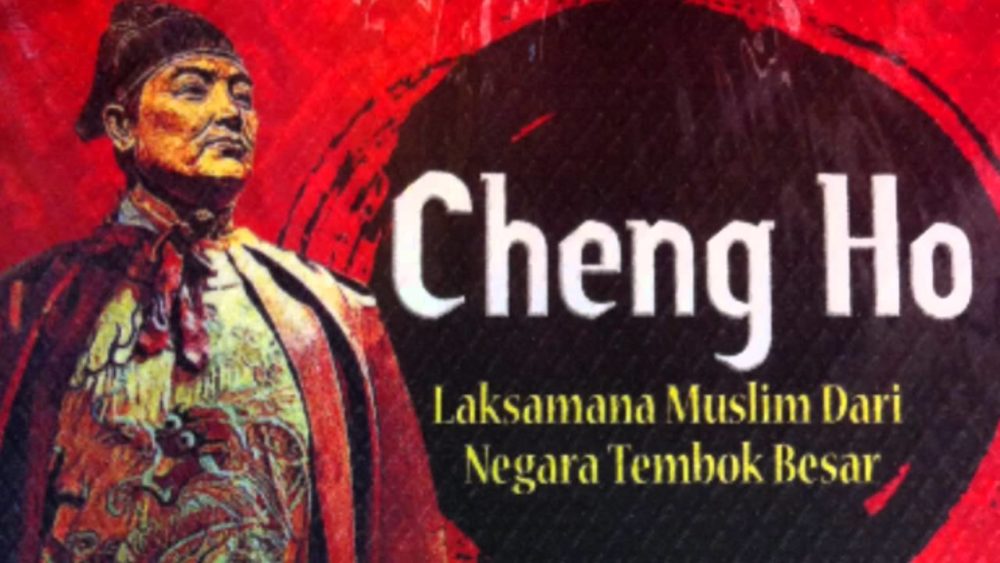Selama ini beredar luas provokasi yang menyandingkan istilah Cina dan kafir. Bahkan istilah Cina dan kafir seringkali terbaca dari status-status media sosial yang penuh kebencian dan broadcast di pesan-pesan pribadi yang bernada rasial. Sebagai istilah yang mengandung pesan politik, istilah Cina-kafir tentu saja memiliki kelemahan-kelemahan argumentasi dan basis logika, yang dibarengi dengan kedangkalan berpikir dan lemahnya keinginan mencari fondasi pengetahuan untuk memahami isu ini.
Selama ini beredar luas provokasi yang menyandingkan istilah Cina dan kafir. Bahkan istilah Cina dan kafir seringkali terbaca dari status-status media sosial yang penuh kebencian dan broadcast di pesan-pesan pribadi yang bernada rasial. Sebagai istilah yang mengandung pesan politik, istilah Cina-kafir tentu saja memiliki kelemahan-kelemahan argumentasi dan basis logika, yang dibarengi dengan kedangkalan berpikir dan lemahnya keinginan mencari fondasi pengetahuan untuk memahami isu ini.
Sejak setahun terakhir istilah Cina-kafir menguat sebagai bahan perbincangan penuh kebencian dan kekerasan kata-kata yang bernada peyoratif. Istilah ini sering diulang dalam debat-debat terbuka, demonstrasi jalanan, hingga khutbah-khutbah di masjid. Ibarat virus, istilah Cina-kafir telah menggerogoti nalar berpikir orang-orang yang membenci seorang tokoh politik yang, karena perbedaan pendapat dan kepentingan, diserang dari pelbagai penjuru dengan basis isu rasial, agama hingga tuduhan-tuduhan korupsi yang belum terbukti secara hukum hingga kini.
Sebagai istilah yang ditujukan mempengaruhi massa, atau dalam target antara mendelegitimasi marwah seorang pemimpin politik, istilah Cina-kafir perlu dikoreksi agar tidak menjadi “kanker kata-kata”. Demikian pula istilah ini perlu digali asal muasalnya, serta dikembalikan pada konteks yang tepat, agar tidak menjadi peluru bahasa. Menjernihkan kembali istilah ini setidaknya akan menyehatkan perang kata-kata dan kontestasi makna dalam medan pertarungan politik kita.
Pertama, istilah kafir tidak relevan dalam negara demokrasi. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa Indonesia sepakat untuk mengusung negara demokrasi yang menggunakan amanat rakyat. Memang, terjadi perdebatan panjang dalam perumusan dasar negara dan konstitusi negeri ini dalam sidang-sidang Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan (BPUPK) maupun pada forum-forum permusyawaratan lainnya.
Dengan jelas dan tegas argumentasi-argumentasi sempit keagamaan bisa dipatahkan dan terakomodasi dalam semangat spiritualitas-kebangsaan. Penggunaan simbol-simbol agama untuk pesan politik tidak lagi menjadi pilihan utama karena telah terangkum dalam nilai-nilai spiritualitas Pancasila.
Dalam negara demokrasi, tidak ada istilah kafir, karena semua menjadi warga negara yang berpegang pada aturan-aturan hukum dan konstitusi. Ulasan mendalam tentang argumentasi ini menjadi kajian Akhmad Sahal (Dalam NKRI Tak Ada Orang Kafir!) dan Mun’im Sirry (Umat Kristiani Itu Kaum Beriman, Bukan Kafir) di Geotimes.
Labelisasi kafir menjadi tidak relevan karena yang menjadi pedoman bukan undang-undang agama tertentu, melainkan landasan hukum dan ideologi negara yang menjembatani semua agama dan etnis. Inilah pemikiran visioner para pendiri bangsa, yang perdebatan panjangnya dan trik-trik politik untuk merumuskan Pancasila tidaklah sia-sia.
Kedua, istilah Cina-kafir menjadi gagal dalam logika bahasa. Karena Cina tidak mesti terasosiasi dengan “kafir”. Jika ditelusuri secara jernih, banyak orang Cina—atau Tionghoa untuk penyebutan yang lebih empatik—yang beragama Islam. Orang-orang Tionghoa Muslim ini memiliki peran besar dalam membangun jembatan komunikasi lintas etnis-agama dan menjaga pilar-pilar harmonisasi sosial. Mereka ada dan berjasa, namun seolah dianggap tidak ada, misalnya untuk memaksakan kehendak politik dalam delegitimasi peran atas kepemimpinan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama).
Bahkan seorang mantan presiden negeri ini, dalam sebuah unggahan video di Youtube, juga menyebut Ahok dengan istilah Cina-kafir. Sebagai mantan presiden, dengan segenap prestasi dan kehebatan kepemimpinannya, penyebutan bernada rasial dan delegitimatif ini sejatinya menunjukkan watak aslinya secara personal yang selama ini tertutupi citra sebagai korban politik, “playing as victim”. Senjata kata-kata dengan penyebutan Cina-kafir, perlu disaring agar tidak memperkeruh suasana.
Tentu jika kita melacak sejarah panjang orang-orang Tionghoa di Nusantara, istilah Cina-kafir akan kehilangan maknanya. Pada kisaran abad XV, Laksamana Cheng Ho (Zheng He) melakukan muhibah, perjalanan panjang menyusuri kawasan pesisir Nusantara. Cheng Ho melakukan tujuh kali lawatan ke berbagai kawasan, yang di antaranya singgah dan mewariskan jejak peradaban di Aceh, Palembang, Cirebon, Semarang, Lasem, Tuban, Ujung Galuh, dan beberapa kawasan lain (Tan Ta Sen, 2010).
Kiprah Cheng Ho tidak hanya menjadi selebrasi kebudayaan orang-orang Tionghoa dari dinasti Ming. Jejak Cheng Ho juga berdampak pada tumbuhnya komunitas-komunitas Tionghoa di beberapa kawasan pesisir di Sumatra dan Jawa. Cheng Ho, sebagai Tionghoa Muslim, menginspirasi silang budaya antara kebudayaan Tionghoa dan kebudayaan Nusantara.
Selanjutnya, beberapa wali juga dianggap sebagai keturunan Tionghoa. Riset Sumanto al-Qurtuby (“Arus Cina-Islam-Jawa; Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV & XVI”), memaparkan argumentasi ini. Di antara faktanya, Raden Patah (pemimpin kharismatik Kerajaan Demak), bernama Jin Bun. Meski riset-riset tentang transmisi Islam dari daratan Tionghoa menjadi perdebatan sejarawan, bukti-bukti yang dipaparkan beberapa peneliti menarik sebagai bahan renungan.
Dinamika beragama dan interaksi orang Tionghoa pada empat abad terakhir akan saya eksplorasi dalam esai yang lain. Atau, jika pembaca sempat jalan-jalan ke beberapa kawasan (Surabaya, Pandaan, Jawa Timur, Jember, Banyuwangi, Purbalingga dan kota-kota lain) telah banyak masjid berarsitektur Tionghoa yang di antaranya bernama masjid Cheng Ho dan masjid Lao Tzu.
Demikianlah identitas orang Tionghoa. Orang Cina tidaklah tunggal. Orang Tionghoa di Indonesia juga memiliki kontribusi dalam proses silang budaya. Mereka memiliki kontribusi yang sama dengan keturunan Arab, India, atau peradaban-peradaban besar dunia. Inilah wujud tamansari kebudayaan Nusantara, yang sebaiknya dinikmati sebagai keragaman, bukan fakta yang ingin diingkari dan diseragamkan.
Dengan menelusuri konteks sejarah dan kebudayaan negeri ini, menolak klaim Cina-kafir akan lebih menyehatkan daripada meracuni pikiran dengan istilah-istilah bernada kebencian.
Baca juga: