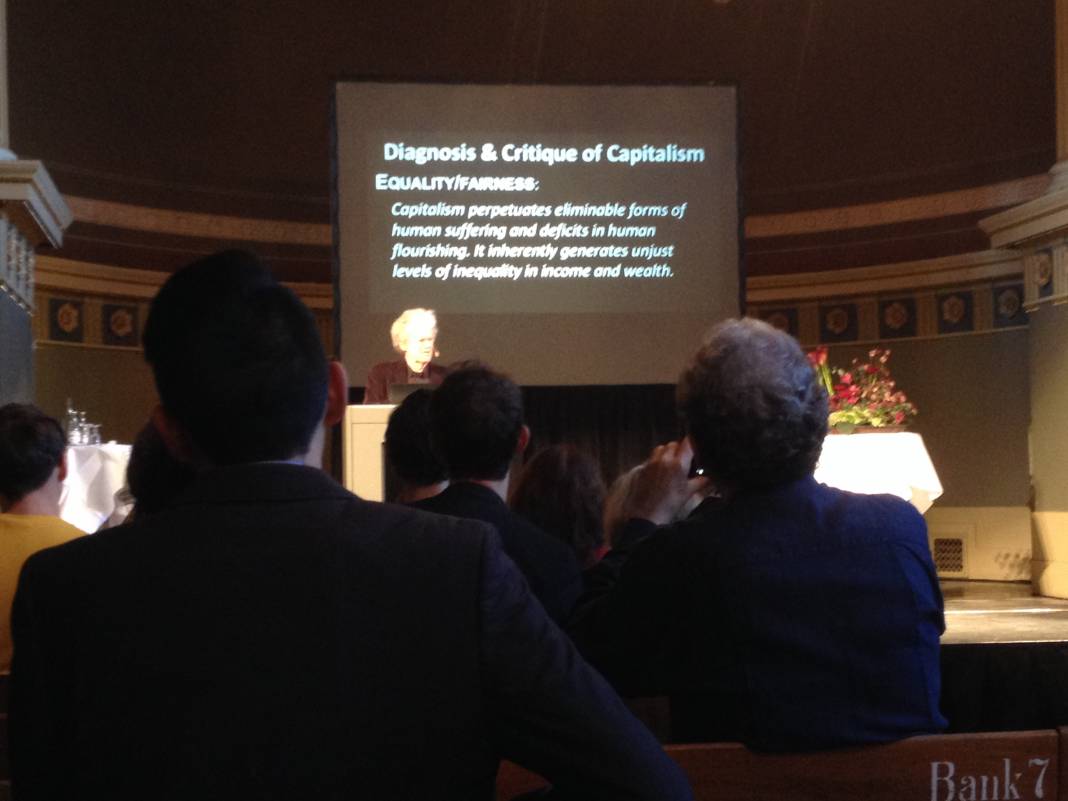Pada tanggal 25 Mei 2017, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi menerbitkan peringatan untuk berhati-hati memilih Konferensi Internasional dan/atau Jurnal Ilmiah. Pasalnya, banyak seminar internasional yang diikuti terindikasi predator. Pun begitu juga dengan jurnal ilmiah. Karena ada target publikasi di jurnal terindeks Scopus, banyak dosen yang kemudian ramai-ramai mengirimkan artikel karya mereka di jurnal-jurnal yang masuk dalam kategori Beall’s List sebagai predator.
Belum lagi dengan munculnya Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No 20 tahun 2017 yang mengatur soal keharusan publikasi ilmiah di jurnal terindeks untuk keperluan pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor, dan memicu banyaknya protes kepada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi terkait dengan kebijakan baru ini. Apa yang menjadi problem?
Sebagai seorang peneliti muda (saya baru saja mengikuti pendidikan riset lanjut di level Doktoral tahun ini), tentu saya bisa dibilang belum tahu apa-apa mengenai problematika kompleks ini. Terlebih, walaupun berkarir sebagai peneliti di perguruan tinggi dan 4 tahun membantu mengelola lembaga penelitian di UGM, saya tidak sempat berkecimpung lebih dalam di dalam negeri. Namun demikian, dari pandangan awam, saya ingin melihat hal ini sebagai dampak dari 4 hal penting dalam dunia pengetahuan di Indonesia.
Pertama, keterkejutan akademisi kita terhadap kebijakan Scopus bisa jadi adalah indikasi lemahnya tradisi pengetahuan di dunia akademik Indonesia. Yang saya maksud dengan “tradisi pengetahuan” ini adalah trisula ‘Baca-Tulis-Diskusi” yang seakan tenggelam di bawah Tridharma Perguruan Tinggi: “Pengajaran-Penelitian-Pengabdian Masyarakat”.
Dua hal itu bukanlah dua hal yang berbeda, tetapi saling terkait satu sama lain. Jika Tridharma perguruan tinggi adalah semacam ‘panduan profesional’ bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang mendefinisikan cakupan aktivitas para dosen dan peneliti di perguruan tinggi, maka “tradisi pengetahuan” bisa jadi adalah “panduan kultural” bagi para akademisi sebelum berkiprah dan melaksanakan Tridharma.
Bisa jadi, keterkejutan kita dengan kebijakan Kementerian Riset & Pendidikan Tinggi tentang keharusan publikasi di jurnal ilmiah terindeks (Scopus dan kawan-kawannya) adalah refleksi dari absennya aktivitas baca-tulis-diskusi di tengah kesibukan mengajar-terlibat dalam proyek riset-memberdayakan masyarakat.
Hal ini bisa jadi tidak bisa disalahkan. mengingat (1) hampir semua universitas di Indonesia berorientasi pada pengajaran, dan bukan riset serta (2) padatnya aktivitas mengajar membuat aktivitas membaca, menulis, dan berdiskusi dengan kolega (atau mahasiswa) menjadi minim.
Akademisi kita (terutama yang masih muda) mengajar 9-10 mata kuliah per minggu, setiap semester, tanpa adanya kesempatan untuk sabbatical leave atau minimal kesempatan untuk duduk diam melakukan penelitian. Belum dengan bimbingan dengan mahasiswa S1, S2, atau S3 yang juga menyita waktu. Plus dengan tumpukan aktivitas administratif untuk keperluan akreditasi departemen atau pengelolaan Universitas, yang membuat banyak aktivitas tersita untuk rapat, mengurus dokumen, atau urusan ke Jakarta.
Saya tidak perlu menyebut fakta lain bahwa para akademisi kita juga punya keluarga di rumah – kecuali bagi segelintir dosen dan peneliti muda yang masih melajang karena belum mendapatkan pasangan.
Namun demikian, beban yang berat ini sebetulnya bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan terjadi juga di negara-negara lain. Namun demikian, di beberapa negara lain, ada beberapa kelonggaran institusional terkait hal ini, seperti. Sabbatical leave yang memungkinkan seorang akademisi dibebaskan dari beban administratif dan pengajaran sebanyak 6 bulan-1 tahun setelah 5-7 tahun. Sehingga, dosen bisa menggunakan waktu tersebut untuk meningkatkan produktivitas risetnya tanpa terganggu oleh aktivitas lain.
Di beberapa tempat lain, universitas juga mengakui profesi Peneliti (Research Fellow) yang setara dengan staf akademik lain, dengan kewajiban hanya melakukan riset atau mengelola lembaga penelitian. Kelembaman institusional jadi penting. Namun, pada dasarnya kelembaman ini hanya akan berjalan efektif jika tradisi pengetahuan terlembagakan dalam institusi pendidikan di Indonesia.
Produktivitas akademik hanya bisa terjaga jika para peneliti punya waktu membaca secara rutin, menulis di publikasi akademik dan mereview artikel jurnal, serta aktif berdiskusi dengan kolega untuk menguji gagasan-gagasan baru. Tentu ini sangat ideal, namun jika ingin para akademisi dan peneliti kita punya karya baik, pengaturan kelembagaan mesti diperbaiki untuk memungkinkan tradisi pengetahuan terjaga.
Kedua, bisa jadi keterkejutan akademisi kita dengan kebijakan publikasi adalah refleksi dari diskoneksi komunitas akademik kita dengan komunitas akademik di luar negeri, yang sebetulnya beragam dan sangat tergantung dengan (1) disiplin (2) minat riset, atau (3) bahkan jejaring antar universitas yang ada.
Kita bisa mengambil contoh pada minimnya keanggotaan akademisi kita dengan Asosiasi Profesi yang terlembaga secara internasional, yang sebetulnya bisa didapatkan secara sangat mudah dengan membayar. Asosiasi Profesi yang biasanya ada secara global menjadi penting sebagai ‘komunitas akademik’ karena tidak semua peneliti bisa berdialog dan berkomunikasi secara luas, karena batasan disiplin atau minat riset.
Sebagai contoh, dalam studi Hubungan Internasional (yang sudah saya geluti sejak 10 tahun silam), ada beberapa Asosiasi Profesional besar semacam International Studies Association atau International Political Science Association yang keanggotaannya terbuka baik bagi dosen dan peneliti yang meminati studi Politik atau Hubungan Internasional. Setiap tahun, ISA menyelenggarakan Konvensi tahunan di Amerika Utara dan menerbitkan 6 jurnal akademik dengan Impact Factor tergolong baik.
Keanggotaan ISA tergolong cukup murah, hanya $25 per tahun untuk mahasiswa dan $40 per tahun untuk Dosen. Dengan parameter ISA saja, sebetulnya, para akademisi bisa punya target untuk publikasi di 6 jurnal yang terpercaya atau presentasi di Konvensi tahunan ISA (atau Konferensi Regional mereka yang setiap dua tahun diselenggarakan di negara Asia/Pasifik.
Belum lagi dengan beberapa asosiasi/jurnal akademik yang lain yang tidak hanya mencakup satu disiplin, tetapi lintas-disiplin berdasarkan minat riset, seperti Earth System Governance (untuk kajian lingkungan), Millennium (jurnal yang berbasis di Inggris, untuk Teori), atau Association of Asian Studies (untuk kajian Asia). Begitu pun dengan jaringan serupa di Asia Timur, Afrika, atau Amerika Latin yang juga bergeliat dan berkembang dengan tradisi akademik masing-masing yang tidak melulu sama dengan rekan-rekan di Eropa atau Amerika Utara.
Tentu saja ada banyak dosen dan akademisi Indonesia yang punya reputasi global, baik di dalam dan luar negeri. Namun demikian, kita perlu mengakui bahwa kebijakan pendidikan tinggi Indonesia belum berorientasi pada penguatan jaringan akademik berbasis peneliti. Karena masih lebih banyak berorientasi pada institusi. Tentu saja, kerjasama institusional penting, namun tidak cukup untuk menopang riset. (Bersambung)