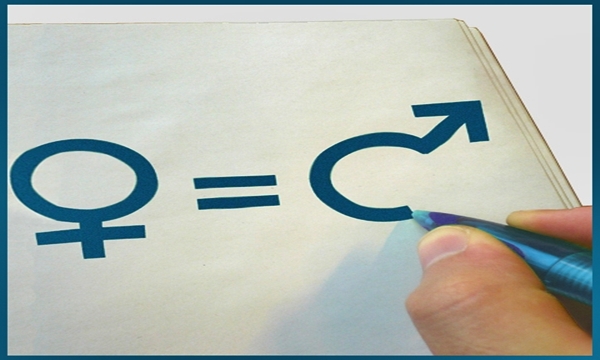Islam sering kali digambarkan sebagai ajaran yang sedemikian patriarkis. Mulai dari Taliban yang melarang kaum perempuan bersekolah, bahkan keluar rumah, hingga aneka kartun media Barat yang meledek para muslimah bercadar.
Islam sering kali digambarkan sebagai ajaran yang sedemikian patriarkis. Mulai dari Taliban yang melarang kaum perempuan bersekolah, bahkan keluar rumah, hingga aneka kartun media Barat yang meledek para muslimah bercadar.
Belum lama berselang, di media sosial santer kontroversi tentang Dewan Ideologi Islam di Pakistan mengizinkan suami memukul istri jika menolak berhubungan seks. Seolah ada pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap istri, yang identik dengan pemaksaan kehendak suami. Polemik terus berlanjut hingga bagaimana prosedur pemukulan, seberapa keras, dan seterusnya. Intinya, Islam digambarkan sebagai agama yang membenarkan penindasan terhadap perempuan.
Bagaimana posisi perempuan dalam Islam terus diperdebatkan para ulama. Sebagian menuding Islam kurang menghargai kaum ini, akibat beberapa budaya kerap memposisikan perempuan sebagai benda, bukan manusia.
Bermunculanlah para feminis seperti Aminah Wadud, Mustansir Mir, Fazlur Rahman, Abdullah Saeed, yang menganggap banyak penafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang bertentangan dengan keadilan dan kesetaraan manusia, baik pria dan wanita, di mata Allah. Sebut saja tafsir atas hukum poligami, pembagian hak waris, hingga kepemimpinan oleh perempuan.
Intinya, Islam kerap dituding sebagai agama yang sangat patriarkis. Terlebih dengan beragam pemberitaan tentang bagaimana wanita-wanita di sejumlah negara Islam diperlakukan bagai harta milik pria. Tidak boleh mengendarai mobil, dilarang mengecap pendidikan tinggi, dinikahi secara paksa, dan sejenisnya. Padahal itu semua bukan ajaran Islam, melainkan tradisi dari bangsa bersangkutan yang kebetulan saja berpenduduk mayoritas Islam.
Saya tidak mau berpolemik mengenai tafsir atau kritik para feminis tersebut, sebab bukan ranah saya. Namun Islam yang saya kenal melalui kisah para nabi sangat berbeda dengan yang dituduhkan sebagian orang.
Kata orang bijak, apa yang diyakini seseorang bisa tergambar dari kesehariannya. Dari bagaimana Nabi Muhammad SAW memilih pasangan hidup, kita bisa tahu bahwa beliau bukanlah seorang patriarkis. Bagaimana mungkin seorang patriarkis akan menikahi seorang perempuan pebisnis sukses yang usianya jauh di atasnya?
Kekayaan Siti Khadijah binti Khuwailid di usia 40 tahun berlipat-lipat dari Muhammad yang kala itu berusia 25. Khadijah juga digambarkan sebagai wanita mandiri secara ekonomi. Bahkan dialah yang memberi dukungan moril dan materil kepada Rasul untuk menyebarkan ajaran Islam.
Kemandirian dan ketangguhan Khadijah membuat Muhammad tidak menduakannya hingga Khadijah wafat di usia 65. Selain karena cinta, bisa jadi Muhammad merasa enggan untuk berlaku poligami terhadap istri pertamanya yang sangat powerful itu.
Istri ketiga Nabi Muhammad, Siti Aisyah, dikenal sangat cerdas dan berwibawa. Hingga pernah memimpin 30.000 pasukan dari Mekkah saat perang berlangsung. Kisah tersebut mengilustrasikan betapa Nabi telah memberi keleluasaan bagi istri-istrinya untuk berkiprah di luar rumah. Sangat jauh dari gambaran suami yang menindas hak-hak istri.
Dari sini saja kita dapat melihat Muhammad bukan seorang patriarkis. Dia menempatkan sang istri setara dengan dirinya, tidak menganggapnya sebagai benda sebagaimana para pria kebanyakan di zamannya.
Tradisi Arab era jahiliyah, yang sebagian masih dipraktikkan hingga sekarang, sangat ditentang Muhammad. Misalnya tradisi yang menganggap kelahiran bayi perempuan tidak pantas untuk dirayakan sebagaimana bayi lelaki. Nabi Muhammad justru memerintahkan agar bayi perempuan mendapat perayaan kelahiran, sebab mereka bukan aib.
Di era Arab sebelum Islam, seorang pria bebas mempunyai istri sebanyak mungkin, sebab kaum perempuan tak ubahnya dengan harta benda yang bisa dibeli. Muhammad mengecam keras praktik ini dengan membatasi poligami yang tak lebih dari empat istri, dan harus diperlakukan secara adil. Mengenai bagaimana bisa adil terhadap empat istri ini pun sampai hari ini masih terus diperdebatkan di kalangan umat Islam.
Dalam The Status of Women in Early Islam, Freda Hussain menyebut Nabi Muhammad setidaknya telah merombak enam hukum di era Arab jahiliyah. Semua sangat memuliakan posisi perempuan. Mulai dari tradisi penguburan bayi perempuan, hak waris, ikatan pernikahan, kontrol wanita atas mas kawin, nafkah, hingga aturan menikah lagi. Saya yakin, jika Nabi Muhammad masih hidup akan lebih banyak lagi hukum yang dia tetapkan demi memajukan kaum perempuan. Terlebih dengan maraknya kasus perkosaan atas perempuan dan anak-anak.
Jika Nabi Muhammad SAW sedemikian toleran dan memuliakan wanita, lalu mengapa muncul anggapan bahwa Islam adalah agama yang menindas wanita? Lagi-lagi kembali ke budaya suatu bangsa di mana suatu ajaran agama dipraktikkan.
Sebagai gambaran paling simpel, Amerika Serikat, yang bukan negara Islam, justru belum pernah punya presiden perempuan. Hillary Clinton yang kini mewakili Partai Demokrat mendapat serangan bertubi-tubi dari kalangan konservatif yang masih sangat berpandangan patrarkis. Dan lawan Hillary pun tidak tanggung-tanggung, Donald Trump, yang kita kenal sebagai sosok amat sangat patriarkis.
Bagaimana dengan Indonesia? Kendati populasi Muslim sangat dominan, kita pernah punya presiden wanita. Bahkan Pakistan pun pernah dipimpin Benazir Butho, pemimpin negara Islam pertama di dunia.
Dari semua paparan di atas, rasanya sangat naif jika masih menganggap Islam adalah agama yang menindas wanita. Konsep patriarkis tidak lahir dari keyakinan beragama, melainkan pola pikir yang sudah terbangun dan terburu berkarat. Bahkan seorang atheis sekalipun bisa menjadi patriarkis sejati. Dan perlu diingat, pandangan patriarki sudah muncul jauh sebelum agama-agama lahir.
Jadi, Muslim yang beranggapan bahwa dirinya harus bersikap patriarkis berarti dia tidak meneladani Nabi Muhammad. Muslim yang patriarkis justru mewarisi tradisi jahiliyah yang ditentang keras oleh Nabi.
Terkait