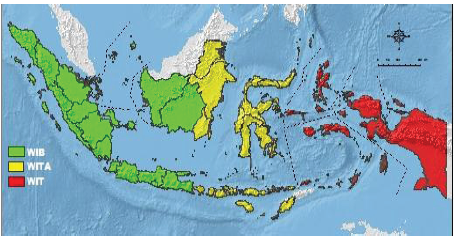Menjadi orang Indonesia adalah suatu proses, bukan peristiwa, apalagi suatu definisi, yakni sesuatu yang selesai, pasti, dan jelas. Menjadi orang Indonesia adalah kemenjadian seseorang untuk meyakini bahwa dirinya bagian dari Indonesia sekaligus merasa belum menjadi bagian dari Indonesia. Sebelum jauh memahami “menjadi orang Indonesia”, kita perlu paham terlebih dahulu, apakah Indonesia?
Saya tahu bahwa pembahasan ini tak cocok dalam bentuk artikel sesingkat ini. Namun secara substansi, saya ingin menyampaikan bahwa “Menjadi orang Indonesia” adalah sesuatu yang dinamis, kompleks dan penuh tensi (tarik menarik).
Apakah Indonesia? Begitu banyak sarjana yang berusaha mendefinisikan Indonesia. Realitas tentang Indonesia bisa saja sesuatu yang terbayangkan oleh si pembuat narasi: Ben Anderson, Benda, Castle, Ricklefs, Philphott, Pram, Tan Malaka, Joshua Oppenheimer’ dan yang lainnya. Masih banyak lagi para sarjana yang mengungkapkan apa itu Indonesia.
Namun apakah semua itu benar? Tentunya benar semua, karena mereka mengolah data tentang realitas yang ada pada suatu realitas yang awalnya diklaim/diasumsikan sebagai ‘Indonesia’ lalu setelah secara selektif (deliberative) dikumpulkan datanya, maka mereka menamainya sebagai Indonesia. Di sini Indonesia ‘Ada’ (Being) karena ada asumsi awal (pre assumption) ‘ide’ tentang Indonesia.
Lagi-lagi, menurut saya, Indonesia adalah sebuah narasi tentang tarik menarik antara masa lalu (past) dan masa depan (future) yang secara praktis dijalankan di masa kekinian (present). Siapapun boleh tahu tentang Indonesia dan menjadi Indonesia, tapi apakah itu benar adanya?
Menjadi orang Indonesia adalah ketika dia tahu betul masa lalu narasi Indonesia dibuat, dikonstruksikan entah oleh sarjana, rezim, kepala negara/pemimpin, tukang becak atau pengemis. Namun kita seringkali mengambilnya dari narasi besar sarjana dan pemimpin politik, bukan dari narasi kecil seperti petani atau buruh atau tukang bangunan.
Jadi mengetahui Indonesia adalah sekaligus berproses menjadi Indonesia. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Banyak pertanyaan untuk kita renungkan sebagai orang yang mendaku orang Indonesia:
Apakah ketika kita memiliki KTP Indonesia otomatis menjadi orang Indonesia sejati? Ber-KTP Indonesia tapi justru menjadi beban bagi Indonesia; Ber-KTP Indonesia justru berbuat ribut dan kisruh di Indonesia; Ber-KTP Indonesia justru ingin ‘mensuriahkan’ Indonesia atau meng-‘Arab Spring’-kan Indonesia; Ber-KTP Indonesia justru berkontribusi nol kepada Indonesia, sekaligus mencaci maki yang memberi kontribusi kepada Indonesia.
Apakah ketika kita menjadi beban negara Indonesia kita adalah orang Indonesia sejati atau justru orang yang sebenarnya hanya menumpang hidup di Indonesia? Jika kita menumpang dan menjadi beban, lalu apa bedanya kita dengan benalu parasit pada inangnya?
Apakah dengan berkontribusi kepada Indonesia, ‘kita’ menjadi orang Indonesia? Secara given, orang yang merasa dan telah menjadi Indonesia jawabannya pasti seratus persen orang Indonesia. Namun ada pertanyaan reflektif lainnya, jika berkontribusi kepada Indonesia apakah kita malah bukan Indonesia? Mengapa? Sebab jika kita kontribusi ke sesuatu, ke sekelompok orang atau bangsa atau negara, maka kita memiliki identitas jauh lebih besar dari yang kita kasih kontribusi. Lalu kita apa dan siapa? Kok memberi ke Indonesia?
Misalnya, Raja Yogyakarta memberi modal untuk pendirian Indonesia atau Raja Aceh memberi emas monas untuk Indonesia, bukankah mereka lebih besar dari Indonesia? Jika kita memberi kepada Indonesia, bisa jadi kita lebih dari Indonesia itu sendiri. Hal ini memberikan pemahaman bahwa dialektika menjadi orang Indonesia dan bukan-menjadi-orang-Indonesia dalam diri seseorang menjadi sangat penting, karena justru bias jadi hal inilah yang menjadikan seseorang orang Indonesia (ada proses dialektika yang terus menerus).
Apakah menjadi orang Indonesia diukur dengan kulit, agama, bentuk badan, dan ras yang ada di pulau yang diklaim oleh negara Indonesia? Jika bermata sipit, apa bukan Indonesia? Jika Syiah, maka bukan Indonesia? Apa jika berkulit hitam, bukan Indonesia? Apa jika mencintai budaya Arab, bukan Indonesia? Apa jika…
Apakah menjadi orang Indonesia diukur oleh lamanya leluhur berdiam di pulau yang diklaim bangsa ‘baru’ Indonesia? Lalu ukuran lamanya berapa tahun atau berapa abad? Sebab yang termasuk lama pun dengan ukuran turunannya Majapahit saja dipinggirkan haknya di Indonesia sebagai bukan Indonesia. Mereka dianggap sebagai penganut agama bukan “agama Indonesia”, karena tidak diakui oleh Kementerian Agama. “Agama lokal” yang sudah lama sekali di Indonesia dianggap bukan “agama Indonesia” tapi dianggap sebagai “budaya lokal” tertentu misalnya Sunda, Jawa, dll.
Lalu apakah menjadi orang Indonesia adalah menjadi orang yang meneriakkan “Allahu Akbar!” dengan mengepalkan tangan ke udara mengancam orang yang bermata sipit dan beragama impor? Apakah yang berteriak itu beragama lokal atau impor? Jadi sebenarnya mereka itu orang darimana?
Menjadi orang Indonesia menurut saya adalah proses kita memahami narasi bayangan seseorang, lalu menjadi sekelompok orang, lalu menjadi banyak kelompok orang-orang yang bersepakat. Kesepakatan ini dibentuk oleh sebuah narasi tarik menarik antara masa lalu (past) dan masa depan (future) yang secara praktis dijalankan di masa kekinian (present) disertai dengan dinamikanya dan kompleksitasnya.
Bayangan baik untuk mengkonstruksi makna agar hidup kita bermakna. Bayangan dibuat untuk kepentingan manusia agar terisi hidupnya, jelas dari mana dan akan kemana. Bayangan itu sekedar standar sementara bagi manusia untuk mengarungi hidup yang lebih luas lagi, yakni hidup darimana dan akan kemana.
Bayangan tentang Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, Burung Garuda, Pancasila, lagu, bendera, bahasa, dan dialektika adalah perdebatan dari sejak narasi bahkan sebelum Majapahit harus dimaknai sebagai konstruksi Indonesia. Hal ini yang kita perlu pahami sebagai proses.
Sebenarnya masih banyak lagi narasi konstruksi Indonesia seperti kompleksitas tarik menarik orang-orang nasionalis-sekuler, Kristen, Buddha, Hindu, berbagai macam suku, ras, Islam Jawa, Islam-Arab, Islam-baru-jadi-jadian yang tanpa fondasi trajektori pengetahuan jelas tentang revolusi Indonesia yang diilustrasikan dengan apik oleh Kahin.
Ada suatu kesepakatan menjadi orang Indonesia yang seharusnya tidak dipotong ‘antriannya’, tidak disalip, diserobot, atau didesak. Orang-orang yang sungkan mengantri semacam ini sangat mengkhawatirkan dan membahayakan trajektori Indonesia sebab akan mengacak-acak kesepakatan awal tanpa ada usaha memahaminya. Mereka bertindak seolah-olah Indonesia itu sudah jadi sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Padahal, Indonesia adalah suatu proses panjang bahkan sejak sebelum Majapahit lahir, mungkin jaman Kapitayan.
Demikian pula “menjadi orang Indonesia” adalah proses seseorang memahami masa lalu keindonesiaan demi fondasi makna hidup kekinian dan masa depan. Masa kini adalah masa depannya masa lalu yang dipenuhi makna dari memori masa lalu. Keterjebakan atas masa lalu menjadikan tradisi tertutup, padahal tradisi bersifat dinamis, terbuka dan berubah-ubah dengan tetap berfondasi pada prinsip-prinsip masa lalu.
Menjadilah orang Indonesia dengan terus memaknai trajektori keindonesiaan. Janganlah terjebak pada masa lalu bayangan tentang Indonesia sehingga menjadi stagnan atas tradisi lama lalu gagap, gelisah, dan bingung menghadapi masa kekinian; ketakutan atas masa kini tanpa fondasi akar kuat tradisi masa lalu Indonesia menjadikan kita mengambil masa lalu bangsa lain (misalnya Arab atau Barat) untuk mengisi makna masa kini kita. Hal inilah yang memprihatinkan.
Oleh sebab itu, sejak dini, generasi kita perlu diberikan makna hidup atas trajektori keindonesiaan, bukan trajektori bangsa lain. Trajektori bangsa dan negara lain justru menjadi justifikasi akan trajektori keindonesiaan kita dan bukan malah tersihir mengikutinya. Makna hidup menjadi orang Indonesia adalah proses panjang akan makna “becoming Indonesia” dan memaknai diri terus menerus sebagai “kemenjadian orang Indonesia”.
Memang semuanya itu bayangan saja, sebuah imajinasi kesepakatan orang-orang terdahulu kita. Namun demi keharmonisan hidup kita dan kebermaknaan hidup kita yaitu darimana kita berasal dan akan kemana kita, maka kesepakatan menjadi orang Indonesia dan makna akan trajektori keindonesiaan yang sifatnya konstitutif menjadi amat sangat penting untuk kita lanjutkan secara dialektis dan berkelanjutan demi mencapai kesepakatan-kesepakatan baru dan makna baru.
Menjadi orang Indonesia juga menjadikan diri kita berbeda dengan bangsa lainnya sehingga di sini kita punya identitas dan modal untuk kita tawarkan kepada bangsa lain, serta sumber referensi yang berbeda untuk mengisi kekosongan bangsa lain sehingga hubungan antarbangsa yang berbeda-beda menjadi berwarna, bermakna dan saling memaknai.