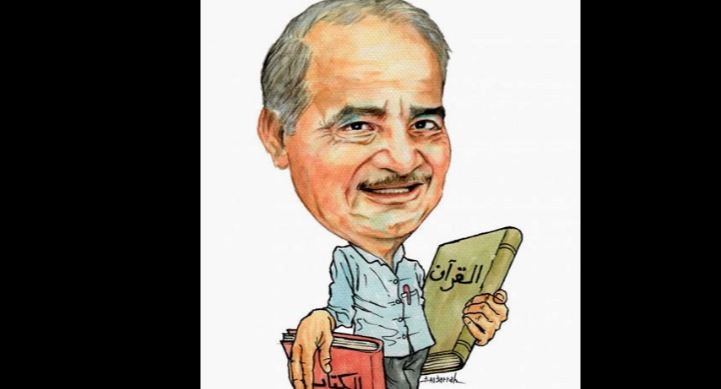Muhammad Syahrur adalah sosok kontroversial yang pernah hidup di dunia ini. Pemikirannya tidak hanya mendapatkan kritik dari kaum konservatif, tetapi juga dari kelompok liberal seperti Nasr Hamid Abu Zayd. Dekonstruksi adalah salah satu ciri khas pemikirannya.
Bagi ulama-ulama konservatif, Syahrur adalah sosok yang paling dibenci. Hal itu disebabkan karena dia selalu membongkar kemapanan-kemapanan yang ada. Mulai dari permasalahan teologi yang dianggap profan hingga perkara hukum (syariat) yang selama ini dianggap final (qath’i).
Meskipun begitu, Syahrur tidak pernah meninggalkan dekonstruksi yang dilakukan tanpa sebuah tawaran dan gagasan. Ia selalu memberikan konsep tandingan yang baru, yang lepas dari teori-teori sebelumnya. Menurut Amin Abdullah gaya Syahrur ini menyebabkan shifting paradigm, yakni gegar otak. Pergeseran paradigma, yang tanpa mempedulikan bangunan keilmuan sebelumnya, tentu akan memantik polemik.
Sebuah ijtihad tidak harus berangkat dari teori-teori sebelumnya. Perkara ijtihad dapat muncul dari sebuah latar belakang yang sama sekali berbeda, meminjam istilah dari Amin Abdullah sebagai fresh ijtihad. Sehingga sangat disayangkan, jika fenomena Syahrur tersebut ditanggapi secara emosional dan apriori.
Tulisan ini berkepentingan melacak dekonstruksi yang dilakukan Syahrur tersebut. Sangat tidak mungkin, Syahrur melakukan hal tersebut tanpa sebuah latar belakang yang memotivasi dirinya. Tulisan ini juga akan mengungkap, dasar teori yang digunakan Syahrur sekaligus memberikan beberapa kritik terhadap pemikirannya yang berbeda dari sebelumnya.
Motivasi Dekonstruksi Syahrur
Dekonstruksi yang dilakukan Syahrur setidaknya berangkat dari dua faktor, subjektif dan objektif. Pertama, faktor subjektif merupakan motivasi (kesadaran) yang berangkat dari dalam dirinya (self awareness) ketika melihat dinamika kajian keislaman (dirasah al-islamiyah) dan keadaan umat Islam.
Syahrur adalah sosok yang ekspresif, dia tidak dapat menyembunyikan kemarahannya dan selalu meledak-ledak ketika mengungkapkan sesuatu. Apalagi sesuatu itu menurutnya bertentangan dan menyebabkan kerusakan. Hal ini terlihat hampir semua karyanya.
Sebagai contoh dalam bukunya Dirasat Islamiyah Mu’ashirah fi Ad-Daulah wa al-Mujtama’. Di sini dia mengungkapkan bahwa pasca kematian sahabat Ali ra, ketika sistem pemerintahan dipegang oleh Mu’awiyah, tiran Islam mulai bangkit dan memengaruhi segala hal termasuk pemikiran keislaman. Baginya tidak ada lagi pemikiran yang lain, sebab orang yang berseberangan dipastikan, minimal akan mendapatkan siksaan fisik dan maksimal dipenjara atau dibunuh.
Lanjutnya lagi, hakim di era ini, adalah hakim mutlak (otoriter) yang anti koreksi dan anti pertanyaan. Segala hukum dianggap given (pemberian Tuhan). Apalagi proses pergantian kepemimpinan itu terjadi melalui kudeta, seperti yang terjadi pada kekuasaan Mamluk dan Ustmani. Baitul Mall berada di bawah kendali hakim, seolah-olah itu adalah hartanya.
Masalah-masalah harta tergantung pada selera penguasa. Kalau penguasanya baik, seperti Umar bin Abdul Aziz, maka beruntunglah masyarakat. Namun ketika penguasanya zalim, maka masyarakat akan hidup menderita, menunggu sampai petaka ini selesai dalam waktu yang tidak dapat ditentukan.
Syahrur juga memberikan tudingan, bahwa di bawah kekuasaan tiran ini umat Islam diajak untuk menerima kenyataan baik dan buruk apa adanya tanpa proses kritis dan usaha untuk memperbaiki. Konsep qadla dan qadar direkonstruksi seperti itu untuk mengamankan kekuasaan. Kekhalifahan diposisikan sebagai representasi Tuhan di bumi. Pembangkangan terhadap kekhalifahan sama dengan membangkang terhadap perintah Tuhan.
Kekuasaan tiran ini juga merusak sistem perundang-undangan Islam (fiqh). Kekuasan di era ini mencoba menggabungkan atau menghilangkan sistem legislasi. Semua hal dipegang dalam satu tangan. Ketundukan dan kepatuhan (taat kepada ulil amri) menjadi terminologi dan dasar yang kuat untuk melenyapkan syura. Kritik yang paling keras dari Syahrur adalah era ini, kepemimpinan ini, tidak ubahnya seperti Fir’aun.
Bahasa sarkastik seperti itu tentu saja lebih banyak memantik emosi dan kemarahan ketimbang simpati. Namun itulah gaya Syahrur yang ekspresif. Baginya, gaya seperti itulah yang efektif menumbuhkan kesadaran intelektual muslim. Mereka harus dipecut, agar mau membaca kembali sejarah yang selama ini mapan dan dianggap sakral tersebut.
Kedua, faktor objektif, yakni kemandegan (jumud) pemikiran keislaman (dirasah al-islamiyah). Keadaan seperti ini tidak hanya dirasakan oleh Syahrur, melainkan hampir semua intelektual Muslim lainnya, terutama yang berkiblat kepada Muhammad Abduh atau yang berpandangan progresif.
Kebangkitan Islam di penghujung abad 18, ternyata hanya mampu memunculkan kesadaran umat Islam agar bangkit dari ketertindasan dan keterjajahan, tetapi gagal dalam merekonstruksi paradigma kemajuan umat Islam. Hal ini terbukti pasca Muhammad Abduh, pembaharuan pemikiran keislaman berjalan sangat lamban. Produk-produk hukum Islam saat ini masih didominasi pemikiran abad pertengahan.
Begitu juga yang terjadi dalam karya tafsir. Saat ini dapat dikatakan terjadi arus balik pemikiran tafsir. Karya-karya tafsir yang muncul pasca kebangkitan umat Islam mulai ditinggalkan. Tafsir Al-Manar, yang menjadi ikon kebangkitan umat Islam kini tidak lagi terdengar. Umat Islam, ternyata lebih tertarik dengan produk tafsir zaman kemunduran Islam. Padahal konteks zaman sudah sangat berbeda. Perubahan-perubahan besar (great disruption) yang terjadi saat ini tidak memberikan dampak pada pemikiran umat Islam.
Ajakan untuk membuktikan otentisitas Al-Qur’an, dengan memberikan bukti-bukti historis terhadap ayat-ayat polemik tidak banyak mendapatkan respons. Malah pendapatnya tersebut ditanggapi negatif oleh Yusuf Qardlawi. Arkoun kemudian dikategorikan sebagai pemikir Muslim yang mengabaikan keberadaan teks Al-Qur’an (ta’thil li an-nushush) sebagai anti tesis dari kelompok tekstualis (dzahiriyyah).
Hal serupa juga terjadi pada Nasr Hamid Abu Zaid. Ketika dia mengatakan bahwa Al-Qur’an merupakan teks budaya, dia malah dianggap sebagai pemikir Islam yang ingin merusak Islam dari dalam. Pikirannya tersebut dianggap sebagai pelecehan terhadap Al-Qur’an. Menganggap Al-Qur’an sebagai teks budaya sama dengan menyamakannya dengan produk manusia.
Gagasan tersebut terdapat dalam bukunya Mafhum An-Nash Dirasah fi Ulum al-Qur’an. Jika ditelaah, di dalam bukunya tersebut tidak terdapat maksud sebagaimana yang dituduhkan kepadanya. Al-Qur’an sebagai teks budaya yang dimaksud Nasr Hamid Abu Zaid adalah perubahan historis bentuk Al-Qur’an, yang semula berbahasa lisan (oral tradition) kemudian berubah dalam bentuk mushaf (teks), dan teks sesungguhnya adalah produk budaya.
Ketika Al-Qur’an masuk dalam peradaban teks, maka sejak saat itu pula Al-Qur’an tidak bisa dilepaskan dari keilmuan linguistik. Nasr Hamid Abu Zaid sebenarnya ingin mengajak umat Islam menggunakan keilmuan linguistik kontemporer untuk memahami nash-nash Al-Qur’an.
Begitulah kira-kira gambaran kemandegan kajian keislaman. Munculnya pikiran-pikiran baru dianggap sebagai upaya merusak tatanan kajian keislaman yang sudah mapan. Syahrur adalah sosok independen yang ingin keluar dari kondisi tersebut.
Melacak Sumber Dekonstruksi Syahrur
Berangkat dari kegelisahan inilah Syahrur memberikan konsep baru cara membaca al-Qur’an (qira’ah al-mu’asyarah), yang benar-benar berbeda dan tidak ada hubungannya dengan teori klasik sebelumnya. Namun, yang dilakukan Syahrur sebenarnya sama dengan Ibnu Hazm al-Andalusi, yakni dengan menggunakan pendekatan bahasa (dzahiriyah) meskipun metodologinya berbeda.
Sebagian besar memandang Syahrur termotivasi dengan teori bahasa dari Ibnu Faris, bahwa bahasa Arab mempunyai keunikan tersendiri, yakni tidak memiliki sinonimitas. Dari sinilah kemudian Syahrur membangun teorinya dengan menciptakan terminologi-terminologi baru dan sekaligus menerapkannya secara kaku. Seperti membedakan antara al-Kitab dan tanzil hakim, sunnah nubuwwah dan sunnah risalah, begitu juga dengan posisi Muhammad, sebagai Nabi, Rasul, dan manusia biasa (basyar).
Bagi Syahrur, perbedaan-perbedaan term (bentuk kata) memiliki konsekuensi tersendiri dalam merekonstruksi sebuah pemahaman. Syahrur sangat yakin kata-kata yang terdapat dalam Al-Qur’an memiliki maksud-maksud tertentu juga, dan jika itu dikaitkan satu dengan yang lainnya akan membentuk sebuah pemahaman yang utuh. Gagasan seperti inilah yang diyakini Syahrur hingga akhir hayatnya.
Dalam penelitian penulis, sebenarnya apa yang dilakukan Syahrur bukan hal yang baru. Penulis melihat ada kesamaan pola antara metode yang digunakan Syahrur dengan pemikiran Ferdinand de Saussure (selanjutnya disebut Saussure). Bahkan penulis melihat Syahrur benar-benar menggunakan teori Saussure tersebut secara baik. Kehebatan Syahrur adalah dia mampu mensintesiskan kerangka teori linguistik struktural Saussure dalam kajian keislaman secara matang.
Pertama, Saussure menjelaskan bahwa bahasa itu berkembang (sinkronik). Perkembangan bahasa mengikuti perkembangan sosial dan budaya tempat bahasa itu dituturkan. Para pakar bahasa sebelumnya memahami bahasa secara diakronik (beku). Oleh karena itu mereka terkadang melakukan penelitian bahasa secara filologi.
Konsep Syahrur tentang bahasa juga seperti itu. Syahrur meyakini bahwa bahasa itu berkembang. Bahasa Arab yang dahulu berbeda dengan bahasa Arab yang ada sekarang. Oleh sebab itu agar dapat memahami Al-Qur’an secara baik seseorang harus berpijak pada perkembangan Bahasa Arab kontemporer. Berangkat dari situlah ia selalu memberikan judul dalam buku-bukunya dengan kalimat qira’ah al-muasyirah (cara pandang kontemporer).
Karena bahasa itu berkembang, maka Al-Qur’an yang juga berbahasa Arab, pemahamannya juga berkembang. Perkembangan bahasa Al-Qur’an seirama dengan perkembangan zaman, oleh karena itu al-Qur’an maknanya bersifat progresif.
Kedua, Saussure membagi bahasa menjadi tiga bagian atau ranah, langage, langue dan parole. Langage adalah bahasa yang hidup dalam komunikasi yang melingkupi berbagai representasi identitas (bahasa daerah). Langue adalah konsep bahasa yang masih berada di dalam ide sebagai hasil dari konvensi masyarakat pada daerah tertentu. Sementara parole adalah artikulasi bahasa dalam komunikasi yang memiliki keunikan dan simbol-simbol bahasa yang khas.
Memang dalam tulisan-tulisannya Syahrur tidak pernah mengupas konsep ini. Namun dalam prakteknya Syahrur menggunakan pemisahan ranah bahasa ini. Sebagai contoh kata ummat yang masih abstrak dicirikan dengan langage. Kemudian kata qaum merupakan representasi dari parole. Dalam bukunya Dirasat Islamiyyah Mu’ashirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama’ Syahrur menjelaskan bahwa qaum dicirikan dengan ke khasan bahasa yang dimiliki. Sementara langue menurut Syahrur digunakan dalam bahasa.
Ketiga, Saussure menjelaskan bahwa bahasa bekerja berdasarkan sistem pembeda (differential). Misal ketika kita menyebut kata kursi, maka pemahaman terhadap kursi disebabkan karena adanya perbedaan dengan benda lain seperti meja, pintu, dan sebagainya. Jadi makna sebuah bahasa bukan terletak pada objek bendanya, melainkan pada perbedaan dengan benda lainnya.
Dari sinilah sepertinya Syahrur meyakini tidak ada sinonimitas dalam bahasa, dan dia temukan hal tersebut dalam teorinya Ibnu Faris. Pertanyaan yang diajukan adalah mengapa di dalam Al-Qur’an disebut kata al-kitab dan tanzil hakim, jika tidak ada maksud pembedaan tersebut?
Dari gagasan inilah Syahrur kemudian membuat konsep-konsep kunci dan menerapkannya secara kaku. Konsep differential bahasa inilah yang paling dominan nampak dari teorinya. Semua karya Syahrur, dari yang awal hingga yang akhir menunjukan differential bahasa.
Keempat, lebih lanjut Saussure membagi bahasa menjadi dua signifier (penanda) dan petanda (signified). Jika kita menyebut kata kursi, maka kursi disebut dengan penanda (signifier) yang dicirikan dari bunyi (phoneme) kursi. Sementara petandanya (signified) adalah huruf k-u-r-s-i. Huruf-huruf inilah yang membentuk tentang konsep kursi.
Syahrur sebelum memberikan argumentasi, selalu mengawali dengan membahas akar kata dari sebuah topik pembahasan. Menurutnya, kata bahasa Arab selalu berkaitan maknanya oleh sebab itu akarnya harus ditelusuri secara detail.
Adanya konsep tasyrif dalam bahasa Arab sangat sesuai dengan teori signifier dan signified. Salah satu contoh yang dilakukan Syahrur seperti memahami kata sunnah (signifier) yang menurutnya berasal dari kata sanna yang artinya “sesuatu yang mudah”. Maka, konsep sunnah (signified) tidak boleh lepas dari prinsip kemudahan.
Kelima, Saussure menjelaskan bahwa pemahaman terhadap bahasa tidak dapat dilepaskan dari model paradigmatik dan sintagmatik. Pemahaman bahasa secara paradigmatik adalah pemahaman bahasa yang terbangun dari konsep s-p-o-k (subjek – predikat – objek – keterangan). Sementara pemahaman sintagmatik adalah pemahaman yang terbangun dari relasi makna kata perkata atau dari kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Ada unsur logika dan keteraturan pemahaman di dalamnya.
Dekonstruksi teori Syahrur sebenarnya berangkat dari teori sintagmatik yang dikembangkan Saussure ini. Ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur’an, jika dikumpulkan akan menghasilkan pertautan makna yang membentuk struktur atau bangunan teori tersendiri. Fase puncak dari teori Syahrur adalah kemampuannya dalam hal merekonstruksi relasi makna antara satu ayat dengan ayat lainnya.
Teori sintagmatik ini jika dilihat dalam perspektif kajian tafsir lebih dekat dengan teori munasabah ayat. Namun teori munasabah yang dibangung Syahrur sangat berbeda dengan keilmuan tafsir pada umumnya. Teori munasabah tidak melepaskan konteks historis sebuah ayat. Sedangkan munasabah berbasis sintagmatik yang digunakan Syahrur tidak memedulikan konteks historis tersebut.