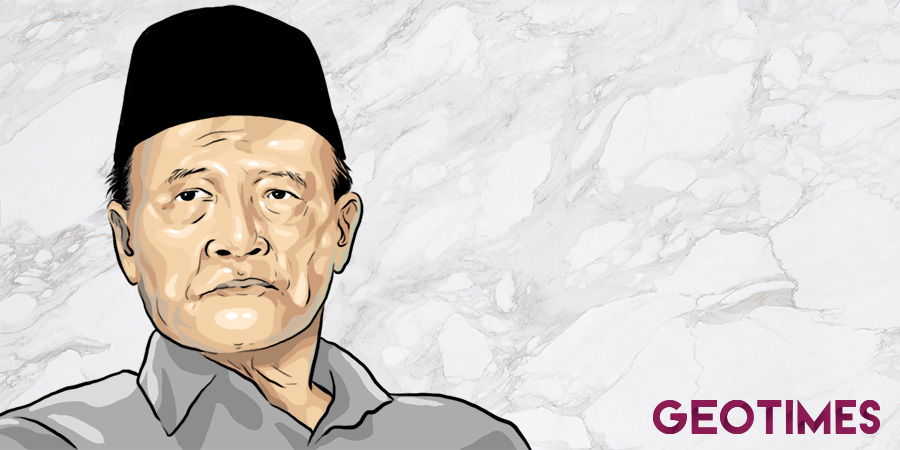Empat puluh hari yang lalu, bangsa Indonesia berduka sangat mendalam atas berpulangnya putra terbaik bangsa, Buya Ahmad Syafii Maarif. Lahir di Sumpur Kudus, Sijunjung, Sumatera Barat, 31 Mei 1935 dan wafat di Yogyakarta, tanggal 27 Mei 2022, dalam usia 86 tahun. Buya dikenal semasa hidupnya sangat sederhana dan bersahaja. Merasakan dan menghayati benar penderitaan rakyat. Meyakini agama Islam sebagai pedoman etika dan petunjuk hidup dengan sepenuh hati, namun tanpa kehilangan respek dan rasa hormat kepada pemeluk agama lain yang berbeda. Pluralis-inklusif, non-diskriminatif. Radius pergaulannya sangat luas, egaliter, dan teguh pendirian. Cendekiawan-intelektual-ulama berwawasan luas dan terbuka. Aktivis multidimensi. Sangat taat beribadah salat 5 waktu. Keteguhan integritas etisnya tidak diragukan. Penulis produktif, prolifik, dan kritis. Warga negara dan masyarakat Indonesia menobatkannya sebagai “muazzin bangsa”, bapak bangsa dan guru bangsa.[1] Pada tahun 2008 menerima Ramon Magsaysay Award for Peace and International Understanding,[2] selain itu, Buya menerima tanda jasa Bintang Mahaputra dari pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2015.
Kepergiannya meninggalkan pesan dan jejak pergulatan, pergumulan, dialog yang hidup bagaimana mengharmoniskan hubungan keislaman, keummatan, keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan kemanusiaan dalam sukma dan jati diri warga dan bangsa Indonesia. Sepanjang karir kehidupannya, Buya bergumul tidak kenal lelah dengan keenam elemen dasar tersebut dalam hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pergumulan dan dialog yang hidup tersebut disampaikan dalam ceramah, tulisan dan buku-bukunya. Pergumulan tersebut sejatinya mewakili sosok kegelisahan dan pergulatan sosok “manusia Indonesia” yang sesungguhnya. Kehidupan Buya adalah cermin yang terang benderang memantulkan hakekat, jati diri, sekaligus keprihatinan warga negara dan bangsa Indonesia pada umumnya. Warisan keprihatinan dan kegundahan Buya sangat dialami, dihayati dan dirasakan oleh warga negara dan bangsa Indonesia yang majemuk secara agama, kepercayaan, etnis, suku, ras, golongan, partai dan kelas.
Pidato kebudayaan memperingati empat puluh hari wafat Buya, selain sebagai tribute untuk almarhum, juga akan memotret akar dari kegelisahan Buya selama hidupnya di dalam upaya bagaimana menjaga keseimbangan dan mengatur satu kesatuan tarikan nafas antara keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan.[3] Kiprah perjuangan, pemikiran dan wawasan yang ditinggalkan Buya untuk generasi penerus kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara perlu terus menerus dikaji oleh umat beragama dan warga negara Indonesia pada umumnya.
Dalam pidato Syafii Maarif memorial lecture ini, saya akan memotret Buya Ahmad Syafii Maarif dari perspektif bagaimana almarhum mengejewantahkan atau menerapkan pandangan hidup seorang Muslim progresif dalam karir hidupnya dan bagaimana sebagai seorang yang beriman/beragama/berislam yang otentik namun penuh semangat patriotik (faithful patriotism) dalam berjuang membela hak-hak kewargaan, kemajemukan, Pancasila, kebhinnekaan, toleransi, inklusivitas dan kemanusiaan di tengah hutan belantara keummatan, perpolitikan, keindonesiaan, kebangsaan dan kenegaraan.
Muslim progresif
Pemikiran Islam kontemporer sekarang ini sejatinya lebih kompleks. Setidaknya, ia mewakili 3 (tiga) fase sejarah pemikiran Islam sekaligus, yaitu era Traditional, Modern dan Postmodern. Saya katakan kompleks karena ketiga-tiganya hidup bersama-sama dan berdampingan, untuk tidak menyebutnya campur aduk, pada saat sekarang ini. Terlebih pada era digital dan media sosial yang merubah semua tatanan kehidupan berinteraksi dan berkomunikasi. Kadang berjalan berdampingan, kadang berbeda arah dan haluan, dan tidak jarang konflik, tergantung pada lingkungan dan cuaca sosial politik di dalam negeri dan atmosper hubungan internasional dan kasus-kasus yang melibatkan umat Muslim di luar negeri. Tapi, yang jelas ketiganya adalah gejala “contemporarity”, masing-masing mempunyai perannya sendiri-sendiri, ketiganya tidak dapat dipisahkan meskipun dapat dibedakan. Pemikiran Islam yang datang belakangan (Postmodernitas) tidak dapat meninggalkan pemikiran Islam sebelumnya (Modernitas), dan begitu saja corak pemikiran Islam Modernitas tidak dapat dipahami dengan baik tanpa memahami pemikiran Islam Tradisional. Ada kesinambungan sejarah perkembangan pemikiran Islam yang tidak terputus antara satu fase dengan fase lainnya. Pemikiran Islam tidak bisa dipenggal baik di awal, di tengah dan di belakang, tanpa resiko kehilangan akar kesejarahan kekayaan khazanah intelektual keislaman yang sangat kaya berikut nilai-nilai moral yang lengket di dalamnya. Beban sejarah manusia Muslim yang hidup di era kontemporer jauh lebih berat dari pada dua era sebelumnya, karena secara intelektual mereka harus memahami dengan baik perkembangan sejarah pemikiran Islam yang pernah dilalui sebelumnya, ditambah dengan kemajuan teknologi informasi dalam bentuk platform digital dan media sosial yang tidak terbayangkan sebelumnya dan tidak pernah terjadi di era yang manapun.
Belum lagi dilihat dari kompleksitas isi atau content dari pemikiran Islam. Sebagai contoh, Fazlur Rahman, guru Buya di Chicago, dalam bukunya Islam, terbit tahun 1979an menyebut tema-tema besar pemikiran Islam, antara lain mencakup Kenabian Muhammad, al-Qur’an, Hadis (Asal-usul dan Perkembangan Tradisi), Struktur Hukum, Teologi Dialektik dan Perkembangan Dogma, Syari’ah, Gerakan Filsafat, Doktrin dan Praktik Sufi, Perkembangan Sekte, Pendidikan, Gerakan Pembaharuan Pra-Modern dan Modern.[4] Sedang Abdullah Saeed, pelanjut ide Rahman dalam pengembangan tafsir al-Qur’an, menyebut beberapa item pokok Pemikiran Islam yang belum disebutkan dalam buku Rahman, antara lain the Islamist Extremists, the Secular Muslims dan the Progressive-Ijtihadists.
Tampak bahwa pemikiran Islam sangat padat dan kaya muatan. Menguasai yang satu, dengan meninggalkan yang lain bukannya tanpa resiko. Menguasai Kalam atau aqidah dan fikih, tetapi tidak memahami Tasawuf, misalnya, juga akan berakibat tidak utuhnya pandangan dunia keberislaman seseorang dan lebih-lebih para elite pimpinan kelompok atau organisasi keagamaan Islam. Sama halnya, sebutlah menguasai al-Qur’an dan al-Sunnah, tetapi tanpa mengenal dengan cukup baik diskusi Kalam, Tasawuf dan Fikih Siyasah (politik) dari era klasik atau abad tengah, moderen dan kontemporer akan terasa kering dan bisa salah ketika mengambil kesimpulan karena kehilangan nuansa historisitas perkembangan pemikiran keilmuan keislamannya.
Belum lagi jika harus menyebut keharusan intelektual Muslim era sekarang yang mensyaratkan perlunya pemahaman yang baik tentang persoalan sosial, ekonomi, budaya, politik, sains dan teknologi.Yang terakhir ini memerlukan pendekatan baru, yakni asupan dan sumbangan dari ilmu-ilmu sosial (social sciences), kemanusiaan kontemporer (humanities) dan sains dan teknologi. Isu-isu fundamental dan kontemporer seperti Negara Bangsa (nation-states), Kewargaan (al-muwathanah), Hak asasi manusia (HAM), Pluralitas, Multikulturalitas, Toleransi dan intoleransi, Gender, Hubungan Muslim dan non-Muslim, Lingkungan hidup, Globalisasi, Perubahan iklim (climate change), Pandemi Covid-19 dan seterusnya mengandaikan perlunya pendekatan dan pemahaman yang bercorak multi-, inter-, dan transdisiplin dalam Pemikiran Islam kontemporer. Buya Syafii Maarif sejak muda sampai usianya yang 86 tahun berenang mengarungi gelombang arus besar dari tiga generasi pemikiran Islam sekaligus. Oleh karenanya patut dicermati, ditelusuri rekam jejak pergulatan internal dan eksternal Buya dan patut pula diteladani bagaimana keahlian Buya mengolah, menavigasi dan membingkainya dalam format “keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan”.
Ada dua kata kunci penting yang biasa dikemukakan Buya Ahmad Syafii Maarif dalam berbagai kesempatan, baik dalam ceramah maupun tulisan, yaitu bagaimana umat Islam memperlakukan al-Qur’an sebagai kitab suci yang bermuatan pedoman etika dan pentingnya ilmu pengetahuan (scientific temper) bagi umat Islam. Ungkapan yang biasa digunakan Buya Syafii adalah “Mari kita berdialog dengan al-Qur’an” dan “Muhammadiyah -sebagai gerakan Islam moderen inklusif, yang dipimpinnya tahun 1998-2005- sebagai Gerakan Ilmu”. Dua untaian kata tersebut dicoba diramu ulang dari tetesan gurunya Fazlur Rahman, selama menempuh studi doktoral di universitas Chicago, antara tahun 1976 sampai akhir tahun 1983. Perjumpaan dan pergulatan intelektual dengan Fazlur Rahman dan keterpautan dirinya dengan tokoh-tokoh dalam jaringan pembaharuan pemikiran Islam mengubah jalan pikiran dan pandangan hidup Buya, dari yang semula agak Islamis-Maududian ke civil Islam-Rahmanian.[5] Sebuah corak pemikiran Islam yang berusaha mengatasi pergumulan keras seolah tanpa kenal henti dan dikotomi antara kesalehan keagamaan (al-mutadayyin) dan kesalehan kewargaan (al-muwathanah).
Ungkapan dan ajakan “berdialog dengan al-Qur’an” mengingatkan tafsir tematik Rahman, Major Themes of the Qur’an,[6] sedang “Gerakan Ilmu” terinspirasi dari bukunya yang lain, yaitu Islam and Modernity.[7] Terinspirasi oleh Rahman, Buya menafsirkan al-Qur’an berbeda dari para pendahulunya. Buya tidak menafsirkan al-Qur’an juz per juz atau ayat demi ayat tapi lebih memilih tema-tema atau ayat-ayat tertentu dalam al-Qur’an yang relevan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat moderen.[8] Karenanya, karya Buya lebih komunikatif dan mudah dicerna oleh masyarakat luas. Tema-tema yang diangkat antara lain tentang problem sosial kemanusiaan kontemporer, seperti keterbelakangan umat Islam, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, kejumudan, korupsi, kolusi, nepotisme, kemunafikan, tirani penguasa, otoritarianisme, despotic interpretation, negarawan versus politisi, kejujuran para pemimpin, dampak dari tindakan para politisi oligarki.
Dalam hubungan dengan tafsir tematik al-Qur’an, saya punya pengalaman dengan Buya ketika saya memimpin Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (1995-2000). Setelah muktamar Aceh, tahun 1995, saya diberi amanah oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah terpilih untuk memimpin Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Nama baru Majelis yang saya usulkan saat itu dan diterima oleh Pimpinan Pusat terpilih. Gagasan pembaharuan keilmuan dan wawasan sosial keislaman dalam Muhammadiyah saya tuangkan dengan cara membentuk divisi-divisi baru dalam Majelis, yang tidak terbatas lagi hanya pada fatwa fikih-keagamaan. Beragam divisi itu antara lain Wanita dan Keluarga, Pengembangan Pemikiran Islam dan Ilmu Pengetahuan/Teknologi; Pengembangan Pemikiran Islam dan Budaya; Hisab dan Pengembangan Tafsir dan lain-lain.[9] Dalam hal tafsir tematik hanya satu yang sempat terbit yaitu, Hubungan Sosial Antar Umat Beragama.[10] Tanpa ragu, Buya, sebagai Ketua PP Muhammadiyah memberi kata Pengantar pada buku Tafsir Tematik tersebut, meskipun dalam perjalanan berikutnya Tafsir Tematik tersebut dicukupkan pada cetakan pertama (Juli 2020) dan tidak dilanjutkan seterusnya.
Menurut Abdullah Saeed, ada enam kelompok pemikir Muslim era Kontemporer, yang corak basis ontologi, epistemologi dan aksiologinya berbeda dari yang satu dan lainnya. (l) The Legalist-traditionalist. Meskipun manusia Muslim hidup pada era modern, bahkan posmoderen sekarang, namun masih sangat banyak, bahkan mungkin merupakan mayoritas umat Islam, masih bercorak Legalist-traditionalist, yaitu corak keberagamaan Islam yang berpedoman pada hukum-hukum, cara berpikir sosial-keagamaan yang ditafsirkan dan dikembangkan oleh para ulama dan cerdik pandai periode pra-Modern; 2) The Theological Puritans, yang fokus pemikirannya pada dimensi etika dan doktrin Islam; (3) The Political Islamist, yang kecenderungan pemikirannya pada aspek politik Islam dengan tujuan akhir mendirikan negara Islam; (4) The Islamist Extremists, yang memiliki kecenderungan menggunakan kekerasan untuk melawan setiap individu dan kelompok yang dianggapnya sebagai lawan, baik Muslim ataupun non-Muslim;[11] (5) The Secular Muslims, yang beranggapan bahwa agama merupakan urusan pribadi (private matter); dan (6) The Progressive Ijtihadists, yaitu para pemikir modern atas agama yang berupaya menafsir ulang ajaran agama agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern. Pada kategori yang terakhir inilah, menurut hemat saya, posisi keulamaan dan intelektual keislaman Buya Ahmad Syafii Maarif berada.[12]
Karakteristik pemikiran Muslim progresif-ijtihadis, dijelaskan oleh Abdullah Saeed dalam bukunya Islamic Thought: An Introduction sebagai berikut : (1) mereka mengadopsi pandangan bahwa beberapa bidang pemikiran hukum Islam tradisional memerlukan perubahan dan reformasi substansial dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Muslim saat ini; (2) mereka cenderung mendukung perlunya fresh ijtihad dan metode baru (al-tajdid al-manhajy) dalam berpikir dan berpandangan keagamaan Islam untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer; (3) beberapa diantara mereka mengambil langkah mengkombinasikan kesarjanaan Islam tradisional dengan pemikiran dan pendidikan Barat modern; (4) mereka secara teguh berkeyakinan bahwa perubahan sosial, baik pada ranah intelektual, moral, hukum, ekonomi atau teknologi, harus tergambar jelas dan terrefleksikan dalam pemikiran dan pandangan hukum Islam; (5) mereka tidak mengikutkan dirinya terseret dan terjebak pada kubangan dogmatism atau madzhab hukum dan teologi tertentu (madzhabiyyah; hizbiyyah; thaifiyyah) dalam kajian dan pandangan-pandangan sosial-keagamaannya; dan (6) mereka meletakkan titik tekan pemikirannya pada keadilan sosial, keadilan gender, HAM, dan relasi yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim.
Sekilas tampak jelas bahwa corak epistemologi keilmuan Islam kontemporer, dalam pandangan Saeed, adalah berbeda dari corak epistemologi keilmuan Islam tradisional. Penggunaan metode kesarjanaan-keulamaan dan epistemologi tradisional masih tetap ada dan diperlukan, dimana nash-nash al-Qur’an dan al-Hadits menjadi titik sentral berangkatnya, tetapi metode penafsirannya harus didialogkan, dikawinkan dan diintegrasikan terlebih dahulu dengan penggunaan epistemologi baru, yang melibatkan social sciences dan humanities kontemporer dan filsafat kritis (critical philosophy).[13] Abdullah Saeed memang tidak menyebut penggunaaan metode dan pendekatan tersebut secara eksplisit disitu, tetapi pencantuman dan penggunaaan istilah ‘pendidikan Barat modern’ adalah salah satu indikasi pintu masuk yang dapat mengantarkan para pecinta studi Islam kontemporer ke arah yang saya maksud. Buya Ahmad Syafii Maarif memenuhi syarat yang dicantumkan oleh Abdullah Saeed. Latar belakang pendidikan, baik di tanah air maupun di luar negeri, memenuhi kriteria tersebut. Lebih-lebih lontaran-lontaran pemikiran keislamannya yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, baik ceramah, artikel di media, wawancara di televisi maupun buku-buku yang ditulis menjadi saksi dengan sendirinya.
Selain itu, juga isu-isu dan persoalan-persoalan humanities kontemporer terlihat nyata ketika Saeed menyebut “keadilan sosial”, lebih-lebih keadilan gender, HAM dan hubungan yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim. Buya Syafii juga demikian, meskipun dalam hal “kesetaraan gender”, buya Syafii tidak begitu vokal karena sudah merasa diwakili oleh ‘Aisyiyah dalam tubuh persyarikatan Muhammadiyah. Namun belakangan, tahun 2021, para penulis perempuan menulis khusus tribute untuk Buya dan diterbitkan dengan judul Ibu Kemanusiaan. Catatan-catatan Perempuan untuk 86 tahun Buya Ahmad Syafii Maarif.[14] Persoalan humanities kontemporer tidak akan dapat dipahami, dikunyah dan disimpulkan dengan baik, jika epistemologi keilmuan Islam masih terkungkung penggunaan metode dan pendekatan ‘Ulum al-Din lama. Pendidikan agama Islam di bangku sekolah sampai perkuliahan agama di perguruan tinggi, apalagi di berbagai tempat yang lain, termasuk pesantren di tanah air masih didominasi corak pengajaran dan pendidikan yang bercorak ‘Ulumu al-din lama, yang hampir-hampir tidak atau belum melibatkan riset lapangan (al-muqarabah al-maidaniyyah), termasuk belum membahas perihal kewargaan dalam negara bangsa yang tuntas dan mendasar dalam hubungannya dengan isu-isu dan paham keagamaan. Dalam Epilogue, Bab 12, Abdullah Saeed menjelaskan pandangan dan kritiknya terhadap Ilmu-ilmu Syari’ah (lama), yang terdiri dari Hadis, Usul al-fiqh dan Tafsir jika hanya berhenti dan puas dengan menggunakan metode, cara kerja, pola pikir dan paradigma lama.[15]
Buya Syafii dikenal sebagai kritikus sosial-agama, sosial-budaya dan sosial-politik yang tajam. Kritik dilontarkan ke publik secara lugas (bahasa Jawa: tanpa tedeng aling-aling). Mencermati perkembangan politik dunia Muslim di belahan Timur Tengah dan Asia Selatan, tanpa ragu Buya melontarkan kritik dengan mengatakan bahwa fenomena Sunni dan Syi’iy yang selalu tidak akur dan penuh pertengkaran dan percekcokan, untuk tidak menyebutnya selalu menyulut konflik berdarah seperti yang dipertontonkan oleh gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), Negara Islam di Irak dan Siria, Saudi Arabia vs Yaman dan lainnya, dengan tegas Buya menyebut bahwa keduanya, baik Sunni maupun Syi’iy adalah produk sejarah belaka yang tidak harus diikuti dengan begitu saja, tetapi produk sejarah yang harus dikoreksi dan diperbaiki. Ketika melihat gelagat Front Pembela Islam (FPI) di tanah air yang semakin ganas dan menjadi-jadi karena pemerintah tidak mengambil sikap yang tegas, maka Buya mengeluarkan pernyataan yang sangat berani bahwa anggota FPI dan sejenisnya yang rajin melakukan sweeping adalah “Preman Berjubah”.[16] Dengan kritik dan pernyataan-pernyataan seperti itu Buya tidak gentar, tidak takut untuk dikucilkan oleh warga masyarakat Muslim. Beberapa tahun kemudian, pemerintah baru mengambil sikap tegas dengan cara membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).[17]
Tidak hanya perilaku internal umat Islam yang dianggap tidak elok dan tidak pantas yang Buya kritik, tapi juga keluar. Penjajahan, penindasan, dan rasisme adalah daki peradaban yang harus dilenyapkan dari muka bumi.[18] Mengapa Buya bersikap kritis seperti itu? Selain beliau ingin menegakkan kaidah al-Qur’an, “al-amru bil ma’ruf wa al-nahyu ‘an a-mungkar” (menganjurkan berbuat baik dan mencegah tindakan mungkar), juga kalau kita mengikuti penjelasan Omid Safi, bahwa salah satu ciri dan tugas Muslim Progresif adalah memang untuk melontarkan kritik dan pertimbangan dari berbagai perspektif. Bukan Muslim progresif, jika enggan dan tidak melontarkan kritik dan menyampaikan pertimbangan yang bercorak multiple-exist critique. Saya kutip, agak sedikit panjang:
“… It means openly and purposefully resisting, challenging, and overthrowing structures of tyranny and injustice in these societies. At a general level it means contesting injustice of gender apartheid (practiced by groups such as Taliban) as well as presecution of religious and ethnic minorities (undertaken by Saddam Hussein agains the Kurds, etc.). It means exposing the violation of human rights and freedom of speech, press, religion, and the right to dissent in Muslim countries such as Saudi Arabia, Turkey, Iran, Pakistan, Sudan, Egypt, and others. More specifically, it means embracing and implementing a different vision of Islam than that offered by Wahhabi and neo-Wahhabi groups. A vital corollary component of our multiple critique entails standing up to increasingly hegemonic Western political, economic, and intellectual structures that perpetuate an unequal distribution of resources around the world. This hegemony comprises a multitude of forces, among them the oppressive and environmentally destructive forces of multi-national cooperations whose interest are now linked with those of neo-imperial, uniliteral governments. … that put profit before human rights, and “strategic interest” before the dignity of every human being”.[19]
Pada prinsipnya, Muslim progresif secara tegas menolak, menentang dan membuang jauh-jauh perbuatan dan sikap tirani dan ketidakadilan dalam masyarakat. Terlibat aktif dalam menentang ketidakadilan gender seperti yang dipraktikkan oleh Taliban, juga persekusi terhadap kelompok minoritas etnis dan agama seperti yang dilakukan oleh Saddam Hussein terhadap suku Kurdi. Menentang dan menolak dengan tegas pelanggaran hak-hak asasi manusia, tindakan menghalang-halangi kebebasan berbicara, press, agama, dan hak untuk berbeda pendapat di negara-negara Muslim seperti Saudi Arabia, Turki, Iran, Pakistan, Sudan, Mesir dan lainnya. Terlebih khusus lagi, menerapkan cara pandang atau visi keislaman yang sangat berbeda dari visi, sikap dan cara pandang yang dipraktikkan kelompok Wahhabi dan Neo-Wahhabi. Komponen penting lain dari kritik berlapis yang dilihat dari berbagai sudut pandang (multiple critique) yang dilakukan oleh Muslim progresif adalah berdiri tegak menentang semakin hegemoniknya Barat dalam kehidupan politik, ekonomi dan intelektual yang berakibat pada distribusi sumber daya alam yang tidak adil di seluruh dunia. Cengkeraman hegemoni tersebut melibatkan kekuatan-kekuatan besar korporasi multi-nasional yang berdaya rusak tingkat tinggi terhadap lingkungan hidup. Perusahaan multi-nasional lebih mengedepankan keuntungan (profit) dari pada menghargai hak-hak asasi manusia, lebih mendahulukan kepentingan strategis dari pada menghormati harkat dan martabat setiap manusia. (Bersambung)
Disampaikan dalam Syafii Maarif Memorial Lecture (SMML), Maarif Institute, Salihara Art Center, Jakarta, 5 Juli 2022
[1]Satu tahun sebelum Buya wafat, telah terbit 2 buku ditulis para aktivis muda dalam rangka memperingati 85 tahun usia Buya. Pertama, David Krisna Alka dan Asmul Khairi (Ed.), Mencari Negarawan. Sosok dan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, April 2022. Kedua, Aulia Taarufi & Prima Sulistya dkk. (Ed.), Ibu Kemanusiaan. Catatan-catatan Perempuan untuk 86 tahun Buya Ahmad Syafii Maarif, Yogyakarta: Penerbit Buku Langgar, 2021.
[2]http://rmaward.asia/?s=ahmad+syafii+maarif. Menurut dewan juri penghargaan tersebut diberikan karena Buya Syafii mempromosikan kemajemukan masyarakat Indonesia dan prinsip nonsektarian Pancasila di tengah-tengah arus kuat tarikan fundamentalisme Islam.
[3]Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009. Buku ini telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan diterbitkan oleh Leiden University Press, Belanda, dengan judul Islam, Humanity and Indonesian Identity. Reflection on History, Leiden: Leiden University Press, 2018. Setahun kemudian, juga diterbitkan oleh NUS Press, Singapur, tahun 2019, dengan judul yang sama, Islam, Humanity and Indonesian Identity.
[4]Buku Fazlur Rahman, Islam, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Salman ITB, Bandung tahun 1984. Terbitan Indonesia diberi kata pengantar oleh Ahmad Syafii Maarif dengan judul “Fazlur Rahman, al-Qur’an dan Pemikiran Islam”.
[5]Sebagai perbandingan Hajriyanto Y. Thohari, “K.R.T. Radjiman, Bung Hatta, dan Buya Syafii”, dalam David Krisna Alka, Asmul Khairi (Ed.), Mencari Negarawan …, h.15. Fajar Riza Ul Haq, “Muslim Puritan Pembela Pancasila”, dalam Mencari Negarawan …, h. 85. Abd. Rohim Ghazali, “85 Tahun Ahmad Syafii Maarif: Cermin Berjalan Demokrat Sejati”, dalam Mencari Negarawan …, h. 74. Yudi Latif, “Guru Bangsa Berpulang”, Kompas 28 Mei 2022, h. 6.
[6]Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980.
[7]Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, Chicago: The University of Chicago Press, 1982. Telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Pustaka, Bandung, tahun 1985. Diberi kata pengantar oleh Ahmad Syafii Maarif. Semula Fazlur Rahman berharap Buya sendiri yang menerjemahkan seperti termaktub dalam suratnya tertanggal 30 Oktober 1982, tapi dengan pertimbangan keterbatasan waktu, Buya menyerahkan ke Pustaka Salman ITB, Bandung. Hasil terjemahan Pustaka Bandung kemudian dibaca sendiri oleh Buya dengan memberi catatan perbaikan disana sini. Lebih lanjut lihat Kata Pengantar buku.
[8]Sumanto Al-Qurtuby, “ Humanisme Islam Buya Syafii”, Kompas, 10 Juni 2022.
[9]Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 28/SK-PP/I-A/2.a/1995, 12 Nopember 1995, dalam BRM No. 03/1995-2000 Rajab 1416/Desember 1995.
[10]Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, PP. Muhammadiyah, Tafsir Tematik Al-Qur’an tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama, Yogyakarta, Pustaka SM, 2000.
[11]Dunia Islam umumnya dan Indonesia khususnya tidak begitu sadar adanya perkembangan baru dalam pemikiran Islam yang disebut oleh Abdullah Saeed sebagai The Islamist Extremist. Publik umumnya baru sadar bahwa memang ada genre pemikiran Islam baru, yang bercorak “Extremist” setelah tahu dan menyaksikan melalui televisi dan media sosial adanya ledakan bom di berbagai tempat di dunia dan juga bom bunuh diri di berbagai tempat. Di Indonesia, istilah populer yang digunakan untuk genre The Islamist Extremists ini adalah Jihadis. Selebihnya, dengan nuansa yang tidak seekstrim golongan The Islamist Extremists, ada istilah-istilah lain yang digunakan seperti Tahriri, Salafi, Tarbawi, Islamisme Populer. Lebih lanjut, Noorhaidi Hasan (Ed.), Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi, Yogyakarta: Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Press, 2018, khususnya Bab 1 dan 8. Terlebih halaman 274. Juga MAARIF Institute, Menjaga Benteng Kebinekaan di Sekolah: Studi Kebijakan OSIS di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon, 2018; Eko Riyadi & Despan Heryansyah (Ed.), Optimalisasi Peran FKUB: Mewujudkan Indonesia Damai, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2018.
[12]Abdullah Saeed, Islamic Thought: An Introduction, London and New York, Routledge, 2006, h. 142-50. Untuk lebih detil, dapat juga dibaca Omid Safi (Ed.), Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism, Oxford, Oneworld Publications, 2003. Tariq Ramadan juga menengarai ada 6 kecenderungan pemikiran Islam abad akhir abad ke 20 dan abad ke 21, yaitu Scholastic Traditionalism, Salafi Literalism, Salafi Reformism, Political Literalist Salafism, Liberal or Rational Reformism, dan Sufism. Lebih lanjut Tariq Ramadan, Western Muslims and the Future of Islam, New York: Oxford University Press, 2004, h. 24-28. Kategorisasi dan klasifikasi trend pemikiran Islam oleh Saeed dan Tariq Ramadan ini memang berbeda dari yang biasa dikenal di tanah air tahun 80an, ketika para ilmuan lebih menekankan pada perbedaan antara Traditionalism dan Modernism, yang kemudian muncul dalam nama mata kuliah seperti Aliran Modern dalam Islam (Modern Trend in Islam).
[13]Melihat pentingnya mengkaji dan meneliti secara berkelanjutan persoalan stagnasi metodologi dalam studi keislaman kontemporer, lebih lanjut M. Amin Abdullah, “Islam as A Cultural Capital in Indonesia and the Malay World: A Convergence of Islamic Studies, Social Sciences and Humanities”, Journal of Indonesian Islam, Volume 11, Number 02, December 2017, h. 307-325. Juga Multidisiplin, Interdisiplin & Transdisiplin. Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer, Yogyakarta: IB. Times, 2020.
[14]Aulia Taarufi & Prima Sulistya (ED.), Ibu Kemanusiaan. Catatan-catatan Perempuan untuk 86 tahun Buya Ahmad Syafii Maarif, Yogyakarta: Penerbit Buku Langgar bekerjasama dengan SaRang Building, 2021, 330 halaman.
[15]Abdullah Saeed, Interpreting the Qur’an. Towards a contemporary approach, New York: Routledge, 2006, bagian 12, Epilogue, h. 145-154. Menurut al-Jabiri, metode lama yang menghambat pengembangan metodologi studi Islam, dideskripsikan sebagai metode yang mencukupkan diri hanya dalam ruang lingkup kajian teks dengan pendekatan Bayani, minus pendekatan Burhani. Lebih lanjut Muhammad Abid al-Jabiry, Bunyah al-’Aql al-Araby: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li Nudzum al-Ma’rifah fi al-Tsaqafah al-Arabiyyah, Bairut: Markaz Dirasaat al-Wihdah al-Arabiyyah, 1986. Menurutnya, epistemologi Bayani hanya akan memperkuat hegemoni nash atau lafdz (sulthatu al-lafdz), hegemoni al-asl (sulthatu al-asl atau al-Salaf) dan hegemoni sikap dan pandangan yang serba permisif-serba boleh; tidak mengenal dan tidak mengakui hukum kausalitas seperti yang umum dijumpai dalam ilmu pengetahuan (sulthatu al-tajwiz), h. 560-1.
[16]Ahmad Syafi’i Maarif, “Preman Berjubah”, Republika, 9 Agustus 2005.
[17]Pada tanggal 19 Juli 2017 pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan HAM secara resmi mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Kemudian, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam, 30 Desember 2020.
[18]Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan …, h. 20.
[19]Omid Safi (Ed.), Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism, Oxford: Oneworld Publications, 2003, h. 2-3.