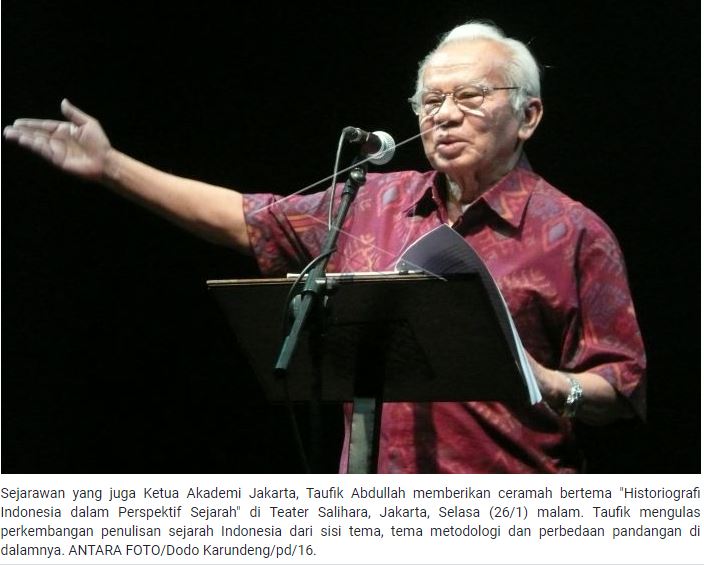Mendengar Dr. Taufik Abdullah punya acara di kampus UGM, saya mendatanginya. Itu bulan Juli, 1984. Saya ingin mewawancarainya sebagai wartawan Himmah, majalah kampus UII pengganti Muhibbah, yang dibredel 1982. Ini merupakan niat yang nekat. Saya bukan hanya tahu reputasi tingginya sebagai sejarawan, tapi juga mendengar sikapnya yang sering tak sabar terhadap lawan bicara — apalagi wartawan! — yang “kurang nyambung”.
Tapi saya, mahasiswa Fakultas Hukum tahun ke-3, memberanikan diri — bayangan berjumpa dan punya kesempatan menginterviu ilmuwan sosial ternama itu mengalahkan rasa gentar. Saya menyiapkan diri untuk ditanggapinya dengan ketus atau bahkan dibentak untuk pertanyaan bodoh saya. Atau untuk tanggapan balik yang meleset atas keterangan awal yang saya akan minta penjelasan lanjutannya.
Taufik Abdullah, yang menulis skripsi S1 di UGM dalam bahasa Inggris, terhitung jarang menulis, apalagi di koran harian. Ia lebih banyak mengedit buku antologi, menulis pengantar buku-buku orang lain. Belakangan (1994) ia ikut meredaksi dan menulis pengantar yang mengesankan, untuk kumpulan “Manusia dalam Kemelut Sejarah” — sebuah tema di satu edisi majalah Prisma, parameter perkembangan ilmu sosial kala itu, yang kemudian dibukukan dan banyak diminati pembaca. Buku itu berisi catatan biografis tentang tokoh-tokoh bangsa seperti Haji Agus Salim, Sutan Sjahrir, Abi Hanifah, dll., yang ditulis oleh para penulis seperti Mangunwijaya.
Saya bahkan tak pernah membaca tulisan Pak Taufik sendiri di Prisma; tapi pendapat-pendapatnya sering muncul di jurnal itu dalam galeri opini. Pandangan-pandangan ringkasnya di sana selalu menarik, mendalam dan mengajukan perspektif baru — misalnya tentang peran dan fungsi perguruan tinggi pada edisi Prisma 1976.
Sore itu di kampus UGM, selepas sebuah sesi seminar, saya mendatangi the famous scholar. Dia langsung menerima permintaan wawancara mendadak itu dengan ringan, lalu menjawab panjang-lebar semua pertanyaan saya; rasa-rasanya kebanyakan pertanyaan itu dikualifikasinya dulu supaya jelas maksudnya (dan karena itu baru bisa dijawab dengan layak!). Di luar dugaan, ia tak segarang kesan yang saya dengar — tapi sepintar yang saya tahu.
Saya lupa apa saja isi wawancara panjang itu, yang saya transkripsi sendiri menjadi 25 halaman ketikan, dan dimuat nyaris utuh sepanjang 8 halaman majalah. Beberapa bulan kemudian kami berjumpa lagi, dan dengan berdebar saya tanyakan pendapatnya tentang catatan wawancara itu; berapa banyak yang meleset. Ia menjawab spontan: “Bagus! Hanya ada satu salah-cetak,” katanya. “Anda menulis basiclly. Mestinya basically. Tapi itu cuma kesalahan yang sangat kecil. Tidak berarti. Secara keseluruhan, bagus!”
Pulang ke kamar indekos, saya periksa lagi wawancara itu. Benar. Saya menulis ucapannya dengan keliru. Mestinya basically. Betapa cermat ia memeriksa, dan betapa tajam daya ingatnya. Dan saya jengkel. Sejumlah frase asing yang dikemukakannya saya tulis dengan akurat, mengapa untuk sebuah adverb yang tak penting itu saya malah meleset?
Dari wawancara yang cukup panjang itu, saya hanya ingat satu hal saja: ia meramalkan bahwa masyarakat kita akan mengalami diferensiasi sosial yang makin kaya. Ia memberi catatan khusus tentang keulamaan. Para ulama, kiai, ustad, katanya, akan semakin profesional. “Mereka akan berperilaku seperti semua profesi lain, misalnya artis, olahragawan, manajer perusahaan, dan lain-lain,” katanya.
Waktu itu saya tidak mengerti; bahkan cenderung tak setuju dengan pandangannya yang “meremehkan” kaum ulama dan ustad — dengan menyamakan mereka dengan profesi-profesi duniawi seperti bintang film dan atlet. Tapi sejak itu pernyataan Pak Taufik menancap di benak saya.
Bertahun-tahun kemudian, setiap menyaksikan gejala profesionalisasi ulama itu di televisi dan ceramah-ceramah umum, saya teringat ramalannya itu — yang tiap hari terasa kian terbukti.
Para ustad tampil di layar televisi dengan semua elemen dan marketing gimmick yang sama dengan artis penghibur. Kostum mereka diatur rapi, yel-yel dikarang oleh produser program TV untuk diteriakkan oleh hadirin di studio, sapaan oleh sang ustad kepada hadirin maupun pemirsa di rumah dibakukan dan dijadikan ciri khasnya (“jamaah rahimakumullah”, “kawula muda”, “bro and sis”, dll; tiap penceramah punya sapaan khas masing-masing; duplikasi akan dipandang sebagai skandal unprofessional yang memalukan).
Elemen profesional lainnya: honor besar. Para ustad berlomba-lomba mendesakkan diri untuk bisa tampil di layar TV; mereka sibuk melobi produser sebagai penguasa program. Jika mereka mujur dan kemudian terkenal, tingkat honor akan naik pesat dalam ceramah off air, terutama di daerah-daerah, yang warganya gandrung pada bintang TV apa saja dari ibukota, dan mendambakan para selebriti religius itu bisa hadir di kampung halaman mereka.
Honor besar juga siap mereka terima untuk nasihat perkawinan anak pejabat tinggi atau pengusaha kaya; atau untuk tausiyah dalam tahlilan orang terpandang.
Taufik Abdullah telah membekali saya dengan kacamata yang tajam untuk melihat profesionalisasi ulama — yang terus saya ingat, hingga 36 tahun sesudah saya mendengarnya pertama kali. Tanpa perspektifnya itu, saya rasa saya tak kunjung mampu menamai gejala ini — padahal, tanpa diberi nama, tanpa menggunakan kerangka teori, gejala apapun tidak akan banyak maknanya, sebab orang tidak akan pernah mampu mengidentifikasinya dengan jelas.
Studi mendalam Taufik Abdullah terhadap sejarah, saya pikir, telah membuatnya mampu mendeteksi suatu gejala sosial dengan tajam, sebab historiografi memang persis mempelajari hal itu — mempelajari tendensi atau kecenderungan sosial yang akan menuju pada kondisi tertentu, jika tendensi itu berlanjut. Pada 1984 itu ia, yang menulis disertasi tentang gerakan kaum muda di Minangkabau, di Universitas Cornell, Amerika, rupanya sudah mendeteksi tendensi profesionalisasi ulama tersebut, meskipun para ustad belum banyak tampil di televisi, dan waktu itu hanya ada TVRI (RCTI sebagai stasiun swasta baru muncul 1989).
Ia mempelajari sejarah sebagai historiografi, bukan hagiografi (melihat aneka peristiwa hanya dari aktor-aktor besar, bahkan disertai semangat mengagungkan aktor-aktor itu), apalagi sekadar sebagai kronik peristiwa (seorang pangeran Jawa melawan Belanda dari tahun sekian sampai tahun sekian; seorang nabi di jazirah Arab membawa pengikutnya hijrah tahun sekian, dsb).
Barangkali Taufik Abdullah sepakat dengan Denys Lombard, sejarawan Prancis yang menulis trilogi sejarah Jawa. Kepada seorang kawan yang minta saran tentang jurusan yang harus dimasuki anaknya di perguruan tinggi, Lombard menyarankan agar anak itu belajar sejarah. “Satu-satunya ilmu (sosial) yang penting adalah sejarah,” katanya. *