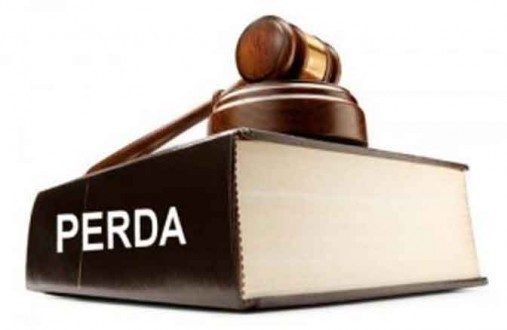Kebijakan Bupati Gowa yang akan memecat ASN (Aparatus Sipil Negara) yang bekerja di lingkungannya yang buta aksara al-Qur’an membuat kita sadar jika syariatisasi di daerah-daerah masih dan sedang berjalan. Bagaimana seorang ASN itu bisa dipecat karena dia tidak bisa baca al-Qur’an, bukankah ketidakbisaan baca al-Qur’an itu sesuatu yang tidak menjadi syarat menjadi ASN?
Ya, sejak Jokowi menjadi presiden, pembicaraan tentang gerakan penyusunan Perda bernuansa yariah atau Perda bernuansa agama di daerah-daerah tidak begitu mendapat perhatian. Hal ini bukan berarti gerakan Perda atau aturan-aturan daerah berdasarkan syariah itu berhenti sama sekali. Beberapa gerakan di beberapa daerah tentang tetap berjalannya penegakan hukum atau aturan bernuansa syariah misalnya mengejutkan kita. Termasuk kejutan yang diberikan oleh Bupati Gowa di atas.
Sebenarnya, peringatan tentang maraknya gerakan penyusunan Perda bernuansa keagamaan sudah lama diingatkan oleh pelbagai kalangan di Indonesia. Komnas Perempuan misalnya pernah menghitung jika jumlah Perda Syariah sudah mencapai ratusan yang terjadi di banyak tempat.
Pada tahun 2018, Komnas Perempuan pernah menyatakan jika ada 421 Perda yang diskriminatif termasuk mayoritas disebabkan oleh Perda-perda bernuansa syariah. Ini artinya, meskipun dalam pemerintahan Jokowi Perda diskriminatif ini tidak mengemuka ke permukaan, namun dari segi jumlah ternyata masih banyak.
Dalam membuat Perda bernuansa syariah ini memang tidak begitu saja dinamakan dengan istilah “perda syariah” secara langsung, namun dibungkus dengan penamaan-penamaan yang lain. Misalnya Perda tentang pendidikan di mana di dalamnya literasi baca al-Qur’an, ada perda tentang pelarangan minuman keras dimana di dalamnya bisa melibatkan kelompok tertentu untuk melakukan razia minuman keras dlsb. Penamaan ini tidak begitu saja terjadi, namun ini bagian dari strategi untuk syariatisasi untuk mayoritas wilayah non-Muslim, dan juga strategi Kristenisasi untuk daerah-daerah Kristen dan Hinduisasi untuk daerah-daerah Hindu. Namun, masalah ini pada mulanya banyak dimulai oleh daerah-daerah Islam yang memang merupakan agama mayoritas.
Pangkal persoalan perda-perda bernuansa syariah dan keagamaan ini sebenarnya sudah bisa dikenali sejak lama, yakni otonomi daerah. Pemerintah daerah melalui undang-undang memiliki hak untuk mengatur pemerintahan mereka, ada beberapa pengecualian termasuk di dalamnya agama. Meskipun agama jelas tidak boleh diatur oleh pemerintah daerah, namun pada kenyataannya, agama diinstrumentalassi oleh aktor-aktor daerah.
Menurut Michael Buehler, agama dijadikan sebagai pendongkral elektoral kepemimpinan politik di daerah. Sebuah daerah misalnya mengajukan Perda bernuansa syariah, katakanlah peningkatan literasi al-Qur’an, ini bukan untuk literasi al-Qur’an itu sebagai tujuan akhirnya, namun untuk tujuan politik elektoral. Kepentingan jelas, bahwa agar di Pilkada depan pihaknya bisa terpilih lagi. Jalan untuk menjadi populer dan diterima rakyat adalah dengan cara instrumentalisasi agama. Hal ini bisa terjadi, karena menurut beberapa studi, justru yang banyak memainkan isu ini adalah pemimpin-pemimpin daerah yang didukung oleh partai-partai nasionalis.
Kita mengira jika gerakan ini berhenti paling tidak berkurang ketika Jokowi berkuasa. Mengapa? Karena pada saat itu pemerintahan Jokowi memiliki komitmen untuk melakukan sinkronisasi peraturan-peraturan daerah dengan peraturan nasional. Jokowi sebenarnya sudah tahu bahwa kita memiliki aturan yang saling bertabrakan yang jumlahnya mencapat 3000 lebih. Bahkan sejak Gus Dur menjadi presiden hal seperti ini terus dikemukakan.
Karena masalahnya sudah ketahuan, maka kita berharap bahwa Jokowi dalam pemerintahan keduanya, melaksanakan janjinya. Mengapa janji ini perlu dilakukan cepat, karena fenomena perda bernuansa syariah bukan hanya sekedar fenomena ketidaksinkronan peraturan nasional dan daerah saja, namun ini merupakan bibit dari benturan ideologi nasional. Benturan ideologi ini tidak sekedar benturan ideologi, namun bisa mengarah pada disintegrasi bangsa. Kita tahu bahwa, sebagai bangsa, kita sudah memiliki kerangka baku tentang peraturan nasional dan daerah yang harus saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain. Karenanya, dengan bekal ini, perda bernuansa syariah atau agama lain, harusnya bisa dituntaskan.
Selama ini kita hampir lengah dalam melihat masalah ini. Kita harus bangkit lagi melihat bahwa dengan peristiwa Goa ternyata masalah perda bernuansa syariah memang belum benar-benar selesai. Kita tidak mau bahwa dalam diam gerakan ini lalu menjadi mainstream dan kita telat untuk menghentikannya.
Kita tidak boleh lengah karena perda bernuasa syariah atau agama lain memang benar-benar memiliki pendukung militannya, meskipun mungkin itu tidak besar. Meskipun kecil tapi kalau tidak ada gerakan counternya, maka masyarakat mayoritas yang tadinya berada pada pihak yang netral atau bahkan tidak bisa tergerus untuk mendukung gerakan itu karena informasi yang datang kepada mereka adalah hanya informasi dari kelompok pro-perda bernuansa syariah.
Ada hal penting lainnya, mengapa kita harus “alert” pada masalah cripping shariatisation (syariah yang merangkak) karena kecenderungan radikalisme di daerah-daerah itu cukup mengalami peningkatan. Jika fenomena ini dibiarkan maka bisa jadi peraturan-peraturan daerah itu akan menjadi semacam alat pelindung bagi gerakan radikalisme dan esktremism di daerah. Kita tidak memiliki alasan lain kecuali kita cepat menyelesaikan persoalan konflik peraturan nasional dan daerah di atas yang membawa dampak multi-komplek ini.
Sebagai catatan, fenomena Bupati Gowa memberikan peringatan kepada kita bahwa gerakan memasukkan agama ke dalam peraturan daerah tidak berhenti. Gerakan terus tetap jalan. Jika terlihat seolah-olah gerakan itu berhenti, maka hal itu terjadi karena kita sendiri yang berhenti memperhatikan masalah itu.