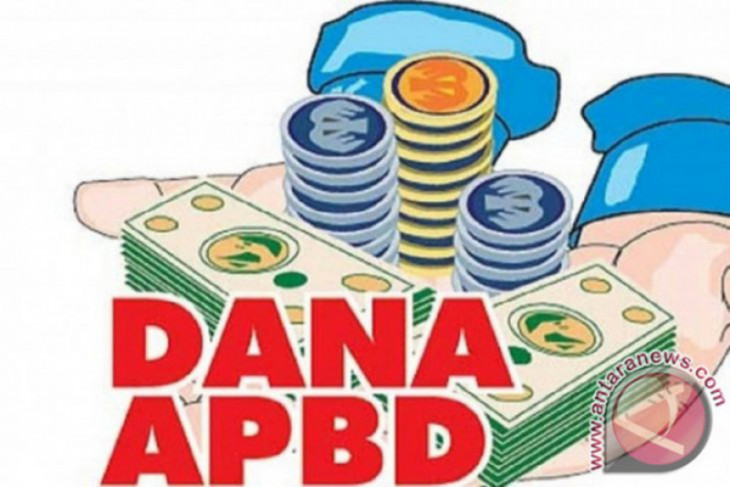Rp234 triliun dana pemerintah daerah yang mengendap di bank bukan sekadar angka fiskal. Ia adalah cermin dari kondisi psikologis birokrasi kita yang terbelenggu oleh ketakutan, kehati-hatian patologis, dan kepemimpinan yang kehilangan arah. Fenomena ini mencerminkan pilihan kolektif untuk tetap “aman” daripada berinovasi, sebuah gejala psikopolitik yang meresap dalam struktur kekuasaan.
Di balik alasan teknis seperti perencanaan yang lemah atau prosedur yang rumit, tersembunyi ketakutan sistemik. Dalam The Burnout Society (Byung-Chul Han, 2015), masyarakat modern digambarkan sebagai entitas yang lelah secara psikis, di mana tekanan internal untuk tampil bersih dan bebas masalah menggantikan tekanan eksternal yang bersifat disipliner.
Dalam konteks birokrasi, menggunakan anggaran berarti mengambil risiko, dan risiko berarti potensi kesalahan yang bisa berujung pada pemeriksaan atau ancaman terhadap karier. Maka, membiarkan dana mengendap menjadi pilihan yang secara psikologis lebih nyaman.
Robert Jackall dalam Moral Mazes: The World of Corporate Managers (1988) menjelaskan bahwa dalam organisasi yang kaku, moralitas bergeser dari “apa yang benar” menjadi “apa yang aman bagi atasan dan posisi saya”. Di pemerintahan daerah, menyerap anggaran untuk program substansial bisa jadi benar secara etis, namun berisiko secara politik. Akibatnya, dana lebih sering disimpan untuk kepentingan mendesak pimpinan atau dialihkan ke proyek yang menarik perhatian media, bukan ke perbaikan sekolah atau drainase yang tak populer.
Dalam The Psychology of Money (Adrian Furnham, 2014), uang dalam institusi publik bukan hanya alat transaksi, melainkan simbol kekuasaan. Mengendalikan alirannya berarti menjaga cadangan pengaruh. Setiap rupiah yang tidak digunakan menjadi potensi alat tawar politik, bisa digerakkan saat dibutuhkan untuk membangun loyalitas atau meredam konflik internal.
Kepemimpinan birokrasi pun turut memperparah situasi. Alih-alih menciptakan “keamanan psikologis” seperti yang dikembangkan Amy Edmondson dalam The Fearless Organization (2018), banyak pemimpin justru mengadopsi gaya transaksional yang penuh kecurigaan. Dalam model Laissez-Faire Leadership yang merupakan bagian dari Transformational Leadership Theory (Bass & Avolio, 1994), pemimpin semacam ini cenderung menghindar, tidak memberi arahan jelas, dan enggan mengambil tanggung jawab. Akibatnya, anggaran dibiarkan mengendap tanpa tekanan konstruktif dari atas.
Ketakutan patologis dalam pengambilan keputusan menjalar seperti virus, melumpuhkan sistem saraf organisasi. Transparansi dan akuntabilitas berubah menjadi ritual kosong. Laporan keuangan yang tebal dan rumit justru menyembunyikan masalah, bukan mengungkapnya. Masyarakat sipil dan media, yang seharusnya menjadi penyeimbang, kesulitan menavigasi labirin istilah anggaran yang tidak ramah. Sistem ini tampak akuntabel secara formal, namun kosong secara substansial—sebuah tiruan tata kelola yang hanya indah di atas kertas.
Dalam ruang birokrasi yang kehilangan arah ini, praktik kolusi dan penggelembungan anggaran menemukan celahnya. Dorothy Leidner dalam The Psychology of Corruption (2018) menyebut bahwa korupsi jarang lahir dari niat besar. Ia tumbuh dari pembiaran terhadap penyimpangan kecil yang dianggap lumrah. Ketika anggaran disusun tanpa tujuan program yang jelas—fenomena yang dikenal sebagai incremental budgeting—terbuka ruang kosong yang mudah diisi oleh kepentingan kelompok.
Fenomena groupthink yang dikaji Irving Janis dalam Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes (1982) menunjukkan bagaimana tekanan sosial dalam tim bisa membungkam suara kritis. Ketika pemimpin memberi sinyal bahwa “yang penting laporan lancar” atau “cari dana operasional yang tidak tercatat”, anggota tim cenderung menyesuaikan diri. Mereka yang jujur memilih diam karena takut dikucilkan. Terbentuklah ilusi kesepakatan, di mana keputusan kolektif untuk menahan atau menaikkan anggaran demi kepentingan kelompok dianggap sah, bahkan “demi kebaikan bersama”.
Elisabeth Noelle-Neumann dalam The Spiral of Silence: Public Opinion – Our Social Skin (1984) menjelaskan bahwa suara mayoritas yang sebenarnya pasif sering kali dianggap sebagai kebenaran dominan. Dalam suasana ini, anggaran menjadi alat kolusi yang dibungkus dengan narasi kebersamaan, padahal berakar pada ketakutan dan kepentingan sempit.
Lalu, bagaimana keluar dari labirin psikologis ini?
Pertama, diperlukan intervensi psikopolitik melalui perombakan sistem insentif. Pemerintah pusat dan lembaga pengawas harus mengubah paradigma dari menghukum kesalahan menjadi memberi penghargaan atas keberanian dan kecepatan. Insentif, baik material maupun simbolik, harus diberikan kepada mereka yang menyerap anggaran dengan dampak nyata dan proses transparan. Ini sejalan dengan teori Operant Conditioning dari B.F. Skinner dalam Science and Human Behavior (1953), yang menekankan pentingnya penguatan perilaku positif dalam organisasi.
Kedua, pelatihan kepemimpinan harus bertransformasi. Kepala daerah dan timnya perlu dibekali mentalitas pelayanan, bukan dominasi. Kepemimpinan yang mampu menciptakan ruang aman secara psikologis akan mendorong inovasi dan keberanian dalam pengelolaan anggaran. Studi Edmondson (Harvard Business School, 1999) menunjukkan bahwa tim dengan tingkat keamanan psikologis tinggi memiliki performa inovatif yang lebih baik.
Ketiga, transparansi harus disajikan secara ramah dan mudah diakses. Diperlukan platform digital yang mampu memvisualisasikan aliran dana hingga ke tingkat desa, dengan tampilan yang bisa dipahami masyarakat umum. Studi dari Open Government Partnership (OGP, 2021) menunjukkan bahwa visualisasi anggaran yang mudah dipahami meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat akuntabilitas lokal.
Dana Rp234 triliun yang tidak terpakai bukan hanya soal efisiensi fiskal, melainkan soal keberanian untuk membebaskan birokrasi dari belenggu ketakutan. Ia adalah cermin dari jiwa organisasi yang terperangkap dalam zona nyaman, kepemimpinan yang menghindar, dan budaya kolusi yang halus namun merusak.
Untuk mengalirkannya, dibutuhkan lebih dari sekadar instruksi. Diperlukan terapi kolektif: keberanian untuk mengubah sistem insentif, membangun kepemimpinan yang aman secara psikologis, dan menciptakan transparansi yang bisa diakses publik. Hanya dengan itu, dana rakyat bisa mengalir ke sungai pembangunan yang hakiki—yang memanusiakan dan memakmurkan.